MK dan Pilihan Sistem Pemilu
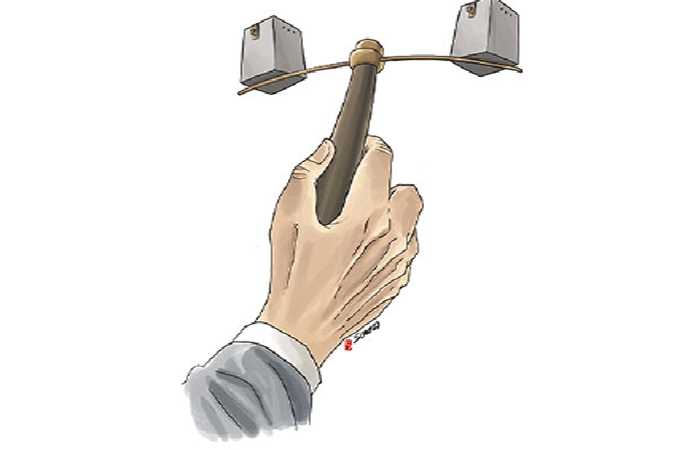
DALAM catatan Andrew Reynolds dkk (2005), secara tradisional sistem pemilu jarang dipilih dengan sadar dan sengaja. Meskipun desain sistem pemilu yang disengaja telah semakin umum akhir-akhir ini, sering kali pilihan atas sistem pemilu ialah suatu kebetulan. Hasil dari kombinasi keadaan yang tidak biasa, dari tren yang lewat, atau kekhasan sejarah, dengan dampak kolonialisme dan pengaruh negara tetangga yang acap kali sangat kuat.
Pandangan serupa juga dikemukakan Allen Hicken (2019), yang menyebut ada tiga kondisi yang melahirkan inisiasi untuk mereformasi sistem pemilu, meliputi kegagalan sistemis (systemic failure), sebuah peristiwa katalitik (a catalytic event), dan adanya perubahan preferensi petahana (change in incumbents’ preference). Kegagalan sistematis terjadi apabila sistem pemilu yang sedang berlaku gagal memenuhi harapan normatif publik untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan efektif.
Sementara itu, peristiwa katalitik yang mendorong perubahan sistem pemilu umumnya berupa suatu krisis yang menghubungkan antara kesengsaraan politik dan/atau ekonomi dan sistem pemilu yang kemudian menghasilkan permintaan untuk melakukan reformasi. Reformasi sistem juga bisa terjadi karena politikus petahana merasa akan mendapatkan keuntungan dengan mendorong perubahan sistem (atau setidaknya dengan tidak menentangnya), dengan petahana meyakini akan mendapatkan manfaat elektoral secara jangka panjang melalui keberlakuan sistem pemilu yang baru tersebut. Atau sebaliknya, petahana mengharapkan keuntungan elektoral jangka pendek dari pilihan sikap sebagai pembaharu (dikenal sebagai ‘motivasi tindakan’).
Yudisialisasi politik
Di Indonesia, sistem pemilu, selain merupakan produk pergulatan pembentuk undang-undang sebagai refleksi sejarah penyelenggaraan pemilu terdahulu (terutama pemilu-pemilu Orde Baru), dipengaruhi adanya peran putusan pengadilan melalui upaya pengujian undang-undang (judicial review), ataupun penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Kekuatan Bahasa Ibu Sehebat Ibu berbahasaKeberadaan MK dalam rangka mengukuhkan pemisahan kekuasaan dan kontrol antarcabang kekuasaan (checks and balances) memang memungkinkan para pihak untuk melakukan penilaian dan mengambil langkah hukum atas norma undang-undang yang dianggap inkonstitusional, atau bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945. Hal itu mengakibatkan menguatnya fenomena yudisialisasi politik dengan hakim dan peradilan ditarik masuk untuk memutuskan persoalan-persoalan politik dalam pengaturan pemilu Indonesia selanjutnya.
Pasca-Pemilu 1999, pembentuk undang-undang memutuskan untuk mengubah sistem pemilu proporsional daftar tertutup (closed list) untuk memilih anggota DPR dan DPRD sehingga pemilih bisa langsung mencoblos caleg pilihannya di surat suara. Surat suara tidak hanya akan memuat nomor urut dan tanda gambar partai, tapi juga memuat nomor urut dan nama caleg yang diusung partai. Namun, pada Pemilu 2004 melalui UU No 12 Tahun 20023, hal itu masih dilakukan melalui penerapan sistem proporsional terbuka yang relatif tertutup (relatively closed open list system) dengan caleg akan menduduki kursi yang diperoleh partai apabila mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut bilangan pembagi pemilih atau BPP.
BPP sendiri diperoleh melalui penjumlahan total suara sah di suatu daerah pemilihan yang kemudian dibagi dengan total jumlah kursi yang diperebutkan di dapil tersebut. Hasil pembagian itulah yang menjadi kuota harga kursi yang harus dipenuhi caleg untuk bisa duduk di parlemen. Kalau tidak ada caleg yang memperoleh suara sejumlah BPP, kursi akan diberikan kepada caleg berdasar nomor urut. Jika partai mendapat dua kursi, dua kursi tersebut akan diberikan kepada caleg nomor urut satu dan nomor urut dua yang diusung partai tesebut.
Mekansime seperti itu membuat ketidakpuasan dan pergolakan di internal partai, khususnya bagi mereka yang mendapat suara lebih banyak, tetapi tidak bisa duduk di parlemen akibat suara mereka kurang dari BPP. Melalui UU No 10 Tahun 2008, pembentuk undang-undang memutuskan untuk mengurangi kuota harga kursi bagi caleg dari semula 100% menjadi 30% jumlah BPP. Itu disebut sebagai sistem pemilu proporsional yang lebih terbuka (a ‘more open’ list system).
Akan tetapi, pilihan proporsional terbuka secara gradual itu dibatalkan MK melalui Putusan No 22-24/PUU-VI/2008. MK menyebut setiap caleg mestinya dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing sehingga persyaratan 30% BPP yang harus dipenuhi caleg untuk mendapat kursi dan kalau tidak, akan kembali berdasar nomor urut, dipandang MK sebagai sesuatu yang menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif.
Dalam putusannya, MK menyebut dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang ialah berdasarkan suara terbanyak maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapa pun caleg yang mendapat suara terbanyak secara berurutan dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihan mereka dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.
MK juga menyandarkan pada pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law), sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga setiap caleg mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum.
Memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama ialah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Karena itu, menurut MK, ketentuan 30% BPP dalam UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.
Sayangnya, putusan tersebut (bisa jadi disebabkan keterbatasan MK dalam menjangkau detail teknis sebagaimana halnya pembentuk undang-undang, atau juga bisa jadi karena kurangnya pengetahuan MK soal sistem pemilu) tidak mempertimbangkan konsekuensi putusan atas operasionalisasi teknis secara holistis terhadap metode pemberian suara dan kaitannya dengan penentuan caleg yang mendapat kursi dari suatu partai.
Saat MK menyandarkan sepenuhnya kepada apa yang disebut ‘suara terbanyak’ caleg, MK terluput untuk mempertimbangkan penyelarasannya dengan metode pemberian suara yang masih membolehkan pemilih memberi tanda satu kali pada kolom nama partai, selain pada kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Kalau MK konsisten dan komprehensif memahami sistem pemilu, argumen ‘suara terbanyak’ caleg akan pula diikuti pertimbangan hukum, bahwa pemberian suara sepenuhnya dilakukan hanya untuk memilih caleg. Atau sebaliknya, jika memang pemilih masih dimungkinkan untuk memilih pada kolom nama partai, partai juga diberi hak menentukan caleg yang dikehendaki mereka untuk mendapat kursi dalam hal kolom nama partai mendapatkan pilihan paling banyak dari para pemilih. Namun, tidak seperti itu putusannya.
KPU sebagai pelaksana undang-undang yang saat persidangan perkara No 22-24/PUU-VI/2008 menyatakan kesiapan mereka atas implikasi perubahan sistem pemilu juga tidak menyarankan ataupun melakukan koherensi teknis itu. Akibatnya, putusan MK yang menghendaki ‘suara terbanyak’ itu pada praktik Pemilu 2009 dan pemilu-pemilu setelahnya masih bekerja dalam logika pemberian suara sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor urut sebagaimana pengaturan UU 10/2008 sebelum dibatalkan MK.
Politik hukum terbuka
Bisa jadi, ketidakakuratan jangkauan teknis itulah yang membuat MK putar arah saat memutus pengujian undang-undang terkait dengan variabel penunjang sistem pemilu berupa penjadwalan atau pilihan model keserentakan pemilu. Dalam Putusan No 55/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ketimbang menyatakan model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal, yang dimintakan Perludem sebagai pilihan konstitusional satu-satunya, MK lebih memilih untuk memberikan panduan berupa asas dan prinsip bagi pembuat undang-undang dalam memutuskan model keserentakan yang akan diatur dalam undang-undang.
Sebagai pedoman, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilu, MK menyebut pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal. Itu, antara lain, (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilu. (2) Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan.
Lalu, (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. (4) Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan (5) tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilu.
Bila kita rujuk sikap MK dalam Putusan No 55/PUU-XVII/2019 dan dikaitkan dengan uji materi atas sistem pemilu pada perkara No 114/PUU-XX/2022 yang saat ini sedang berlangsung, arah MK mestinya akan lebih mudah ditebak. MK akan memutus pilihan atas sistem pemilu merupakan wilayah pembentuk undang-undang untuk mengaturnya (open legal policy), sebagaimana halnya putusan MK terkait dengan model keserentakan pemilu.
Hal itu didasari beberapa pertimbangan. Pertama, UUD NRI 1945 tidak mengatur secara tegas pilihan sistem pemilu untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Meskipun Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menyebut bahwa ‘Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik’, tetapi hal itu tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai sistem pemilu proporsional tertutup sebab dalam sistem pemilu proporsional baik terbuka ataupun tertutup, peserta pemilunya ialah partai politik serta tidak ada ruang bagi calon perseorangan sebagaimana halnya pada pemilu anggota DPD.
Kedua, apabila ditelusuri risalah perubahan undang-undang dasar, akan ditemukan bahwa pilihan sistem pemilu anggota DPR dan DPRD bukan suatu pilihan tunggal. Di akhir Rapat PAH I BP MPR ke-33, pemimpin rapat Slamet Effendy Yusuf menyampaikan rangkuman usul-usul yang muncul selama rapat berlangsung. Terkait dengan sistem pemilu anggota DPR dan DPRD disebutkan bahwa ‘Kemudian secara sepintas lalu juga mulai diperdebatkan, muncul adalah mengenai sistem pemilu. Apakah proporsional, apa distrik atau mixed, campuran, itu juga sudah disebutkan’.
Pada Rapat Paripurna Ke-5 ST MPR 2001, 4 November 2001, yang dipimpin Ketua MPR M Amien Rais, pembahasan mengenai pemilu bergulir kembali. Fraksi-fraksi MPR menyampaikan pandangan fraksi masing-masing. S Massardy Kaphat dari F-KKI menyampaikan antara lain sebagai berikut: “Sistem pemilu untuk memilih wakil rakyat juga seharusnya lebih maju sehingga yang dipilih rakyat tidak cuma gambar-gambar partai, tapi juga orang sehingga yang lebih baik ke depan adalah sistem proporsional. Daftar terbuka yang dipilih rakyat adalah tanda gambar dan orang atau sistem distrik. Akan lebih demokratis lagi bilamana tidak hanya calon partai yang dibolehkan ikut dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga bisa calon perorangan.”
Ketiga, meskipun pemohon menguji sembilan norma yang berkaitan dengan inkonstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka, operasionalisasi teknis sistem pemilu proporsional terbuka tidak hanya terdapat dalam sembilan norma yang diuji tersebut. Kerangka pengaturan sistem proporsional terbuka juga tersebar dalam desain kepesertaan partai politik di pemilu, model kampanye, hak pemilih yang pindah memilih, penetapan perolehan suara oleh KPU (yang masih mencakup partai dan caleg), serta penegakan hukum (khususnya terkait dengan jual beli suara).
Terakhir, keempat, di masa depan sangat mungkin akan ada evaluasi ataupun modifikasi atas pilihan sistem pemilu. Jika MK mengunci pada satu pilihan sistem saja, hal itu akan berdampak pada kesulitasn untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada pemilu-pemilu yang akan datang.
Rambu-rambu
Oleh karena itu, bila menilik beberapa putusan MK termutakhir, soal sistem ini merupakan pilihan yang konstitusional bagi MK untuk menempatkannya sebagai ranah pembentuk undang-undang. Akan tetapi, MK perlu memberikan rambu-rambu pada pembentuk undang-undang terkait dengan asas dan prinsip dalam memilih sistem pemilu, sebagaimana yang dilakukan MK dalam Putusan No 55/PUU-XVII/2019 menyangkut pilihan model keserentakan pemilu.
MK juga penting menegaskan dalam putusan mereka konsistensi pilihan sistem pemilu terhadap berbagai variabel teknis yang menyertainya sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Misalnya saja, tidak relevannya penggunaan nomor urut dan opsi mencoblos partai pada sistem proporsional terbuka dengan popular vote (suara terbanyak). Putusan atas sistem pemilu itu akan menjadi salah satu momentum MK untuk meneguhkan posisi mereka sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia.
Karena itu, MK harus mampu membuktikan kemandirian kekuasaan mereka dan tidak terperosok pada tarik-menarik politik partisan yang justru bisa membuat MK terpuruk dan kehilangan kepercayaan publik. Tentu MK tidak akan segegabah itu. Oleh: Titi Anggraini Pembina Perludem dan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (*)








Tinggalkan Balasan