Buru Hotong dan Ketahanan Pangan
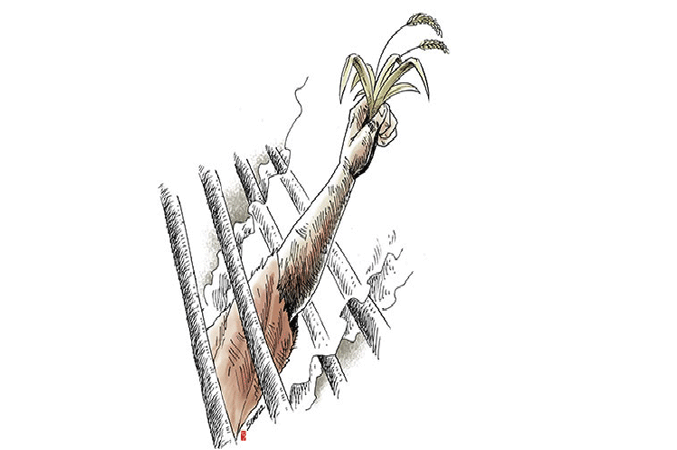
DUA pekan lalu, saya berkunjung ke Pulau Buru. Agendanya ialah untuk berpartisipasi secara sukarela dalam membangun ketahanan pangan Indonesia. Bagi saya, ini juga menjadi semacam panggilan tersendiri karena situasi ketahanan pangan global yang tak menentu semakin mengancam ketahanan kita.
Di Pulau Buru ternyata masih terdapat budi daya sejenis jawawut yang dalam bahasa lokal disebut buru hotong (Setaria italica). Bahan pangan yang pernah menjadi bahan makanan pokok secara luas di kawasan Asia itu, sebelum digantikan oleh beras, memiliki tempat yang sakral di tengah masyarakat Pulau Buru.
Berbagai bentuk penganan dengan bahan utama buru hotong, misalnya, wajib disajikan dalam acara-acara seremonial adat. Itu karena dalam kepercayaan masyarakat Buru, buru hotong ialah bahan makanan anugerah sang Pencipta yang telah memungkinkan keberlanjutan kehidupan sebagaimana dapat dibaca dalam legenda Boki Feten.
Dari segi kesehatan, buru hotong yang tumbuh mirip padi atau alang-alang itu memiliki kandungan karbohidrat seperti beras, rendah glukosa, memiliki protein dan lemak yang lebih tinggi, serta antioksidan. Namun, salah satu tantangannya ialah soal tingkat kedicernaan yang mungkin bisa saja ditingkatkan melalui semacam rekayasa pertanian.
Poin kritis pertama saya di sini ialah, bahwa Indonesia memiliki kekayaan jenis bahan pangan yang seiring waktu kehilangan tempat. Mengikuti tren, pengaruh atau perkembangan tertentu, pola pangan berubah, dan pada tingkat yang signifikan menciptakan ketergantungan. Tanaman yang secara kultur alam cocok dan memiliki akar sosial-kultural dikalahkan. Contoh paling kasatmata ialah tepung gandum atau terigu. Bahan makanan penunjang yang menjadi semakin penting di Indonesia yang mengalahkan umbi-umbian dan jagung. Karena gandum pada dasarnya ialah tanaman subtropis dan tidak dibudidayakan secara massif di Indonesia, volume impor Indonesia, termasuk salah satu yang terbesar di dunia, yakni mencapai lebih dari 5.000 ton atau bernilai lebih dari US$1.500 juta.
Baca Juga: Pekerjaan Besar Pemimpin Baru 2024Karena pada dasarnya kita tak bisa melawan arus, dalam hal ini tren makanan, saya sampai pada poin kritis kedua, yakni betapa respons politik dan ekonomi terhadap pengembangan budi daya tanaman pangan ternyata amat rendah. Hal itu menyebabkan kita kalah dalam budi daya gandum, misalnya, dari negara beriklim tropis lain, seperti Myanmar yang telah memiliki rata-rata produksi gandum tertinggi mencapai 1,8 ton/ha. Padahal, dengan melihat kebutuhan yang amat besar dan betapa mengimpor pada dasarnya berbahaya bagi ketahanan pangan dan roda perekonomian nasional, langkah-langkah politik dan ekonomi sudah sangat mendesak atau bahkan sangat terlambat dilakukan.
Fakta tersebut menjadi semakin menyedihkan ketika membaca betapa riset dan pengembangan tanaman gandum yang dilakukan ahli-ahli dari lembaga penelitian pertanian di Indonesia ternyata telah berhasil mengembangkan varietas yang cocok untuk iklim Indonesia. Sejauh ini budi daya dalam skala kecil baru dilakukan di beberapa daerah, seperti di Pasuruan dan Probolinggo (Jawa Timur), serta Salatiga (Jawa Tengah).
Jauh hari sebelum krisis pangan dunia terjadi karena perang Rusia-Ukraina, dan ini menjadi poin kritis yang ketiga, dengan mayoritas masyarakat yang mengkonsumsi beras, Indonesia sampai saat ini terus-menerus mengimpor beras. Pernyataan-pernyataan tentang swasembada pangan tak lebih dari jualan dan bualan politik.
Secara alam dan sosial-kultural, sudah pasti tak ada lagi persoalan budi daya padi. Ia sudah menjadi tanaman bagi bahan pokok selama ribuan tahun dan ditanam di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun, kenapa impor?
Setelah merenung panjang lebar, saya melihat bahwa ada persoalan sistemis dalam tata kelola pertanian tanaman pangan. Kepemimpinan nasional yang dari waktu ke waktu disibukkan percepatan pembangunan ekonomi yang diukur secara makro dan proyek-proyek mercusuar terjebak dalam sikap permisif terkait signifikansi ekonomi ketahanan pangan.
Pembangunan pabrik, perumahan, pusat-pusat belanja, atau ragam penanda ekonomi kapitalistik lainnya, sebagai contoh, terus menggerus sawah-sawah dan lahan pertanian produktif lainnya. Lahan sawah Indonesia, misalnya, dengan kecepatan konversi saat ini, diperkirakan akan terus menciut menjadi sekitar 6 juta ha saja menjelang 2045.
Demikian pula dengan karut-marut dukungan bagi pertanian tanaman pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu importir besar pupuk dunia. Pada 2021 saja, impor pupuk Indonesia mencapai 8,1 juta ton atau setara dengan US$834,76 (Rp11,94 triliun).
Pelajaran pandemic
Krisis di Eropa, berupa perang Rusia-Ukraina, yang mengancam ketahanan pangan di samping energi, merupakan pelajaran pahit. Namun, pelajaran pahit yang seyogianya dicermati ulang dan dijadikan dasar sikap politik ekonomi, yang pengaruhnya masih amat kuat, ialah pandemi covid-19.
Sekitar tiga tahun, situasi pandemi telah memunculkan ke permukaan apa yang paling penting dan apa yang kurang penting. Ketahanan pangan ternyata tetaplah hal terpenting. Daya tahan ekonomi ternyata sampai taraf signifikan dimungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah, di samping tentu saja resiliensi lapisan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian pangan.
Oleh karena itu, bangsa ini, jika hendak terus abadi, harus merendahkan hati untuk belajar. Pandemi dan kemudian perang di Eropa merupakan momentum untuk itu. Juga soal rasa syukur, yang seyogianya juga hadir di hati para penyelenggara pemerintahan–eksekutif, legislatif, yudikatif–yang tidak semestinya hanya menikmati kue pembangunan yang dibuat dari tetes keringat dan darah rakyat.
Negara-negara maju saja, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan lainnya, ternyata membangun ketahanan pangan yang luar biasa. Mereka memajukan pertanian dalam skala industri yang amat besar yang tidak saja sampai taraf tertentu menghidupi negara, tetapi juga menjadi sokoguru penting ketika ragam krisis terjadi. Karena itu, alangkah naif atau bodohnya kita, bangsa agraris yang diombang-ambingkan oleh badai kapitalisme ini, dengan anugerah alam yang tak terukur, ternyata tak mampu hanya untuk sekadar mencukupi kebutuhan pangan dari waktu ke waktu.
Tak berlebihan rasanya jika kemudian saya bertanya, “Tidakkah tersisa sedikit rasa malu bahwa kapital yang dihambur-hamburkan dalam bentuk kemewahan di jalan-jalan raya, di gedung-gedung tinggi, di rumah-rumah mewah, di meja-meja jamuan yang lebih banyak mubazirnya itu ialah hasil rampokan terhadap nasib ratusan juta anak cucu kita sendiri yang akan hidup di satu, dua, tiga, dan belasan dekade yang akan datang?”. Oleh : IGK Manila Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) dan anggota merangkap Sekretaris Majelis Tinggi Partai NasDem (*)




Tinggalkan Balasan