Paradoks Panggung Sosial Politik

PANGGUNG sosial politik akhir-akhir ini diselimuti paradoks. Di satu sisi sekelompok elite berorkestrasi mengusulkan penundaan pemilu. Meskipun itu tidak bisa lepas dari ‘adiksi’ kekuasaan semata, ironisnya mereka membungkus usulan tersebut dengan mengatasnamakan kemauan rakyat. Di sisi lain menyeruak fenomena ribuan warga antre memburu minyak goreng di berbagai daerah hingga seorang ibu di Berau, Kalimantan Timur, meninggal dunia akibat antre berdesakan. (Metrotvnews.com, 12/3). Lalu Menteri Perdagangan yang sejatinya bertangung jawab atas kelangkaan minyak goreng tersebut tiba-tiba secara defensif mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena rakyat melakukan penimbunan minyak goreng (mediaindonesia.com, 11/3).
Dalam kasus penundaan pemilu, ‘suara rakyat’ dibela, diafirmasi, meskipun kita tak tahu persis, rakyat mana yang dimaksudkan mereka. Bertolak belakang dengan itu, di kasus minyak goreng, rakyat seolah dikambinghitamkan dari berbagai kesalahan kebijakan, termasuk manuver kartel. Meskipun akal sehat publik bisa dengan cepat menyergah, ‘memangnya berapa kuat sih rakyat mampu menimbun minyak goreng?’ Emak-emak itu rela antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng paling untuk goreng tahu, tempe, yang juga harga dan bentuknya mulai berubah. Kalaupun ada yang membutuhkan lebih, mungkin penjual gorengan yang memang harus menjamin kecukupan stok supaya bisa jualan tiap hari demi menyambung hidup. Memudar makna rakyat Paradoksnya panggung sosial politik tersebut tidak terlepas dari kian memudarnya makna dan eksistensi rakyat dalam pikiran dan habitus elite kita. Salah satu teori terbentuknya negara sebagaimana dikemukakan Thomas Hobbes, terbentuknya negara karena ada covenant (perjanjian) antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan organisasi bernama negara untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dalam perspektif ini, rakyat sejatinya tidak menyerahkan kedaulatannya pada elite (negara). Namun, para elite hanya merepresentasikan kepentingan rakyat untuk diperjuangkan bagi kepentingan bersama. Rakyat tetap memiliki kedaulatan penuh untuk mengawasi termasuk menagih dan mengadili sikap dan pilihan politik pemerintah jika hal tersebut bertentangan dengan isi kontrak.
Posisi rakyat di sini memiliki nilai sentral dan substantif dalam perjanjian, kesepakatan, dan dalam aktualisasi berbagai kehendak politik negara. Apa yang terlihat saat ini, makna rakyat seolah mengalami pengerdilan. Dalam demokrasi kontemporer yang mengedepankan logika transaksional dan materialistik, posisi rakyat kerap diinstrumentalisasi sebagai subjek komoditifikasi politik untuk memperlancar agenda kekuasaan segelintir orang. Rakyat hanya menjadi variabel pelengkap dari berbagai sikap dan kebijakan sekelompok elite agar mereka tidak kehilangan legitimasi di hadapan prinsip dan nilai demokrasi dan warga masyarakat. Kenyataan ini terus berlanjut dan menjadi kerikil bagi perkembangan demokrasi saat ini karena posisi rakyat hanya menjadi reservoir dari organisme kekuasaan. Fenomena penundaan pemilu dan kelangkaan minyak goreng di atas bisa dilihat dari perspektif kontrak sosial dalam demokrasi yang menunjukkan melemahnya status dan hak-hak rakyat di tengah negosisasi kekuasaan yang manipulatif. Tampak di dua isu itu ada perjumpaan emotif sekaligus habitus destruktif dari para elite yang menjadikan rakyat tak lebih sebagai ‘gorengan politik’ demi kenikmatan agenda parsial mereka.
Wacana penundaan pemilu misalnya, selain memunggungi konstitusi, juga memperlihatkan arah orientasi antagonistik antara rakyat dan elite. Nama rakyat dikapitalisasi untuk menggemakan kepentingan elite sekaligus dibiarkan terjerumus dalam lembah rivalitas mempertahankan hari-hari hidupnya dari berbagai ancaman krisis, persis di tengah pesta pora elite menggoreng kehendak memperpanjang kekuasaan. Padahal Max Weber mengatakan politik sebagai kemampuan personal untuk mencapai tujuan meskipun ada oposisi. Upaya pencapaian tujuan itu bisa dengan koersif atau kewenangan yang mendapatkan legitimasi rakyat.
Rakyat menjadi penting karena kekuatannya bisa menurunkan kekuasaan. Menurut SP Varma (2007), elite politik ialah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik, baik kekuasaan untuk memengaruhi orang lain dan kekuasaan untuk memengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Sayangnya dalam praktik, definisi tersebut hanya menjadi kekuatan artifisial dan simbolik elite untuk menekan kesadaran kritis rakyat, bahkan sekadar mempertanyakan lemahnya kebijakan para elite. Bukan sebagai liabilitas moral dan konstitutif elite untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat. Apalagi, meminjam Maynard Keynes (1883-1946), negara memiliki tanggung jawab prinsipil untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, memperjuangkan kesejahteraan minimal dan perbaikan standar hidup rakyat. Justru yang terjadi kini rakyat terombang-ambing mendefinisikan posisi populisnya di tengah isu penundaan pemilu dan kebutuhan dasar minyak goreng yang kian langka.
Baca Juga: Menyelisik Pendidikan Kedokteran KitaSementara itu, elite terus memompa berbagai dalil, argumen ke tengah publik dan mengerahkan pendukung artifisialnya demi untuk menangkis resistensi publik dari berbagai isu dan kebijakan yang mereka gulirkan di tengah masyarakat dari ruang-ruang gelap negosiasi atau aproksimasi politik. Alarm keras Meminjam teori kubus kekuasaan (powercube)-nya John Gaventa (2006), salah satu bentuk operasi kekuasaan ialah apa yang disebut sebagai kekuasaan tak terlihat (invisible power), yakni model kekuasaan yang bergerak dalam pengaruh ideologisasi, nilai, bentuk perilaku yang membuat masyarakat tak sadar bahwa ia tengah diperdayai oleh para elite demi akumulasi kepentingan kekuasaannya. Wacana penundaan pemilu di satu sisi menunjukkan hasrat akumulasi kekuasaan ketimbang redistribusi kekuasaan.
Di sisi yang lain, sebagai sebuah sinyal kepada publik terkait bekerjanya operasi-operasi politik gelap oleh kekuatan politik rahasia, yang mencoba untuk membungkam rasionalitas publik dan memaksakan perpanjangan kekuasaan. Seperti membenarkan kata Elias Canetti dalam Crowds and Power (1984); kerahasiaan terletak pada inti kekuasaan. Meskipun Presiden Joko Widodo sudah secara tegas tidak akan menabrak konstitusi dengan menyetujui perpanjangan kekuasaan atau penundaan pemilu karena hanya akan menampar wajahnya. Kesepakatan penuh martabat partai Nasdem dan Golkar untuk tidak memperpanjang polemik penundaan pemilu (Media Indonesia, 10/3), mestinya menjadi alarm keras bagi elite partai lain untuk saat ini juga menyetop berbagai kegaduhan politik. Pada sikap tegas elite politik inilah, terpancar kemuliaan dan orientasi jernih mereka dalam merepresentasikan kepentingan dan memuliakan kedaulatan rakyat. Wajah politik akan jauh lebih humanis dan menawan jika para elite politik duduk bersama mengatasi persoalan riil rakyat termasuk krisis minyak goreng. Komitmen membela kepentingan rakyat ialah harga mati kemanusiaan seorang politik ketimbang sibuk mengemis kursi kekuasaan dari (kehendak) rakyat. Oleh: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang



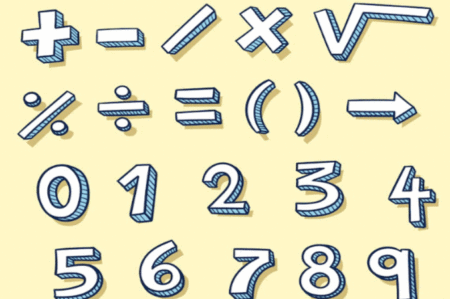
Tinggalkan Balasan