Mewaspadai Tekanan Stagflasi Global
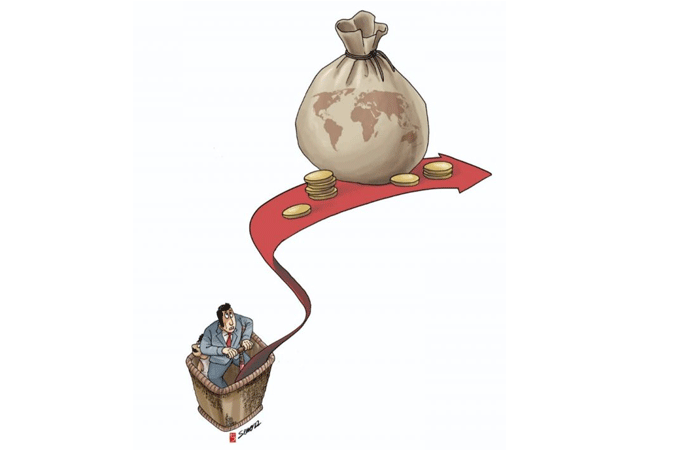
DALAM opininya di Project Syndicate, Nouriel Roubini, profesor emeritus ekonomi di Stern School of Business New York University, memberikan paparan menarik bahwa dunia bakal menghadapi badai stagflasi berkelanjutan (Guardian, 25/4/2022).
Pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina menambah masalah, menyebabkan inflasi lebih tinggi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, negara-negara di dunia harus memperhitungkan risiko konflik militer skala besar, yang mendisrupsi aktivitas perdagangan dan produksi global. Selain itu, sanksi yang digunakan untuk mencegah dan menghukum agresi Rusia itu pun menjadi penyebab stagflasi.
Kawasan Eropa secara keseluruhan sangat rentan terhadap gangguan pada pasokan energi mereka, dengan 40% gas Uni Eropa berasal dari Rusia. Banyak ahli ekonomi mengingatkan bahwa hambatan akses Uni Eropa terhadap gas Rusia akan memicu salah satu resesi terdalam dalam beberapa dekade terakhir di Jerman dan zona euro.
Lonjakan harga gas di Eropa ibarat pil pahit bagi kawasan ini. Jika terjadi perang berkepanjangan, atau sanksi tambahan terhadap Rusia, harga bisa lebih tinggi daripada yang diproyeksikan. Tanpa penghentian gas, pertumbuhan ekonomi di zona euro telah melambat menjadi hanya 0,2% pada kuartal pertama 2022, sementara inflasi naik ke rekor tertinggi 7,5%. Semua itu berujung pada pelemahan perekonomian dunia.
Konsensus global sekarang untuk pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata hanya 3,3% tahun ini, turun dari 4,1% diharapkan pada Januari lalu, sebelum perang meletus. Inflasi global diperkirakan sebesar 6,2%, atau 2,25% lebih tinggi daripada perkiraan Januari lalu. Demikian pula, IMF menurunkan perkiraan mereka untuk 143 negara tahun ini yang menyumbang 86% dari produk domestik bruto (PDB) global.
Baca Juga: Fisika dan Pendidikan PerdamaianRealitas baru yang harus diperhitungkan banyak negara maju dan negara berkembang ialah inflasi lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi melambat. Kini dunia dihadapkan pada stagflasi yang sudah di depan mata. Laju inflasi melampaui ekspektasi, sementara perkiraan pertumbuhan dengan cepat menurun.
Karena itu, upaya luar biasa untuk dapat memerangi stagflasi saat ini ialah bagaimana menyiapkan serangkaian langkah kebijakan yang taktis, tepat waktu, tepat takaran, dan tepat sasaran untuk dapat mengatasi guncangan pasokan agregat yang negatif karena keterbatasan produksi yang justru berdampak pada kenaikan biaya.
Tidak berlebihan jika kondisi stagflasi akan terus menjadi ‘ciri baru’ ekonomi global, dengan disrupsi pasokan global telah mendorong inflasi lebih tinggi, memperlambat pertumbuhan, dan berpotensi menciptakan resesi di beberapa negara.
Roubini juga menekankan perang dingin baru antara AS dan Tiongkok juga akan menghasilkan efek stagflasi. Perubahan iklim pun akan mengakselerasi stagflasi. Kekeringan telah merusak tanaman, merusak panen, dan menaikkan harga pangan. Sama seperti badai, banjir, dan kenaikan permukaan air laut menghambat kegiatan ekonomi.
Dalam kondisi seperti ini, lonjakan harga energi yang tajam tidak dapat dihindari dan ketika harga energi naik, greenflation akan memukul harga untuk bahan baku yang digunakan dalam panel surya, baterai, kendaraan listrik, dan teknologi bersih (ramah lingkungan) lainnya.
Perlu kebijakan taktis
Sejumlah negara melalui bank sentral mereka sudah berusaha keras menjinakkan inflasi melalui jalur suku bunga. Sebut saja AS, Korea Selatan, Selandia Baru, Inggris, dan Australia. Dengan inflasi tahunan mencapai 8,3%, tak ada pilihan bagi The Fed kecuali mengeremnya dengan menaikkan suku bunga sebesar 0,75% dalam dua kali pertemuan terakhir mereka. The Fed juga menghentikan kebijakan quantitative easing seiring dengan pertumbuhan ekonomi tahunan yang melampaui ekspektasi.
Secara umum, seiring dengan pulihnya perekonomian di berbagai negara, langkah bank sentral menaikkan suku bunga menjadi salah satu terapi tepat meskipun masih ada kebijakan nonsuku bunga yang juga bisa ditempuh. Kombinasi/bauran kebijakan suku bunga dan nonsuku bunga (baca: kebijakan makroprudensial) bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tadi.
Kenaikan suku bunga bank sentral di berbagai negara sebagai barometer suku bunga komersial lazimnya akan diikuti perbankan. Hal itu memberikan sedikit tekanan ke pasar modal karena sebagian investor melakukan switching investasi dari portofolio pasar modal ke produk perbankan. Itu merupakan fenomena wajar sehingga tidak perlu direspons dengan kebijakan yang over-reactive atau over-doses yang justru bisa over-killed.
Ketepatan dosis besaran kenaikan suku bunga acuan menjadi penting untuk dipertimbangkan guna menciptakan ketenangan di pasar dan masyarakat luas. Sinyal awal terkait dengan kenaikan suku bunga acuan pun penting di-create sehingga ketika kenaikan suku bunga direalisasikan, pelaku pasar, dunia usaha, dan masyarakat luas bisa menerima dengan baik. Pasar keuangan tetap tenang. Dunia usaha dan masyarakat tetap beraktivitas normal.
Yang perlu dicermati
Terdapat dua hal, yang perlu dicermati para pengambil kebijakan ketika terjadi lonjakan inflasi, disusul kenaikan suku bunga acuan. Pertama, lonjakan inflasi akan memengaruhi secara negatif para pekerja, terutama yang berpenghasilan tetap, lebih-lebih pekerja kerah biru. Maklum, dengan pendapatan relatif tetap, sementara lonjakan harga barang tak tertahankan, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap bisa terdiskon.
Kedua, sekiranya suku bunga perbankan/pembiayaan mengikuti gerakan suku bunga acuan yang naik, kebijakan tersebut seyogianya dikomunikasikan dengan baik (sebagai bagian implementasi prinsip market conduct) sehingga debitur bisa melakukan penyesuaian arus kasnya. Bank dan lembaga pembiayaan terhindar dari pinjaman bermasalah. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan dapat dijaga sekaligus stabilitas moneter juga dapat dipertahankan. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi. Oleh: Ryan Kiryanto Ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan (*)




Tinggalkan Balasan