Menkes Take Over BPJS Kesehatan, Apa Risikonya?
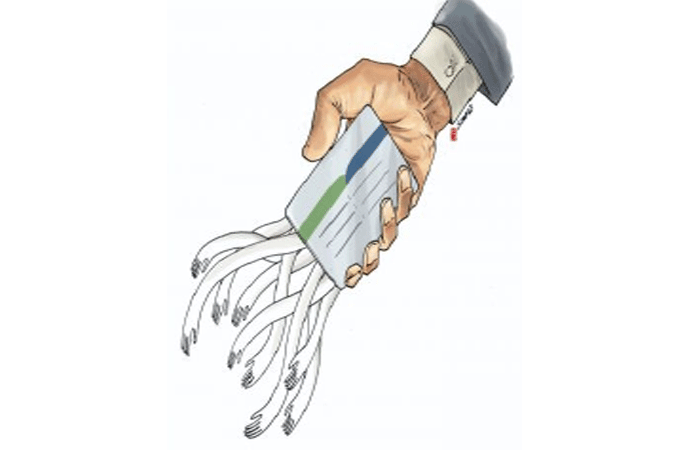
PERTANYAAN di atas muncul dalam pikiran penulis setelah mempelajari secara mendalam RUU Omnibus tentang Kesehatan, yang beredar di masyarakat yang setiap lembar ada tulisan bayangan confidential, tetapi tidak ada pihak yang mengaku sebagai pembuat RUU itu. Namun demikian, tidak ada bantahan dari pihak terkait beredarnya RUU Kesehatan.
Karena RUU itu sudah bergulir, dan pihak Baleg DPR menginformasikan akan membahasnya setelah mendapat persetujuan fraksi-fraksi DPR, penulis lebih menyoroti pasal-pasal tertentu, terkait dengan UU SJSN dan UU BPJS.
Jumlah pasal sebanyak 470 pasal, yang terdiri atas XX bab. Namun, dalam tulisan ini, kita memfokuskan pada Pasal 415 sampai dengan 417, yang bongkar pasang dengan pendekatan Omnibus UU SJSN dan UU BPJS yang seharusnya bersifat lex specialist, dimasukkan dalam RUU Kesehatan yang bersifat generalis.
Pasal 415 itu menyebutkan bahwa RUU Kesehatan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa yang diatur dalam UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004, dan UU BPJS Nomor 24/2011.
Pada Pasal 416, bongkar pasang terkait UU SJSN pada Pasal 13, 17, 19, 22, 23, 24, 27. Pada Pasal 417 RUU Kesehatan, bongkar pasang terhadap Pasal 7, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 28, 34, 37.
Baca Juga: Quo Vadis Pendidikan Pascahadir EduagenPenulis akan menyinkronkan apa sebenarnya makna yang tercantum setiap pasal, dan kemudian dengan begitu saja diomnibuskan dalam RUU Kesehatan.
Pada Pasal 13 UU SJSN itu dimaksudkan ialah dalam konteks peserta 5 program SJSN, bukan diperuntukkan untuk program JKN saja. Maka, dalam Pasal 13 perubahan RUU muncul istilah pemberi kerja dan program jaminan sosial yang diikuti sehingga tidak relevan dalam konteks RUU Kesehatan.
Hal yang sama terlihat pada perubahan Pasal 17. Pasal ini mengatur iuran untuk 5 program SJSN (JK, JKK, JKm, JHT, dan JP) sehingga juga menjadi tidak nyambung jika RUU Kesehatan bicara soal pekerja dan pemberi kerja yang hal itu dalam lingkup jaminan sosial ketenagakerjaan.
Saat memasuki Pasal 19, UU SJSN memang bicara soal Jaminan Kesehatan. Pasal tersebut hanya mencantumkan 2 ayat. Bunyinya ayat (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Ayat (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Pasal ini tidak untuk merumuskan segala sesuatu terkait nomenklatur kesehatan, hanya menegaskan tentang skala nya bersifat nasional, prinsipnya, dan penegasan peserta dijamin memperoleh manfaatnya untuk pemeliharaan kesehatannya.
Soal bagaimana elaborasi manfaat dimaksud, medis dan nonmedis menjadi domain sektor kesehatan. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar kesehatan silakan ditafsir dan dirumuskan oleh Kemenkes dan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang JKN. Karena itu, Pasal 19 RUU Kesehatan yang dikembangkan menjadi 9 ayat menjadi tidak penting. Cukup dimuat dalam Perpres JKN.
Sebenarnya, Kemenkes sudah menerapkannya dalam Perpres 82/2018 tentang JKN, yakni mengatur regulasi teknis yang tidak ada diperintahkan dalam norma UU SJSN/BPJS, tetapi dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan JKN, termasuk Pasal 19A ayat (1) cukup diatur dalam Perpres JKN.
Sama halnya Pasal 22, UU SJSN bicara soal manfaat dan urun biaya jika ada penyalahgunaan pelayanan oleh peserta. Dalam RUU Kesehatan tidak singgung soal manfaat, tetapi moral hazard dari sisi peserta dan cara melaksanakan urun biaya. Pasal 22 UU SJSN dan Pasal 22 RUU Kesehatan, juga diatur lebih lanjut dalam perpres. Artinya tidak ada perubahan makna, hanya sekadar menunjukkan ada perubahan.
Bagaimana dengan Pasal 23. Ini ada perubahan yang fundamental. UU SJSN menegaskan bahwa BPJS Kesehatan bekerja sama dengan faskes dengan pendekatan sukarela. Artinya, kesepakatan kedua belah pihak dengan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing.
Namun, dalam RUU Kesehatan pada Pasal 23 BPJS Kesehatan wajib menerima kerja sama yang diajukan faskes. Hal ini bertolak belakang dengan kemandirian BPJS Kesehatan. Fungsinya sudah menjadi instrumen birokrasi pemerintahan. Karena bersifat wajib, tidak perlu ada lagi perjanjian kerja sama. Hal tersebut berisiko terhadap kendali biaya dan kendali mutu yang harus dilakukan BPJS Kesehatan.
Pasal 24, Kemenkes berkeinginan untuk bersama-sama dengan BPJS Kesehatan dalam mengembangkan sistem kendali mutu dan kendali biaya pelayanan. Sementara itu, UU SJSN kewajiban itu hanya diberikan kepada BPJS Kesehatan, karena terkait jaminan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang efisien. Jika terlibat Kementerian Kesehatan akan terjadi conflict of Interest yang merugikan BPJS Kesehatan.
Pasal 27 RUU Kesehatan juga tidak substantif. Hanya ingin menunjukkan adanya perubahan. Sebab, dalam Pasal 27 UU SJSN itu hakikatnya menyampaikan rambu-rambu terkait dengan iuran bagi berbagai segmen peserta dan elaborasinya diatur dalam perpres.
Pasal 27 RUU Kesehatan memunculkan istilah pendapatan rumah tangga seseorang. Ukuran pendapatan rumah tangga kita belum punya. BPS dapat menentukan pendapatan rumah tangga secara tidak langsung, tetap melalui besaran pengeluaran rumah tangga per bulannya. Deltanya lebar. Ada orang hidupnya tutup lubang gali lubang, rajin berhutang, bagaimana mengukur pendapatan rumah tangganya?
Lebih membingungkan
Penulis melanjutkan mencermati Pasal 405 RUU Kesehatan. Pasal ini lebih membingungkan lagi. Yang dibedah ialah UU BPJS, sedangkan BPJS itu ada dua badan. Pertama disebut BPJS Kesehatan melaksanakan program JKN. Kedua BPJS Ketenagakerjaan yang melaksanakan 4 program JKK, JKM, JHT, dan JP.
Kita mencermati Pasal 417 itu mengutip Pasal 7 (UU BPJS), yang mengatur BPJS sebagai badan hukum publik. Artinya, mengatur dua lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada ayat (2) RUU Kesehatan mengatakan BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan untuk BPJS Kesehatan dan Menaker untuk BPJS Ketenagakerjaan. Adapun UU BPJS pada pasal yang sama menyebutkan BPJS bertanggung jawab kepada presiden, tanpa embel-embel melalui menteri.
Ada dua persoalan di sini. Pertama, apakah boleh RUU Kesehatan mengatur kedududkan menteri tenaga kerja? Kedua, apakah sejauh itu RUU Kesehatan boleh men-downgrade wewenang Presiden? Apakah sejauh itu RUU Kesehatan men-downgrade kewajiban BPJS bertanggung jawab kepada Presiden?
Ini persoalan Tata Kelola Kelembagaan, yang perlu disoroti oleh Men-PAN, terhadap RUU yang mengacaukan Tata Kelola Lembaga Negara.
Persoalan Tata Kelola Kelembagaan ini, juga berlanjut pada Pasal 13. Sama-sama badan hukum publik, kedua BPJS itu harus melaksanakan penugasan dari kementerian (kesehatan dan ketenagakerjaan). Perlu dicatat dalam Ketentuan Umum (Pasal 1) baik UU SJSN dan UU BPJS tidak ada nomenklatur Kementerian.
Hanya tiga lembaga yang disebut, yakni BPJS, DJSN dan pemerintah (dalam hal ini dimaksudkan Presiden). Bagaimana jalan ceritanya tiba-tiba dua kementerian me-remote BPJS. Apa urusannya, RUU Kesehatan mengatur kedudukan Menaker mengontrol BPJS Ketenagakerjaan?
Pasal 15 perubahan (RUU Kesehatan) melakukan perubahan yang mendasar. Menghilangkan ‘pentahapan’ kewajiban pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya. Kalimat ‘pentahapan’ itu tidak perlu dihilangkan. Karena itu historikal proses pendaftaran yang tidak sekaligus. Baca alinea terakhir Penjelasan UU BPJS Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut, jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.
Mungkin penyusun RUU OTK tidak sempat membaca Penjelasan UU BPJS. Pentahapan dimaksud sudah diatur dalam perpres, sudah berjalan baik. Apa urgensinya dihapus?
Perubahan Pasal 21 (RUU Kesehatan), lebih jelas keinginan kementerian untuk mengontrol penuh BPJS melalui Dewan Pengawas. Aturan pada Pasal 21 UU BPJS, unsur pemerintah itu 2 orang. Pemberi kerja 2 orang, pekerja 2 orang, dan tokoh dan atau ahli jaminan sosial 1 orang (total 7 orang). Salah satu dari unsur pemerintah menjadi ketua dewas. Format ini sebenarnya sudah memberi peran pemerintah sebagai ‘pengendali’ dewas karena ketuanya dari unsur pemerintah. Mekanisme kerja mereka adalah kolektif kolegial.
Pada perubahan Pasal 21 (RUU OTK) itu, unsur pemerintah dua kali lipat menjadi 4 orang, dan unsur pemberi kerja dan pekerja ‘dipreteli’ masing-masing 1 orang. Dengan demikian, terjadi perubahan komposisi 4, 1,1, 1.
Unsur pemerintah, di samping sebagai ketua mendominasi jumlah anggota dewas. Perlu diingat, lahirnya UU BPJS tidak terlepas dari perjuangan buruh, sedangkan pemerintah setengah hati waktu itu. Karena itu, pembahasan RUU BPJS cukup lama, alot, dan sangat transparan.
Mencederai kemandirian dan independensi
Kita juga perlu hati-hati mencermati perubahan Pasal 22 (RUU Kesehatan). Dewas dalam melaksanakan fungsinya, ada penambahan kalimat ‘Laporan BPJS kepada Presiden melalui menteri…’. Kalimat itu pada Pasal 22 UU BPJS tidak ada. Artinya untuk melapor ke Presiden atas pelaksanaan kewajiban dewas tidak harus melalui menteri (menkes).
Proses melalui menteri mencederai kemandirian dan independensi sebagai badan hukum publik. Kedua lembaga itu (Kementerian dan BPJS), sama-sama badan hukum publik, jadi tidak boleh ada ‘koptasi’ kementerian terhadap BPJS. Bahkan, kontrol Kementerian itu mencengkram dewas dipertegas dalam upaya dewas membuat regulasi internal Tata Kelola Dewas harus berkoordinasi dengan menteri.
Upaya men-downgrade Organ BPJS semakin sempurna pada perubahan Pasal 24 (RUU Kesehatan), yakni ayat (3) huruf d: ‘Direksi mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi dewas dan Direksi’. Bayangkan, untuk mengusulkan saja oleh Organ BPJS yang semula diusulkan direksi, diganti oleh dewas. Apa tujuannya? Sudah dapat diduga, karena ketua dewas ialah unsur kementerian. Seharusnya, secara struktural kelembagaan, mengatasnamakan Organ BPJS Kesehatan keluar termasuk ke Presiden ialah direksi (direktur utama, sebagai executive).
Pasal 25 UU BPJS tentang Persyaratan umum dewas dan direksi ayat (1) f dihapus. Ayat itu mengatur batasan umur yang dapat menjadi dewas dan direksi paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Tak jelas dasar penghapusan batas umur.
Sewaktu UU BPJS disusun, soal batas umur ini sesuai dengan beberapa lembaga negara lainnya seperti OJK dan DJSN. Pertimbangannya jelas terkait usia produktif, dan kematangan usia minimal. Sebab, Organ BPJS mengelola dana peserta yang sangat besar. Saat ini, total dana jaminan sosial (di luar dana badan) di kedua BPJS lebih dari Rp600 triliun. Ingat itu dana peserta yang dititipkan kepada BPJS.
Apakah karena besarnya dana amanat itu, menyebabkan kementerian ingin mengendalikan BPJS? Indikasi dari RUU Kesehatan sepertinya arah ke sana.
Fakta lain dari dugaan di atas, lihat saja perubahan pada Pasal 28 (RUU Kesehatan). Pasal baru itu mengatur bahwa pansel dewas dan direksi diketuai oleh menteri.
Pada aturan Pasal 28 UU BPJS, pansel diusulkan calonnya oleh DJSN dari berbagai unsur. Ditetapkan oleh presiden dengan keppres. Ketua pansel itu ditetapkan oleh Presiden dari unsur Pemerintah. Sudah jelas, dan mekanismenya sudah berjalan selama ini dengan lancar. Begitu banyak beban tugas menteri, masihkah harus dibebani lagi tugas sebagai ketua pansel. Semakin jelas menteri cenderung ingin full power. Caranya? Dengan mengurangi wewenang Presiden.
Perubahan Pasal 34 (RUU Kesehatan), proses pemberhentian dewas dan direksi, menghilangkan peran DJSN. Suatu lembaga yang eksis tercantum dalam Ketentuan Umum UU BPJS. RUU ini benar-benar ‘menginjak kaki’ lembaga BPJS dan DJSN.
Puncaknya perubahan pada Pasal 37 (RUU Kesehatan), bahwa laporan petanggungjawaban BPJS baik program dan keuangan dilaporkan kepada Presiden melalui menteri (menkes). Ada apa? Di mana otorisasi Organ BPJS untuk menyampaikan laporan program dan keuangan kepada owners (peserta) yang dalam hal ini diwakili secara hukum oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Jika laporan itu sudah ditangan Presiden, dan Presiden memerintahkan kepada menteri tertentu untuk mengevaluasinya, itu sudah menjadi wewenang Presiden karena secara kelembagaan (Organ) BPJS sesuai dengan UU BPJS , pada Pasal 4 berpedoman pada 9 prinsip. BPJS dan DJSN tidak boleh keluar dari 9 prinsip itu, kecuali Organ BPJS dan DJSN dibubarkan dan membubarkan Organ BPJS harus juga dengan UU.
Pembahasan
Dari kajian pasal per pasal RUU Kesehatan, khususnya terkait dengan BPJS tidak dapat dibantah adanya indikasi kuat untuk:
- Mereduksi fungsi, tugas dan wewenang Organ BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan mem-blended-nya ke wilayah wewenang, tugas dan fungsi menteri terkait.
- Memperkuat peran menteri terkait dalam mengontrol aktivitas BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
- Menjadikan BPJS, sebagai subordinasi kementerian terkait, dalam lingkup program dan pembiayaan.
- Inkonsistensi RUU Kesehatan. Substansi masuk ke wilayah sektor Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Men-downgrade wewenang Presiden, dengan menempatkan BPJS bertangung jawab pada Presiden melalui menteri terkait.
- Pasal 416 dan 417 RUU Kesehatan, tidak ada satu poin pun memfokuskan pada upaya peningkatan perlindungan dan mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan secara detail dari peserta BPJS. Di samping itu, substansi Pasal 416 dan 417 mengatur materi di luar wialayah sektor kesehatan.
- Memberikan kekuasan yang full power pada menteri terkait sehingga tidak ada check and balances dalam penyelenggaraan pelayananan JKN.
- Tidak sejalan dengan Pasal 34 ayat (2) dan (4) UU Dasar 1945 sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran konstitusi. Memastikan adanya pelanggaran melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Pertanyaan mendasar dari pembahasan di atas, adalah:
- Apakah Menkes siap mengambil risiko dengan di-take over-nya BPJS kesehatan?
- Apakah Menkes siap turut memikul tanggung jawab secara renteng jika terjadi fraud dan atau moral hazard dalam penyelenggaran JKN?
- Apakah Menkes siap pasang badan jika terjadi defisit dana jaminan sosial JKN, yang berimplikasi memburuknya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan?
- Apakah Menkes siap ‘bermohon’ kepada Presiden jika defisit dana jaminan sosial JKN, sebagaimana dilakukan Dirut BPJS Kesehatan, sewaktu defisitnya Dana JKN 4-5 tahun yang lalu?
- Apakah ada jaminan dengan perubahan pasal-pasal UU SJSN dan UU BPJS dalam Pasal 416 dan 4017 RUU Kesehatan, pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai dengan haknya akan lebih baik?
Penutup
Penulis sangat concern soal masuknya pasal-pasal UU SJSN dan UU BPJS yang sifatnya ‘melumpuhkan’ eksistensi Organ BPJS karena pengalaman panjang kami di DJSN sebagai anggota sejak 2008 dan Ketua DJSN 2011-2015, masa-masa sulit dan penuh tantangan dan cobaan dalam menyusun UU BPJS. Pengawalan dan tekanan buruh luar biasa. DPR bulat semua fraksi ingin mengegolkan RUU BPJS. Namun, di kalangan panja pemerintah saat itu ada yang bersikap abu-abu sehingga menyulitkan perumusan RUU BPJS.
Besarnya aset BPJS baik dana Badan dan Dana Jaminan Sosial, mungkin saat ini dari kedua BPJS itu sebesar lebih Rp700 triliun, di duga kuat sebagai penyebab ‘tidak relanya’ kementerian untuk lebih membesarkan BPJS. Jika perlu tetap ‘kerdil’ dan menjadi stunting.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada Menteri Kesehatan dan Baleg DPR, sebaiknya sesuai dengan argumentasi dan rasionalitas berpikir penulis, tidak usah diteruskan pembahasan Pasal 415, 416, dan 417 RUU Kesehatan. Tidak mudah membangun jaringan kerja BPJS yang baru seumur jagung dan sudah memberikan manfaat bagi para peserta, walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Kita perkuat implementasi, bukan dengan merombak UU. Oleh: Dr Drs Apt Chazali H Situmorang, MSc Anggota DJSN 2008–2011/Ketua DJSN 2011-2015/Pemerhati Kebijakan Publik/ Dosen FISIP UNAS (*)



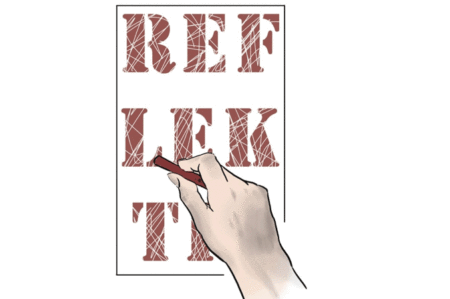




Tinggalkan Balasan