Mengukur Untung dan Rugi Dedolarisasi

Fluktuatifnya kurs mata uang dolar Amerika Serikat beberapa waktu terakhir ini menjadi salah satu topik menguatnya keinginan dari sebagian negara untuk menciptakan alat tukar sendiri. Beberapa negara kemudian menjadikan isu tersebut untuk lebih mengoptimalkan penggunaan mata uangnya dalam transaksi perdagangan internasional.
Berbagai negara pun mulai membuka ruang dialog dengan mitra dagang yang dimiliki untuk memfokuskan penggunaan mata uang domestik dalam transaksi antar negara. Perdagangan antar negara telah berevolusi sejak pertama kali dilakukan. Pada awalnya, barter digunakan sebagai cara bertransaksi. Baik lingkup individu maupun antar negara, barter menjadi pilihan yang sesuai saat itu.
Namun seiring berjalannya waktu, barter memiliki berbagai kelemahan. Keunggulan suatu negara atau keragaman sumber daya yang dimiliki memungkinkan sebuah negara mendapatkan surplus dalam perdagangan. Sebaliknya negara yang tidak memiliki keunggulan berpotensi untuk mengalami defisit dalam perdagangan.
Adanya surplus dan defisit tersebut yang menjadikan mekanisme barter memerlukan instrumen tambahan agar menjadi seimbang. Emas dan perak menjadi pilihan yang digunakan sebagai penyeimbang di dalam perdagangan antar negara. Bagi yang mengalami surplus maka akan mendapatkan tambahan emas/perak sebagai keuntungan dari perdagangan yang terjadi.
Perkembangan perdagangan yang pesat menjadikan instrumen emas dan perak menjadi kurang adaptif dalam penggunaannya. Cadangan yang terbatas serta mekanisme pertukarannya yang kurang fleksibel mengalihkan perhatian semua pihak untuk mencari pengganti emas dan perak di dalam transaksi perdagangan. Instrumen pengganti tersebut yang kemudian disebut dengan uang.
Baca Juga: Meruntuhkan Sistem Patriaki untuk Menjaga Bonus DemografiPada awalnya dolar AS digunakan sebagai katalis mengingat pasca perang dunia kedua perekonomian Amerika Serikat merupakan satu-satunya yang selamat dari kehancuran perang. Sekarang setelah sekian puluh tahun Dolar berkuasa, pertanyaan muncul dari berbagai negara terkait urgensi penggunaan Dolar dalam perdagangan internasional.
Apakah masih diperlukan ataukah dapat digantikan dengan mata uang lain. Relevansi dolar AS kembali dipertanyakan tatkala kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral AS (The Fed) ternyata berdampak pada perekonomian negara lain khususnya yang menggunakan dolar AS sebagai standar nilai.
Dedolarisasi dalam perdagangan sebenarnya bukan menjadi sebuah isu ketika neraca perdagangan antar negara mengalami keseimbangan. Tanpa ada kesepakatan bersama antar negara pun, seandainya tren perdagangan antara negara berimbang maka penggunaan mata uang jelas tidak dibutuhkan sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena pola perdagangan kembali ke era masa awal dahulu yaitu barter.
Namun apabila terdapat surplus dan defisit antar negara maka suka atau tidak suka keterlibatan mata uang sebagai penengah menjadi sebuah kebutuhan. Yang jadi pertanyaan kemudian, mata uang mana yang digunakan? Bagaimana mekanisme penentuan nilai mata uang tersebut, dan negara mana saja yang mau menerima mata uang tersebut?
Beberapa pertanyaan mendasar tersebut perlu dipikirkan dengan matang karena berdampak pada cadangan devisa yang dimiliki oleh sebuah negara. Apabila mata uang yang digunakan merupakan mata uang yang diminati banyak negara dengan kurs yang stabil, tentu saja bukan menjadi sebuah masalah apabila ada negara yang menjadikannya sebagai cadangan devisa. Namun menjadi sebuah keanehan apabila mata uang yang digunakan tidak memenuhi kriteria tersebut.
Tanpa ada mekanisme transparan dan akuntabel dalam pengelolaan mata uang non-dolar, maka sangat dimungkinkan sebuah negara akan mencetak uang baru untuk membayar tagihan dari negara lain. Dan dalam jumlah tertentu, surplus dalam bentuk mata uang lokal ini menjadi tidak likuid akibat minimnya negara yang mau menerima mata uang tersebut.
Perdagangan antara India dan Rusia bisa menjadi contoh sisi negatif penggunaan mata uang lokal dalam transaksi kedua negara. Dalam interaksi keduanya, Rusia mencatatkan surplus sebesar lebih dari $40 miliar yang sebagian besar disumbang oleh penjualan minyak Rusia ke India pada tahun 2022.
Apabila sebelumnya transaksi keduanya menggunakan mata uang dolar sebagai “penengah”, pengenaan sanksi yang dikenakan kepada Rusia membuat kedua negara harus menciptakan alat tukar baru.
Kedua negara “terpaksa” menggunakan mata uang masing-masing sebagai alat pembayaran transaksi perdagangannya. Sayangnya, surplus luar biasa yang dinikmati oleh Rusia harus ditebus sangat mahal. Rusia hanya bisa menerima pembayaran menggunakan mata uang Rupee.
Dan akumulasi Rupee yang membengkak menjadikannya sebagai sebuah aset non likuid bagi Rusia. Tidak banyak negara yang membutuhkan Rupee untuk bertransaksi, sedangkan opsi menyeimbangkan neraca dagang di antara keduanya bukan menjadi pilihan yang mudah saat ini. Alternatif bagi Rusia untuk menggunakan Rupee dalam bertransaksi dengan negara selain India juga bukan merupakan ide yang tepat.
Contoh kedua berkaitan dengan hubungan perdagangan antara Arab Saudi dengan China. Hubungan Arab Saudi dan China jauh lebih mudah dan menguntungkan apabila dibandingkan dengan hubungan India dan Rusia. Arab Saudi mencatatkan surplus dalam perdagangan dengan China setiap tahunnya dari ekspor minyak. Pada tahun 2021, Arab Saudi mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$19,7 miliar dari China.
Keberuntungan dinikmati oleh Arab Saudi meskipun mengalami surplus dan bertambahnya Renminbi sebagai cadangan devisanya. Berbeda dengan nasib Rusia terhadap Rupee, Renminbi jauh lebih mudah untuk diterima banyak negara dibandingkan Rupee.
Perkembangan ekonomi China yang begitu pesat serta meluasnya pasar produk China membuat banyak negara memburu Renminbi untuk bertransaksi dengan China. Namun alih-alih “menjual” Renminbi ke negara lain, Arab Saudi malahan menggunakan surplus tersebut untuk memborong berbagai produk berteknologi tinggi termasuk persenjataan dari China.
Dari kedua contoh di atas, dedolarisasi merupakan potensi namun terselip juga ancaman di dalamnya. Potensi bisa berupa meningkatnya transaksi perdagangan antar negara untuk mengejar keseimbangan ekspor dan impor.
Kasus Arab Saudi dan China membuktikan bahwa ketika Arab Saudi mengalami surplus maka solusi penambahan impor dari China merupakan salah satu cara menyeimbangkan perdagangan. Bertambahnya impor oleh Arab Saudi bermakna adanya peningkatan produksi dan pembukaan lapangan pekerjaan di China untuk memenuhi kebutuhan dari Arab Saudi.
Sedangkan pada kasus India dan Rusia, penambahan aset finansial non likuid justru memusingkan otoritas moneter dalam mengelola devisa. Secara statistik, cadangan devisa akan meningkat disertai variasi mata uang yang beragam.
Namun apabila dihadapkan pada transaksi pembayaran impor, aset non likuid tersebut susah untuk dijadikan alat pembayaran. Satu-satunya cara adalah mengembalikan ke negara penerbit melalui peningkatan impor dari negara penerbit mata uang tersebut.
Dedolarisasi memang akan merumitkan dalam transaksi perdagangan antar negara, masing-masing negara akan mengelola beraneka mata uang dari negara lain sebagai imbas transaksi perdagangan antar negara. Apabila kebijakan tersebut akan diimplementasikan sepenuhnya maka kalkulasi untung rugi khususnya kemungkinan bertambahnya aset-aset non likuid harus mendapatkan perhatian secara khusus. Oleh: Kurniawan Budi Irianto Pejabat pengawas pada Kementerian Keuangan. Opini yang disampaikan merupakan pendapat pribadi penulis, bukan merupakan pendapat resmi dari tempat penulis bekerja. (*)

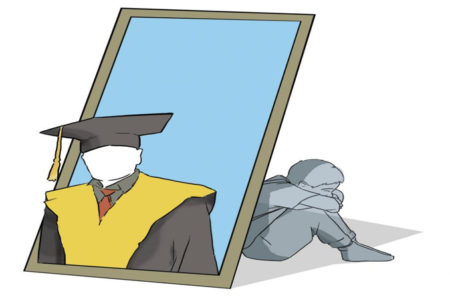


Tinggalkan Balasan