Menghadapi Tahun Ajaran Baru

TIDAK sedikit kalangan yang memandang bahwa di masa pandemi seperti saat ini, kejahatan-kejahatan terhadap anak pun semakin meningkat dan kian brutal. Untuk memastikannya, tentu dibutuhkan kajian sistematis. Namun, paling tidak, tersedia sejumlah alasan untuk membangun asumsi sedemikian rupa. Pertama, banyak keluarga yang kiranya mengalami tekanan psikologis dan sosial yang semakin hari semakin berat. Berhadapan dengan kondisi batin yang terpuruk, seiring dengan frustrasi yang bertumpuk, bisa jadi sebagian orangtua atau anggota keluarga sang anak yang akan ‘mengelolanya’ dengan cara-cara kekerasan. Kedua, anak menghabiskan waktu lebih lama lagi di dalam rumah. Bila dianggap bahwa kebanyakan pelaku kejahatan terhadap anak ialah justru orang terdekat anak, lebih lama berada di rumah sama artinya dengan lebih lama sang anak berada dalam penguasaan orang dekat.
Peluang bagi viktimisasi pun semakin meninggi. Ketiga, ketergantungan anak pada gawai dan aktivitas daring juga menghadirkan ancaman-ancaman baru bagi anak. Kejahatan tidak lagi disyaratkan bahwa pelaku dan korban harus berada di lokasi geografis yang sama, tetapi dapat melalui media virtual. Keempat, meski anak-anak gencar diedukasi tentang betapa bahayanya virus korona, edukasi tentang keterampilan hidup secara umum (dulu sering diistilahkan sebagai new normal) tampaknya masih senjang. Akibatnya, pada musim pagebluk ini keterampilan anak untuk mencari pertolongan pun sangat mungkin tidak turut terbangun meski momentum untuk pembangunan keterampilan itu sudah berlangsung sejak tahun silam.
Pada waktu-waktu lampau, sangat banyak orangtua dan pendidik yang mengakui kesulitan luar biasa yang mereka alami saat ingin mendidik anak atau murid dengan kebiasaan baik. Dilarang merokok malah anak merokok. Diatur agar beribadah tepat waktu justru bermalas-malasan. Atau agar membatasi jam selancar daring direspons dengan kucing-kucingan main ponsel. Kerumitan itu pun dirasakan semakin berat pada masa wabah. Ringkasnya, anak atau murid semakin sulit dikendalikan. Barangkali andai dilakukan kajian, mengacu pada testimoni di atas, akhir-akhir ini semakin banyak dijumpai anak yang mengalami gangguan perilaku (conduct disorder).
Ada tantangan Atas segala keluh kesah itu, saya melihatnya dari dua sisi. Pada satu sisi, dulu, anak-anak berkesempatan mengalami pendisiplinan diri di sekolah. Melalui kegiatan bersama para guru dan teman-teman mereka. Dua pihak itu memang sering kali lebih efektif membentuk perilaku baik. Kini anak-anak melalui pendisiplinan diri hanya dengan satu ‘kurikulum’, yakni ‘kurikulum rumah’. Metodenya sering keliru karena ‘sang guru’ tak memiliki wibawa sebesar wibawa para guru di sekolah. Akibatnya, tendensi (tepatnya bias) anak-anak yang menilai diri mereka serbamampu justru semakin tertantang oleh orang-orang dekat mereka. Kedua, suratan alam bahwa keadaan di seputar pandemi ini memang bertentangan dengan kodrat anak sebagai—katakanlah–manusia yang tidak bisa diam untuk waktu yang lama berhadapan dengan stimulus yang itu-itu saja. Kedua hal di atas telah cukup untuk memunculkan backfire effect. Manifestasinya, semakin anak diberikan ajaran kebaikan, perilaku mereka justru semakin tak menentu. Semakin diarahkan, semakin melawan. Orangtua naik pitam, anak justru terdorong lebih kuat untuk ‘balas dendam’. Sampai di situ, layanan-layanan bantuan yang sebelumnya efektif pun kini mengalami kevakuman.
Atau setidaknya menurunkan tempo kerja mereka secara signifikan. Jadi, tanpa perlu didramatisasi, siapa pun sesungguhnya dapat menyaksikan bahwa kehidupan anak-anak di musim wabah ini menghadirkan persoalan yang sangat kompleks untuk dipecahkan. Setelah berhadapan dengan situasi pelik demikian, melalui tulisan ini saya tidak ingin berlebihan menyodorkan langkah-langkah solusi. Juga saya akui, berbagai perspektif dan pesan tentang pengasuhan yang dulu sering saya berikan kini membutuhkan revisi besar-besaran pada tataran teknis. Fondasi dasarya masih tetap sama, yaitu cinta, dialog, dan bermain. Namun, bagaimana menerjemahkan itu semua ke tataran praktik, korona memaksa saya untuk mengkaji ulang satu per satu. Kemiripan nasib, perkiraan saya, juga dialami oleh—utamanya–kelompok bermain (KB) dan taman kanak-kanak (TK).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi dan Pelajaran dari IndiaKegiatan daring jelas bukan metode yang dapat dipraktikkan untuk kedua jenjang pendidikan tersebut. Atas dasar itu, patut kita berharap bahwa mengembalikan kegiatan belajar-mengajar di sekolah akan sedikit banyak memulihkan anak-anak ke kondisi mendekati normal. Memang, opsi apa pun yang tersedia selalu berpotensi mendatangkan baik dampak positif maupun negatif bagi anak-anak. Tak terkecuali, siapa pun mafhum, kemungkinan anak-anak terkena covid-19. Kita memberikan semangat kepada para pemangku kepentingan untuk benar-benar mendesain program pembelajaran tatap muka dengan berdasarkan hasil riset dan evaluasi berkesinambungan.
Yang ingin saya pesankan melalui naskah ini ialah sisi substansi pembelajaran tatap muka itu nantinya. Bukan materi akademik yang dijejalkan ke kepala murid. Apalagi muatan padat karya berisi materi kelas berjalan ditambah materi kelas sebelumnya yang dibahas ulang. Beban belajar seperti itu hampir dapat dipastikan akan membuat para murid mengalami emotional breakdown. Mereka tidak lagi sebatas goyah, tapi bahkan akan runtuh. Sebagai gantinya, yang paling mendasar, setelah terkungkung dalam berbagai kompleksitas hidup selama berbulan-bulan, para murid perlu diberi kesempatan lebih lapang untuk mengemukakan isi hati mereka. Para guru patut membuka diri untuk menyimak ekspresi kesedihan, ketakutan, bahkan amarah para murid.
Sarjana psikologi menyebut proses itu sebagai katarsis atau emotion focused coping. Itulah kegiatan belajar-mengajar yang paling dibutuhkan sekaligus paling realistis untuk diselenggarakan melalui sekolah tatap muka nantinya. Masa tahun ajaran baru akan datang beberapa pekan lagi. Kementerian pendidikan dan kementerian perlindungan anak perlu duduk bersama merumuskan secepat mungkin program penyiapan seluruh guru di Tanah Air agar mampu berperan layaknya guru bimbingan konseling. Semua kalangan, khususnya di lingkungan pendidikan, patut memiliki kesadaran yang bersama; tahun ajaran baru ialah masa rehabilitasi kolektif nasional. Semoga.



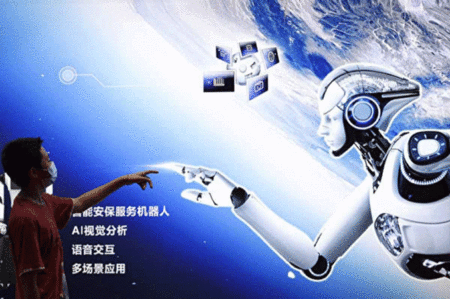
Tinggalkan Balasan