Mencermati Perubahan Stance Kebijakan Moneter Global

PERKEMBANGAN ekonomi dunia yang sangat volatile akhir-akhir ini telah menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Ketika pandemi covid-19 hampir berakhir menuju fase endemi, kini dunia dihadapkan pada perang di Ukraina yang sudah berlangsung delapan bulan terakhir dengan segala risikonya. Perang menimbulkan efek tidak baik bagi perekonomian dunia karena mendisrupsi rantai pasokan global yang mendorong lonjakan harga energi dan pangan. Hampir sebagian besar negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi, disertai inflasi tinggi atau disebut stagflasi. Beberapa negara maju jatuh ke resesi, misalnya Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Jerman. Untuk tahun ini, IMF memperkirakan perekonomian dunia, negara maju, dan negara berkembang tumbuh masing-masing 3,2%; 2,4%; dan 3,7%. Untuk 2023, masing-masing diperkirakan tumbuh 2,7%; 1,1%; dan 3,7%. Khusus Rusia diproyeksikan akan mengalami kontraksi minus 3,4% tahun ini dan minus 2,3% tahun depan. Kondisi ekonomi Rusia bisa lebih memburuk jika perang tidak segera berakhir.
Stance kebijakan moneter ketat Pelemahan ekonomi global sudah mulai terlihat dari indikator purchasing managers’ index (PMI) manufaktur global yang turun dari 51,1 ke 50,3 pada Agustus 2022 lalu. Dari negara-negara G-20 dan ASEAN-6, hanya 24% yang aktivitas manufakturnya masih di zona ekspansi (level PMI di atas 50) dan meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mereka ialah Indonesia, Thailand, Filipina, Rusia, Vietnam, dan Arab Saudi. Satu-satunya negara maju di Eropa yang juga anggota G-20 yang mengalami perbaikan dari PMI level kontraksi (di bawah level 50) ke PMI level ekspansi (level di atas 50) ialah Prancis. Sementara iyu, negara-negara yang PMI-nya masuk zona kontraksi antara lain Jerman, Italia, Inggris, Tiongkok, Korea Selatan, Kanada, Meksiko, Spanyol, dan Turki. Diyakini, bank sentral AS, The Federal Reseve Bank, akan terus menaikkan suku bunga acuan (Fed fund rate/FFR) sampai inflasi terkendali pada level 2%. The Fed diperkirakan tetap menaikkan FFR sebesar 0,75% menjadi 3,75%-4,0% pada pertemuan 3 November. Saat ini konsensus global memperkirakan FFR akan berada di 4,0%-4,25% pada akhir 2022, lebih tinggi daripada 3,5% yang semula diperkirakan pada tiga bulan lalu. Level FFR akan tetap tinggi pada 2023 sebelum pelonggaran dimulai pada 2024.
Hal lain yang patut diwaspadai para pengambil kebijakan di pemerintahan dan bank-bank sentral di kawasan Asia ialah risiko terulangnya tekanan di pasar keuangan menuju krisis mata uang karena terpantau dua mata uang penting di kawasan ini, yaitu yen dan yuan, menunjukkan pelemahan yang tajam terhadap dolar AS. Yuan menempati lebih dari seperempat bobot indeks mata uang Asia, sedangkan yen ialah mata uang global ketiga yang paling banyak diperdagangkan sehingga pelemahannya memiliki dampak yang sangat besar pada mata uang Asia. Dua mata uang Asia tersebut melemah karena meningkatnya kesenjangan arah kebijakan The Fed yang ketat (hawkish) dengan kebijakan bank sentral Tiongkok dan Jepang yang longgar (dovish). Langkah intervensi oleh bank sentral tiap negara dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar yen dan yuan sehingga daya tarik kawasan itu sebagai tujuan bagi para investor pemburu aset berisiko dapat terjaga. Jatuhnya mata uang dari dua ekonomi terbesar di kawasan itu dapat membengkak menjadi krisis jika kejatuhan yen dan yuan menyebabkan pemilik dana luar negeri (asing) menarik uang mereka keluar dari Asia, yang mengarah ke pelarian modal besar-besaran. Investor global sudah mulai menarik dana mereka keluar dari Asia. Para pengelola dana global telah menarik US$44 miliar dari bursa saham Taiwan tahun ini, sebesar US$20 miliar dari ekuitas India, dan US$13,7 miliar dari bursa saham Korea.
Sementara itu, pasar obligasi Indonesia mengalami arus keluar sebesar US$8,2 miliar. Lagi-lagi divergensi kebijakan moneter antara AS (The Fed) yang hawkish dan Jepang (BoJ) yang dovish menjadi penyebab melemahnya yen. Yen jatuh melewati 145 per US$ untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade. Sementara itu, yuan tergelincir melewati level kunci 7 per US$, di bawah tekanan hawkish The Fed. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan krisis pasar properti di Tiongkok, semakin membebani yuan.
Indonesia tetap optimistis Mengingat Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka, dinamika eksternal akan memberi dampak baik langsung maupun tidak langsung. Perlambatan ekonomi dunia disertai penyesuaian stance kebijakan ekonomi global akan tertransmisi melalui jalur perdagangan, investasi, dan keuangan. Kesigapan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang tepat dan terukur menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Tepat jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memperingatkan ancaman resesi di tengah gejolak ekonomi global. Bahkan menurutnya, dunia dipastikan akan mengalami resesi pada 2023. Secara umum, perubahan stance kebijakan bank-bank sentral di dunia yang condong hawkish tentu menjadi perhatian Bank Indonesia (BI). Terkait dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah yang tertekan terhadap dolar AS, BI menerapkan langkah teknis triple interventions. Langkah itu dilakukan melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan obligasi. Lalu, keputusan BI pada 20-21 Oktober 2022 menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 50 bps ke level 4,75% merupakan langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking yang tepat, timely, dan antisipatif untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3,0±1% pada paruh pertama 2023 nanti. Jelas keputusan ini juga untuk menjaga nilai tukar rupiah yang stabil sejalan dengan nilai fundamentalnya karena tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Baca Juga: Memilih Pemimpin BangsaUntuk itu, diperlukan sikap optimistis dan tenang serta waspada tinggi menjadi penting guna menghadapi outlook perekonomian global yang dinarasikan melambat, gelap, mendung, tidak pasti, dan penuh kecemasan disertai badai sempurna. Kompleksitas permasalahan global masih akan mengiringi, dari berlarut-larutnya perang di Ukraina yang meningkatkan risiko geopolitik, risiko disrupsi rantai pasokan global, risiko krisis energi dan pangan, risiko fragmentasi antarkawasan serta antara kelompok negara dan divergensi stance kebijakan ekonomi dan politik mereka yang tajam, hingga risiko perubahan iklim yang ekstrem dan gradual.Oleh: Ryan Kiryanto Ekonom dan Co-founder & Dewan Pakar Institute of Social, Economic, and Digital (ISED)



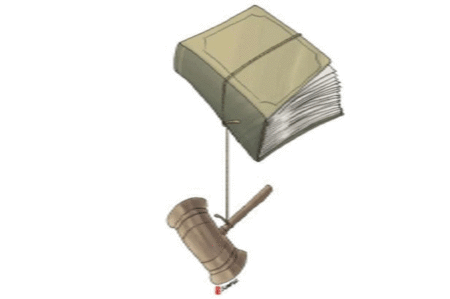
Tinggalkan Balasan