Membangun Sinergi Komunitas Gerakan Islam Wasatiah

AKHIR-AKHIR ini, kita dijejali adanya dua titik kelompok ekstrem yang mendera memenuhi lingkungan pemikiran dan tindakan kita. Dua titik kelompok ekstrem itu ialah sekularisme ekstrem yang menuntut adanya ruang kebebasan individual secara mutlak dan agamaisme ekstrem yang menahbiskan diri sebagai pemegang otoritas kebenaran dan kunci surga, dengan pandangan bahwa semua yang berasal dari pandangan komunitas nonagama pasti sesat, salah, dan menyesatkan.
Saat ini, titik kelompok ekstrem yang pertama berdiri tidak hanya berhadap-hadapan dengan komunitas di luar diri mereka, yang biasanya berasal dari kalangan kelompok agama, tetapi juga telah berdiri menentang dan mencela komunitas di dalam diri mereka, yang dipandang tidak cocok dan menghalangi eksistensi kelompok ekstrem pertama ini, seperti kaum rasional falsafi dan kaum gerakan sosial.
Untuk titik kelompok ekstrem kedua memang sudah menjadi kebiasaan mereka, yakni sangat tegap dan gagah melawan komunitas mereka sendiri dari kalangan agamawan yang berbeda pandangan dan mazhab dengannya, dengan mengatakan pandangan komunitas agama nonkelompok mereka kurang tepat dan kurang sesuai dengan isi dan tafsir ajaran inti agama. Apatah lagi, terhadap kaum sekular dan rasional falsafi, kelompok itu sudah pasti memandang mereka sebagai kafir.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana kelompok beragama dapat menjaga nalar kritis nan jernih untuk merawat kewarasan publik keagamaan dari pengaruh dua kelompok ekstrem itu?
Paradigma dua kelompok ekstrem
Baca Juga: Hidden Agenda Dibalik Putusan Penundaan Pemilu 2024Paradigma berpikir kelompok ekstrem pertama dapat dilacak dari ‘kebencian’ mereka terhadap kesewenangan kelompok agama terhadap publik luas yang terjadi pada abad pertengahan. ‘Luka’ itu masih menganga. Persekongkolan jahat aristokrasi dan agama telah mengebiri hak individu. Pengalaman luka yang mendalam itu telah menjadi trauma berat sehingga menjadi ekstremitas hebat dalam memandang orang mempraktikkan keberagamaan.
Inilah ekstremitasnya: agama dan seluruh atributnya tidak boleh hadir di ruang publik. Agama dan negara harus dipisahkan. Karena agama dapat menghalangi kebebasan individu; agama yang bersekongkol dengan negara, dan negara yang kemudian dikuasai orang jahat yang menggunakan legitimasi agama untuk menancapkan kekuasaannya, akan membuat ruang publik menjadi ajang otoritarianisme negara-agama.
Tidak boleh ada yang berbau agama di ruang publik. Sebaliknya, kritik dan ‘penghinaan’ terhadap agama dan simbol-simbolnya merupakan kepahlawanan yang hebat. Bila ada kritik terhadap sikap kelompok ekstrem, baik terkait pandangan mereka tentang ketidakbolehan agama masuk ke ruang publik atau ‘kritik dan penghinaan’ terhadap agama dan simbol-simbolnya, dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan falsafah kebebasan individu yang sangat dilindungi di Prancis, misalnya, sebagai salah satu contohnya.
Salah satu contoh pandangan yang disemangati ‘kebencian’ Eropa terhadap agama pada abad pertengahan adalah pandangan Ernest Gellner. Dia berpendapat dalam buku Muslim Society (1981) bahwa Islam baik sebagai agama ataupun komunitas/masyarakat tidak akan pernah kompatibel dengan demokrasi, terutama dalam konteks kebebasan individu. Kenapa? Karena konsep percaya satu Tuhan (tauhid) dan konsep umat sebagai masyarakat dalam Islam bersifat tertutup.
Sifat tertutup Islam sebagaimana dapat dipahami dari tauhid dan umat, menurut Gellner, ialah gambaran Islam tidak dapat hidup dalam wilayah keterbukaan berpikir, penghormatan terhadap kebebasan individu dan kebebasan beragama. Pandangan Gellner itu bisa dinilai tidak jernih karena ahistoris. Berbeda, misalnya, dengan pandangan Robert N Bellah dan Karen Amstrong, yang berpijak pada ajaran inti Islam, juga sejarah kenabian Muhammad SAW serta sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun sistem sosial kepemimpinan di Madinah dengan cara yang elegan dan menghargai pluralitas.
Sementara itu, secara umum gambaran kelompok ekstrem kedua dapat dilacak pada tiga uraian yang bertolak belakang dengan kelompok ekstrem terdahulu. Pertama, pada cara pandang tekstualis mereka yang ekstrem. Kedua, pada sikap politik mereka yang selalu menggunakan legitimasi agama untuk meraih simpati publik. Terakhir, pada sikap antipatinya terhadap Barat.
Muhammad Imarah (1986) menyebut cara pandang pertama kelompok ekstrem kedua itu sebagai cara pandang kaum salafiyah tektualis (al-salafiyah al-nususiyah) dengan ciri pemikiran: menolak dan mengingkari akal (al-‘aql) dan rasionalitas (al-‘aqlaniyah), dan to some extent, cenderung memberhalakan teks.
Sebagai implikasi dari perspektif manhaji tekstualisnya, kelompok ekstrem model kedua itu, menurut Bassam Tibi dalam buku berjudul Islam dan Islamisme (versi terjemahan terbitan Mizan 2012), sering kali menonjolkan Islamisme-nya. Islamisme ialah wajah politik keagamaan Islam, yakni wajah politik yang menggunakan simbol agama untuk tujuan politik. Islamisme tidak didasarkan pada iman religius Islam, tetapi pada penerapan ideologis atas agama di ranah politik. Dengan kata lain, Islamisme ialah penafsiran keagamaan yang diturunkan dari tafsir politis atas Islam.
Sikap politis itu semakin mempertegas perbedaan antara Islamisme dan Islam. Pada satu sisi, bagi Islam, umat Islam itu bisa hidup damai dengan nonmuslim. Keimanan Islam bukanlah penghambat bagi perdamaian atau juga ancaman bagi muslim lainnya. Pada sisi yang lain, Islamisme justru sebaliknya, menciptakan keretakan peradaban antara muslim dan nonmuslim.
Sikap anti-Barat lebih banyak disebabkan bukan oleh kajian ilmiah atau kerja sama setara, melainkan lebih banyak terkait dengan kebaperan budaya, metode ilmu pengetahuan, dan moralitas Barat. Bagi kelompok itu, Barat itu sesat, sekuler, dan tidak memberikan dampak yang baik bagi komunitas muslim. Barat itu mengajarkan kebebasan berpikir yang bertentangan dengan Islam dan dapat membuat degradasi terhadap otoritas wahyu. Sikap anti-Barat itu juga jalin-berkelindan dengan sikap politik mereka. Mereka menggunakan sentimen anti-Barat untuk akumulasi pragmatisme politik dalam rangka meraih simpati publik.
Gerakan itu secara politik bisa saja oleh mereka dipandang berhasil. Namun, menurut Abdul Karim Soroush (Mizan, 2002), landasan berpikir dalam membangun gerakan anti-Barat itu secara ilmiah sejatinya telah menjalankan sistem berpikir dan prosedur yang salah. Kesalahan utama kelompok ekstrem model kedua itu terletak pada pandangan mereka bahwa Barat itu monolitik. Padahal, Barat itu tidak monolitik sehingga bila kita melihat Barat yang sekuler tidak serta-merta dapat digeneralisasi sebagai referensi penilaian yang salah atau benar tentang Barat dan peradaban mereka. Bila dua ekstremitas di atas berlaku dalam Islam, justru membuat kita jauh dan semakin jauh dari kewarasan dan nalar kritis beragama.
Merawat kewarasan dan nalar kritis beragama
Salah satu cara terbaik bagi seorang muslim untuk merawat kewarasan publik dan menjaga nalar kritisnya dalam beragama ialah dengan menggaungkan cara berpikir dan bertindak tengahan (tawassuth). Di antara definisi paling sederhana dari cara berpikir dan bertindak tengahan, yaitu, pertama, tidak ta’assub (mementingkan kelompok/golongan) dalam beragama.
Kedua, selalu siap menjadi penyaksi terhadap suatu peristiwa atau isu yang terjadi. Penyaksi di sini bisa diistilahkan dengan ungkapan lain: selalu berpikir jernih dan tidak reaktif-negatif terhadap suatu peristiwa apa pun bahkan ketika peristiwa tersebut seolah merugikan dan menyerang diri atau komunitasnya. Terakhir, selalu berpikir terbuka dalam menerima perbedaan, serta tidak dogmatis dalam beragama.
Cara berpikir dan bertindak tengahan itu belakangan disebut dengan Islam wasatiah. Seperti dijelaskan Din Syamsuddin, berpikir dan bertindak tengahan itu bukan berarti tidak ke sana dan tidak kemari, plin-plan, tidak ajek, dan bahkan tidak punya sikap sama sekali. Justru, sikap tengahan itu ialah suatu sikap yang didasarkan pada pikiran jernih dan terbuka, berdasarkan data, dilandasi sikap kearifan, dan selalu berpijak kepada kemaslahatan bersama, dalam bingkai kepentingan yang lebih besar. Secara lebih teknis, Din Syamsuddin menjelaskan umat Islam sebagai umat tengahan harus selalu menjadi ‘mediating and moderating forces’. Contoh yang dapat dijadikan referensi ialah yang dilakukan Rasulullah SAW terkait dengan Hajar Aswad.
Pelajaran penting yang diberikan Rasulullah SAW adalah, pertama, menjadi penyaksi yang mengamati dan mempelajari. Kedua, hadir dengan pikiran jernih dan cemerlang. Ketiga, meski sejatinya sebagaimana para kepala suku dan kabilah Arab itu sudah berkomitmen dan bersepakat terhadap siapa pun yang hadir di Kabah terlebih dahulu sebelum yang lain datang ialah pemutus serta yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, Rasulullah SAW sebagai yang hadir terlebih dahulu tidak jemawa dan berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW masih berkenan mengajak serta yang lainnya dalam visi bersama.
Fakhruddin al-Razi mengingatkan kita akan pentingnya berpikir jernih dan tidak ta’assub. Kata beliau: “Untuk memperoleh pandangan yang tepat dan baik terkait ayat muhkamat dan mutasyabihat, sebaiknya seorang muslim tidak menjadikan penafsirannya sebagai legitimasi pandangan mazhabnya. Sebaiknya, juga tidak memaksa Al Qur’an sesuai dengan pandangan mazhabnya. Pandangan yang hanya untuk menjawab kepentingan mazhab tentu tidak jernih, dan mungkin menjadi jauh dari maksud Allah SWT.”
Imarah memberikan jawaban solutif-metodologis dalam menyikapi dua titik kelompok ekstrem sekularisme ekstrem dan agamaisme ekstrem, yaitu mengusulkan urgensi penerapan rasionalitas Islam (al-‘aqlaniyah al-Islamiyah). Rasionalitas Islam, menurut Imarah, memiliki dua kaki sekaligus sayap: akal (al-‘aql) dan wahyu (al-naql) yang secara harmonis diciptakan Tuhan semesta alam untuk berdampingan melengkapi pemikiran manusia.
Sinergi komunitas gerakan Islam wasatiah
Islam wasatiah ingin menegaskan bahwa Islam harus hadir bukan dengan kepentingan jangka pendek atau kasuistis. Islam sebaliknya harus hadir sebagai ajaran yang diproyeksi, dan dipahami, dalam relevansi program jangka panjang. Membumi dan bersinergi dengan kepentingan kemaslahatan umat secara lebih luas.
Islam wasatiah perlu menjadi sinergi komunitas gerakan. Sinergi komunitas ialah sebuah sinergi yang lahir dari grass root dan elite sekaligus yang siap berkolaborasi dalam mencapai dan menggapai maslahat yang besar. Dalam sinergi komunitas, antara grass root dan elite perlu ada kesetaraan penilaian peran sehingga dalam memainkan peran masing-masing dapat bekerja dan mencapai target secara maksimal.
Asal muasal gerakan sinergi komunitas ialah dari publik. Bukan dari negara. Namun, sebagai inisiator bisa bersifat kolaboratif. Yang diharapkan dari asal muasal gerakan publik ialah adanya kesadaran yang masif dimiliki publik dalam mengemban suatu visi tertentu, dalam hal ini ialah Islam wasatiah. Muhammadiyah dan NU yang sudah teruji memiliki pandangan Islam wasatiah, serta teruji membangun kesadaran publik untuk melakukan sinergi komunitas, bisa menjadi lokomotif gerakannya. Wallahu a’lam. Oleh: Piet Hizbullah Khaidir Ketua Divisi Kaderisasi dan Publikasi MTT PWM Jawa Timur 2022-2027, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI) Lamongan (*)

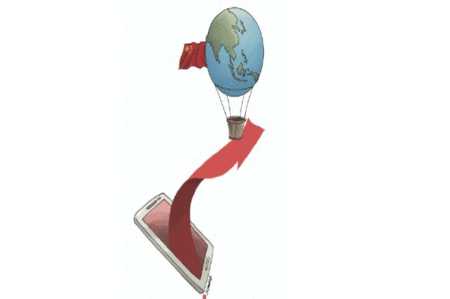


Tinggalkan Balasan