Inkonsistensi Elite, Standar Ganda, dan DOB Papua
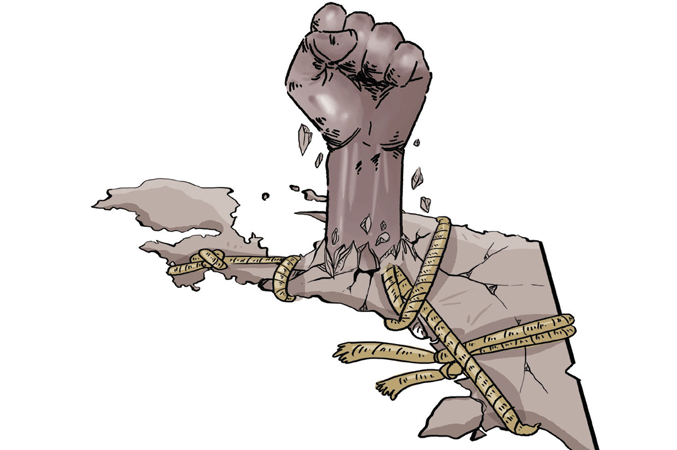
PADA 20 Juni 2022, Komisi II DPR RI akan memulai pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran provinsi–provinsi di Papua. Tiga DOB itu ialah Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Dari jadwal dan agenda pembahasan tiga RUU DOB oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah tampaknya mengejar target akhir Juni telah ditetapkan.
Sementara di daerah selama dua bulan terakhir atmosfer politik lokal terjadi pro-kontra, masyarakat nyaris terbelah antara yang pro versus kontra DOB. Pro-kontra ini bukanlah hal baru di Papua. Sejak 2003 melalui percepatan pemekaran Irian Jaya Barat atau kini Papua Barat (UU No 45 Tahun 1999, Inpres No 1 Tahun 2003) dinamika dan suhu politik yang tinggi mempermasalahkan kehadiran Irian Jaya Barat mencapai titik nadir terganggunya relasi Jakarta–Jayapura.
Polemik bukan saja di kalangan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga antara Pusat dan Papua sehingga menyita perhatian masyarakat politik Indonesia saat itu. Pengalaman empiris pro-kontra percepatan pemekaran Irian Jaya Barat (2003) memperkuat pandangan dan pendapat saya untuk mencermati dinamika pro-kontra tiga DOB 2022 ini. Ada benang merahnya yang dapat ditarik dari dua dimensi, yaitu dimensi filosofis dan sosiologis.
Pertama, dari dimensi filosofis pemekaran tiga DOB di Papua hendak memperteguh fondasi tentang desentralisasi kekuasaan pusat ke daerah (Papua) sekaligus memperkuat demokratisasi rakyat untuk memperkukuh fondasi kebangsaan Indonesia. Kedua, dari dimensi sosiologis, DOB Papua berikhtiar membangun relasi yang harmonis antara pusat dan Papua, terutama rakyat untuk mengembalikan kepercayaan dan ‘keyakinan’ masyarakat akibat implementasi Otsus (UU No 21 Tahun 2001) yang selama 20 tahun (2001–2021) belum mencapai sasaran dan tujuannya. Bahkan masyarakat terutama orang asli Papua (OAP) sebagai subjek dan objek dari implementasi kebijakan khusus tersebut belum mendekatkan mereka pada kesejahteraan dan keadilan.
Hal ini pun menimbulkan ‘polemik’ saling menyalahkan antara pusat dan Papua. Ada inkonsistensi saling tolak kesalahan antara pusat dan Papua terhadap ekses yang timbul akibat praktik otonomi khusus (otsus). Sampai di sini saya tak mau terjerembab tentang siapa yang salah dan siapa yang mesti bertanggung jawab. Namun, jujur belajar dari kesalahan dan kekeliruan selama 20 tahun pelaksanaan otsus ada sisi positif dan juga negatifnya. Hal ini perlu pengakuan bersama untuk koreksi dan evaluasi guna memperbaiki implementasi otsus ke depan (2022–2041).
Baca Juga: Membudayakan Belanja Pemerintah Untuk Menggunakan Produk Dalam NegeriSingkat kata dari dimensi filosofis tentang pemekaran tiga DOB Papua dan dimensi sosiologisnya ada ikhtiar pusat dan juga daerah untuk akselarasi pembangunan Papua, guna mendekatkan masyarakat asli Papua kepada kesejahteraan dan keadilan. Pemandangan perjumpaan bersama ini yang menimbulkan abstraksi sikap politik elite Papua, baik di birokrasi pemerintahan maupun kekuasaan yang menurut Vedi R Hadiz disebut Lokalisasi Kekuasaan (2020).
Lokalisasi kekuasaan maknanya pascareformasi telah terjadi desentralisasi power dan sharing kekuasaan ke daerah dalam rangka demokratisasi. Namun, pada saat yang sama pada tingkat lokal telah melahirkan elite–elite lokal yang terbentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan, kesukuan, atau klan yang meraih kekuasaan melalui pilkada. Itu sebabnya terjadilah enclave elite yang kemudian otoritatif menguasai sumber daya baik politik dan ekonomi di daerah.
Lokalisasi kekuasaan tersebut dengan elite yang membentuk enclave di daerah akibat desentralisasi asimetrik Papua yang selama ini telah menikmati previles dan laba politik dan ekonomi merasa terancam tatkala tiga RUU DOB pemekaran provinsi diintrodusi melalui revisi UU No 21 Tahun 2001 menjadi UU No 2 Tahun 2021 (Pasal 76 ayat 2). Plus dalam satu dekade terakhir menurut pengakuan beberapa kepala daerah terjadi diskrimansi dan ketidakadilan dalam sharing program dan dana–dana pembangunan, termasuk dana otsus. Bahkan dalam satu wilayah pun terdapat ketidakadilan perhatian yang hanya terkonsentrasi pada kabupaten–kabupaten tertentu.
Hal itu kemudian terkristalisasi berbarengan dengan waktunya dilakukan revisi atau perubahan UU Otsus. Hal ini memiliki dasar dan korespondensi administrasi pemerintahan oleh pusat sejak 2019 kepada Papua agar menyiapkan draf revisi, tetapi tak pernah diindahkan. Akhirnya pusat mengambil alih kewenangan tersebut melalui usul inisiatif dengan mengingat tenggat final pemberlakukan dana otsus 2% setara DAU nasional pada 2021.
Dalam revisi otsus bukan saja menyangkut penerimaan dan penerimaan dana otsus ke Papua dan Papua Barat, tapi dilakukan tinjauan terhadap Pasal 76 (UU 21/2001), yakni kata ‘dapat’ bukanlah absolut, tapi dinamis sehingga menjadi entry point kepada pusat, baik eksekutif maupun DPR RI otoritatif untuk melakukan pemekaran provinsi/kabupaten/kota di Papua. Meskipun banyak kalangan terutama dari kota di Papua. Meskipun banyak kalangan terutama dari DPRP pada saat akhir pembahasan di Pansus DPR RI menyampaikan usulannya, situasi politik di DPR RI telah memasuki enjuri time.
Diskursus seputar elite politik (kekuasaan) dengan segudang previles (keistimewaan) yang menguasai sumber daya beririsan dengan tiga RUU pemekaran provinsi di Papua menimbulkan kontraksi. Kontraksi ini melahirkan inkonsistensi dengan pernyataan dan ucapan yang pernah terlontar beberapa tahun menuntut pemekaran provinsi dan kabupaten disertai ‘ancaman’ kepada pusat jika tidak dilakukan pemekaran. Inkonsistensi ini kemudian mengendap dalam kesadaran elite lokal untuk mempertahankan previles yang selama ini telah mereka peroleh berupa keuntungan politik dan ekonomi, dengan mengekstrak dan memanipulasi dimensi sosial rakyat yang seolah–olah memiliki ‘keikhlasan’ membenarkan tindakan dan mengaminkan kehendak mereka.
Pada aras ini telah diabaikan perbincangan bagi keadaban politik. Keadaban politik telah dikotori dengan previles dan keuntungan ekonomi politik (kekuasaan) yang telah dicicipi dan dinikmati selama ini. Previles dan kenikmatan ini dalam benak dan skenarionya tetap dipertahankan bila perlu 100 tahun lagi. Kondisi semacam ini hendak di-status quo, tapi tuntutan pemencaraan provinsi dianggap palu godam yang telah menghantam keseluruhan rancangan dan skenarionya.
DOB provinsi telah menjungkirbalikan ilusi dan sekaligus koreksi serentak untuk merekonstruksi pemekaran provinsi berbasis wilayah budaya agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan menjadi konsentrasi setiap wilayah. Seperti tesis EF Schumacher (1973), small is beautiful (kecil itu indah). Sesuatu yang menjadi kekhawatiran bahwa pemekaran provinsi akan berdampak terhadap marginalisasi OAP dan kedahsyatan arus migrasi. Namun, pertanyaan kritis, apakah dengan satu wilayah provinsi atau dua wilayah administrasi pemerintahan mampu mengeliminasi arus migrasi dari luar. Sementara itu, realitas politik selama dua dekade otsus sebagai paradigma juridis dan politik (kebijakan) yang mana kekuasaan politik justru totalitas di tangan pejabat OAP.
Permasalahannya sampai di mana keberpihakan dan proteksi terhadap masyarakat Papua? Memang diakui ada keberpihakan dan proteksi yuridis formal (perdasi/perdasus) dan diskresi. Namun, produk legislasi itu tak bermakna pada tingkat implementasi. Bahkan parsial tidak terstruktur dan terinsitusionalisasi akibatnya tak memiliki basis referensi yang kuat dan tidak memperoleh dukungan yang legitimate dari pusat pada tingkat aplikatif.
Otsus dilakukan tanpa makna, tanpa evaluasi, dan koreksi bersama. Pada level ini bukan saja inkonsistensi, tapi juga standar ganda tatkala kepentingan pragmatis mempertahankan kekuasaan terancam dan ‘kue’ kekuasaan pun terbagi akibat kebijakan DOB, maka rakyat dijadikan ‘tameng’ dengan berbagai pembenaran dan ancaman pun dimanfaatkan mulai dari isu marginalisasi hingga Papua merdeka.
Labilitas sikap, relasi sosial yang cair, eksklusifisme kelompok atau klan, dijadikan pembenaran untuk mempertahankan konsistensi semu menolak DOB. Padahal, lupa bahwa pemekaran provinsi pernah menjadi tema dan bahkan ancaman kepada pusat jika tidak diwujudnyatakan. Dengan cara semacam ini, kekuasaan politik mendominasi hasrat mempertahankan kekuasaan dan previlesnya di satu pihak dan di lain pihak ada inkonsistensi sikap dan perilaku politik menolak permohonan dan ancaman terhadap DOB, yang pernah terucap dari bibir pejabatnya. Sebuah proses penjungkirbalikan permohonan DOB dimasa lalu demi terus mempertahankan akumulasi keuntungan yang menumpuk. Dalam perilaku politik semacam itu kita dapat menangkap secara transparan sebuah pembongkaran mentalitas konsistensi semu yang akhirnya melecehkan elitenya sendiri. Oleh: Frans Maniagasi Pengamat politik lokal Papua.












Tinggalkan Balasan