UU PPRT, Perlindungan Perempuan Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi
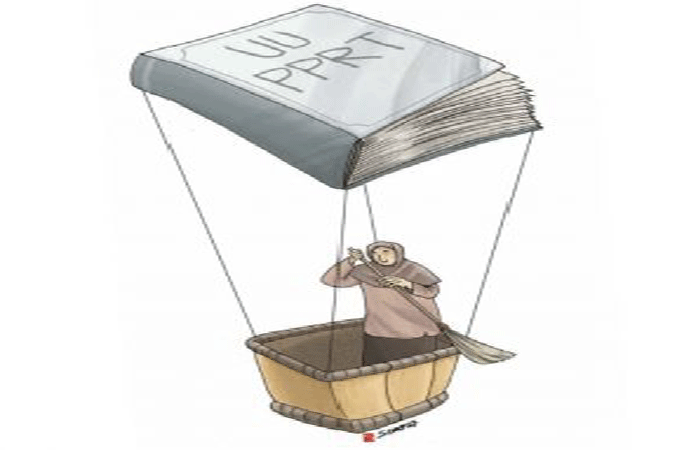
“Dari Mbok Sarinah, saya mendapat pelajaran mencintai orang kecil. Ia orang kecil, tapi jiwanya selalu besar. Sarinah adalah satu nama biasa, tetapi Sarinah yang ini bukanlah wanita biasa. Dia orang yang paling besar pengaruhnya dalam hidupku.” (Sukarno, 1963) SARINAH ialah wajah kemiskinan Indonesia. Untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan, lindungi Sarinah saat bekerja. Perlindungan bisa terwujud melalui gotong royong antara negara, pemberi kerja, dan masyarakat untuk bersama-sana melakukan perbaikan tata kelola pekerja rumah tangga (PRT) sebagaimana termaktub di dalam UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). BPS minggu lalu mengeluarkan data bahwa jumlah penduduk miskin (per September 2022) naik ke angka 9,7% meliputi 26,36 juta orang. Jika kita kaitkan dengan fenomena feminisasi kemiskinan, dapat dipastikan sebagian besar orang miskin di Indonesia tersebut terdiri dari para perempuan. Merekalah Sarinah yang pantang menyerah dan menjadi PRT untuk mengatasi kebutuhan keluarga. Jika diasumsikan bahwa 26,36 juta penduduk miskin itu ialah keluarga PRT, jumlah PRT kita saat ini ada 6 juta orang. Sebagai bagian dari 54% angkatan kerja Indonesia yang tidak berpendidikan dan tidak terampil, menjadi PRT ialah pilihan sekaligus kesempatan bagi para perempuan keluarga miskin. Pasar kerja sektor domestik di dalam maupun di luar negeri sangat terbuka menerima para Sarinah ini untuk bekerja. Sayangnya, bayaran di pasar tenaga kerja RT ini sangat rendah dan kondisi tempat kerjanya disebut dengan 3D, yaitu dangerous (bahaya), dirty (kotor), dan degrading (rendahan). Para Sarinah ini juga tidak mendapat proteksi atas risiko kerja (asuransi) meskipun menjadi PRT taruhannya ialah kecacatan bahkan kematian. Sedihnya pula, semua bansos untuk orang miskin juga tidak mampir kepada mereka sehingga posisi mereka sangat rapuh akibat bencana dan guncangan.
Praktik perbudakan Hampir tidak putus kita membaca nasib PRT yang terlunta-lunta di Hong Kong, Singapura, dan di Arab Saudi. Nasib PRT di dalam negeri pun setali tiga uang. Sejak 2018 Jala PRT setiap hari mendampingi setidaknya dua PRT korban praktik perbudakan, padahal laporan yang masuk ke Jala PRT setidaknya 10/11 orang per hari. Laporan tersebut kebanyakan tidak bisa ditindaklanjuti Jala PRT karena berkaitan dengan permintaan tolong dari keluarga PRT yang kehilangan kontak PRT tersebut. Jenis laporan lainnya ialah laporan dari calon PRT langsung yang menjadi korban penipuan rekrutmen oleh agen melalui media sosial. Para korban yang didampingi Jala PRT sering terlacak karena korban dalam kondisi babak belur, tidak bisa bergerak akibat kekerasan yang berlapis-lapis mulai fisik, mental, ekonomi, pengabaian, hingga seksual. Contoh terbaru ialah Khotimah, Rohimah, dan Riski yang kasusnya bahkan belum naik ke pengadilan karena kejadiannya November tahun lalu. Khotimah selama tiga bulan disiksa delapan orang terdiri dari pasutri, anak, dan empat PRT lainnya.
Diputus komunikasi dari orangtua, tidak dikasih makan, disiksa pukulan, cakaran, disulut rokok, diborgol dan tidur di kandang anjing, ditelanjangi, disodomi dengan buah pisang, dan puncaknya kedua kakinya direndam air mendidih. Gadis berusia 23 tahun itu terancam cacat secara fisik dan mental sehingga terenggut pula masa depan dia untuk menjadi manusia normal dan produktif seperti sebelum menjadi PRT. Khotimah, Rohimah, dan Risky yang ‘ditemukan’ tahun lalu ini hanya mengulang nasib buruk dari PRT sebelumnya. Misalnya Wuryani pada 2018 berhasil melarikan diri dari praktik perbudakan selama sembilan tahun. Nurlela berhasil melarikan diri dari lima tahun perbudakan pada 2015. Atau Toipah yang berhasil melarikan diri dari perbudakan bersama tiga PRT lain setelah disekap dan dihajar selama tujuh bulan. List itu panjang ke belakang. Ratusan yang ditemukan meninggal, termasuk Narsih, PRT usia 14 tahun asal Pasuruan, yang ditemukan tewas pada 12 Februari 2001 setelah disiksa majikan di Surabaya selama empat bulan.
Hari nasional PRT yang diperingati setiap 15 Februari diperuntukkan mengenangkan kematiannya. Dari survei Jala PRT 2019, para PRT ini hampir sebagian besar ialah pencari pendapatan utama bahkan satu-satunya dalam keluarga miskin. Sementara itu, gaji yang diterima para perempuan itu selalu di bawah UMR (40%-50%) per bulan. Gaji yang rendah sering tidak sesuai dengan perjanjian dan sering ditahan untuk memaksa PRT tetap bekerja. Banyaknya penderitaan yang dialami PRT mendorong para aktivis perempuan Rumpun Tjut Nyak Din pada 1998 melakukan pengorganisasian para PRT dan mengampanyekan istilah ‘pekerja’ RT.
Mereka meminta negara untuk turun tangan mengurus nasib PRT yang rawan menjadi korban kekerasan di tempat kerja. Hasil advokasi mereka berbuah. Pada 2010 Gubernur DIY mengeluarkan peraturan gubernur untuk PRT yang pada 2011 disusul dengan lahirnya peraturan Wali Kota Yogyakarta untuk hal yang sama. Dua peraturan itu memungkinkan diadakannya sosialisasi penyadaran kepada para pemberi kerja agar memberikan hak-hak normatif untuk PRT mereka. Pengenalan istilah ‘pekerja’ RT oleh para aktivis perempuan Yogyakarta tersebut menjadi semakin gencar ketika ILO mengeluarkan Konvensi No 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Sayangnya, pemerintah Indonesia menolak meratifikasi konvensi tersebut dan sebagai gantinya mengeluarkan Permenakertrans No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT (PPRT). Para aktivis Yogyakarta tersebut melanjutkan advokasi untuk UU PPRT mulai 2001 melalui Kemenakertrans dan langsung disambut positif mendiang Menteri Jacob Nuwawea. Pada tahun itu muncul kepmen bersama dari Kemenakertrans dan Kementerian PPA tentang hak libur PRT pada Minggu.
Baca Juga: Memahami Substansi BerkesinambunganSayangnya, 19 tahun perjuangan pembebasan para PRT dari kemiskinan tak kunjung diloloskan DPR. Jumlah korban yang 10 Sarinah per hari belum juga menggerakkan pimpinan DPR untuk segera mengagendakan RUU PPRT inisiatif Baleg untuk menjadi inisiatif DPR. Padahal, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan ajakan untuk menyegerakan pengesahan UU PPRT (18/1). Memutus rantai kemiskinan Asas kekeluargaan menuntut kita menempatkan PRT layaknya bagian dari keluarga sehingga berhak diperlakukan sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Perlakuan demikian harus dijamin hukum sehingga well being naik dan dapat berkontribusi naiknya produktivitas PRT. Itulah modal PRT dan keluarga mereka melompat keluar dari lingkaran kemiskinan. Adanya rekognisi (pengakuan) akan profesi pekerja (bukan pembantu/asisten) RT akan memampukan PRT untuk menikmati hak-hak normatif sebagai seorang pekerja. Upah dan kondisi kerja yang layak, jam istirahat yang cukup, libur (sehingga bisa berserikat dan mengembangkan kapasitas personal), beribadah, dan terlindungi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan yang disediakan BPJS. Sebagai orang miskin, mengalami bencana (apa pun bentuknya) ialah sumber kemiskinan. Dengan begitu, tata kelola bansos untuk orang miskin harus bisa diakses PRT karena memang mereka berhak menerimanya. UU domestic workers di Filipina memungkinkan para PRT bisa memperoleh seluruh bansos pemerintah melalui kartu PRT meski mereka tinggal berbeda dari KTP. Semua teori migrasi baik yang klasik (karena faktor eksternal) maupun terbaru (karena keputusan personal) sama-sama menyatakan bahwa ada dampak positif dari migrasi para perempuan untuk menjadi PRT bagi pengurangan kemiskinan keluarga. Sama halnya remiten yang dikirim PRT luar negeri, kiriman uang para PRT dalam negeri ke tempat asal sangat membantu keluarga mereka.
Secara teori, ketimpangan bisa dipersempit dengan menciptakan kesempatan-kesempatan yang sama bagi kelompok miskin. Kesempatan untuk menyekolahkan anak PRT hingga sarjana atau kesempatan PRT menambah ketrampilan saat hari libur bisa mengakhiri jebakan profesi PRT diturunkan dari generasi ke generasi. Kajian terhadap PRT perempuan yang rapuh status sosialnya ini menjadi kajian serius dari aspek hak pekerja khususnya hak sebagai perempuan. Fokus pembahasan feminisme ini pada hal relasi kuasa yang asimetris antara penerima dan pemberi kerja terutama di saat tidak ada legislasi yang melindungi PRT. Pengabaian sistemis dari negara serta eksploitasi oleh agen penyalur dan pemberi kerja menjadi titik sentral untuk membalik keadaan. Yang awalnya eksploitatif untuk kemudian ditransformasi menjadi kolaboratif (gotong royong) melalui UU PPRT, yang tujuannya senapas dengan tujuan program pengentasan rakyat dari kemiskinan. Gotong royong semua pihak untuk pengesahan UU PPRT harus dilanjutkan setelah pengesahan UU PPRT. Pemberi kerja harus memastikan mereka memberi hak normatif pekerja termasuk membayarkan iuran BPJS dan memberi peluang PRT mengembangkan diri; pemerintah untuk memastikan PRT mendapatkan KIS, semua bansos (PKH, Bidik Misi, PIP, LPDP dll); masyarakat–memantau kesejahteraan dan keselamatan PRT di lingkungan mereka, memastikan pula agar PRT menerima program pengentasan rakyat dari kemiskinan negara dan sipil; sedangkan para PRT semangat menjalankan perjanjian kerja dan selalu berijtihad untuk maju.
Kaum Sarinah PRT ialah bagian kaum marhaen dan disebut sebagai kaum mudta’afin (kaum tertindas) di dalam Islam. Pengentasan kaum itu harus melalui revolusi mental untuk membongkar jiwa feodal dan kolonial agar revolusi kebijakan negara menjadi memihak yang lemah, dalam hal ini UU baru untuk PPRT. UU itu dapat diharapkan berkontribusi untuk mengefektifkan UU Pengentasan Rakyat dari Kemiskinan karena keduanya saling menggenapi.Oleh: Eva Sundari Institut Sarinah




Tinggalkan Balasan