Perppu Ciptaker dan Pelecehan MK
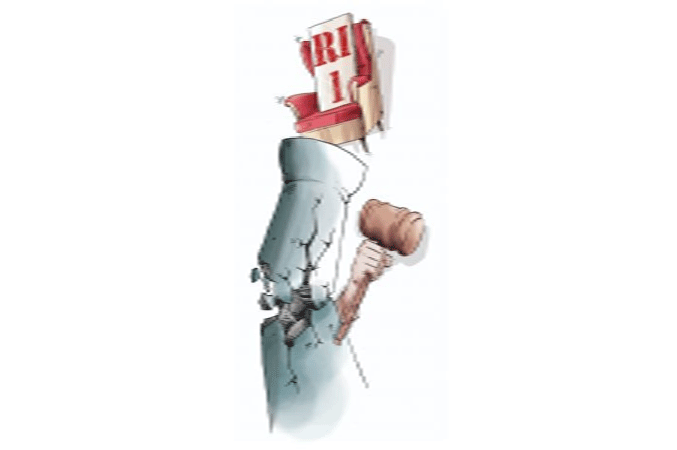
TERBITNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) merupakan persoalan serius ketatanegaraan kita. Perppu Ciptaker nyata-nyata tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Karenanya, secara teori ialah pelanggaran konstitusi sehingga masuk klasifikasi pengkhianatan terhadap negara yang dapat menjadi pintu masuk pemberhentian (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo.
Kegentingan yang dipaksakan
Semua ahli hukum konstitusi paham bahwa syarat konstitusional terbitnya perppu ialah adanya ‘kegentingan yang memaksa’ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Putusan MK No 138/PUU-VII/2009, ketika menguji konstitusionalitas Perppu 4/2009 terkait KPK, memutuskan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud konstitusi ialah pertama, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kedua, kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang karena akan lama.
Apakah itu berarti presiden dapat bebas semaunya menerbitkan perppu karena itu hak subjektif presiden? MK menegaskan tidaklah demikian. Putusan MK 138 membatasi, ‘pembuatan perppu memang di tangan presiden, yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif presiden. Namun, tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa’.
Jadi, meskipun betul hak subjektif presiden, tetaplah harus ada objektivitas yang secara politik diuji dalam forum persetujuan ataupun penolakan perppu di DPR ataupun pengujian konstitusionalitas perppu atau UU-nya di forum MK.
Baca Juga: Kinerja DPR RI kembali ke Rubber Stamp?Di luar forum DPR dan MK, secara teori ketatanegaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat (logic and reasonable). Karena itu, kegentingan tersebut seharusnya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata atau dalam konsep Konstitusi Perancis, Pasal 16 mengatakan kedaruratan itu haruslah serious and immediate threat.
Putusan MK dan ancaman langsung itu sejalan dengan pandangan Profesor Jimly Asshidiqie yang menegaskan bahwa darurat bagi negara memiliki tiga unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu: adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat); kebutuhan yang mengharuskan (reasonable neccesity), dan keterbatasan waktu (limited time) yang mendesak.
Membaca bagian menimbang Perppu 2 Tahun 2022, utamanya huruf d, ‘bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional’. Maka itu, bukan termasuk kategori ancaman yang betul-betul serius dan nyata yang memerlukan presidential constitutional emergency power yang merupakan arti pentingnya perppu.
Kalau didalilkan perang Rusia-Ukraina, ekonomi pascapandemi covid-19, dan potensi resesi 2023, hal tersebut telah lama terjadi, termasuk 13 bulan sejak Putusan MK soal ciptaker pada 3 November 2021. Selama lebih dari setahun itu, mengapa tidak dilakukan langkah-langkah serius melaksanakan putusan MK. Karena itu, Wamenkum dan HAM yang berargumen sembilan bulan waktu yang tersisa tidak cukup sebelum batas waktu dua tahun melaksanakan putusan MK terkait UU Ciptaker tidak boleh dijadikan alasan penerbitan perppu. Karena itu, penerbitan Perppu Ciptaker senyatanya ialah bentuk lari dari tanggung jawab karena tidak mampu dan tidak mau melaksanakan putusan MK tersebut.
Meskipun senyatanya ialah presiden dan DPR sendiri yang menyebabkan tidak cukupnya waktu tersebut, apalagi jika harus memenuhi partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) sebagaimana disyaratkan oleh putusan MK dengan UU yang tebalnya lebih dari 1000 halaman menggunakan metode omnibus law, jalan pintas yang tersisa memang hanya perppu dengan risiko yang sedari awal disadari, yaitu menabrak putusan MK dan menabrak konstitusi bernegara.
Bukan hanya menabrak putusan MK dan UUD, penerbitan Perppu Ciptaker yang merupakan perubahan UU Ciptaker tentunya masih mengadopsi metode omnibus dan karenanya menabrak ketentuan Pasal 42A UU 13 Tahun 2022 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur ‘penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan’.
Dokumen perencanaan tersebut merujuk kepada program legislasi nasional. Sementara itu, penerbitan perppu tentu saja karateristiknya ialah tanpa perencanaan karena sifatnya yang genting dan memaksa. Karena itu, penggunaan metode omnibus law seharusnya tidak memungkinkan untuk penerbitan perppu sebagaimana dilakukan dalam Perppu Ciptaker.
Dengan berbagai persoalan itu, pertanyaan mendasar yang hadir ialah apakah Perppu Ciptaker menjawab kegentingan yang memaksa ataukah kegentingan yang sengaja dipaksakan?
Pelecehan Mahkamah Konstitusi
Menjadi lebih problematik karena Perppu Ciptaker dimaksudkan pula untuk menggugurkan Putusan MK Nomor 109/PUU-XVIII/2020 tentang UU Ciptaker. Putusan MK Ciptaker secara uji formal menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat karena proses pembuatannya problematic, termasuk soal tidak adanya landasan metode omnibus law, perubahan norma hukum UU Ciptaker sebelum diundangkan, dan yang tidak kalah penting ialah tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Putusan MK jelas mengarahkan pembuatan undang-undang, bukan perppu. Kalau akan diubah dengan perppu, harus ada dasar kegentingan yang memaksa yang sangat tidak terbantahkan, bukan hanya perkiraan ataupun dugaan. Tanpa kegentingan yang tidak terbantahkan, Perppu Ciptaker akan menjadi pelanggaran serius atas Putusan MK Ciptaker. Meminjam konsep adanya pelecehan parlemen (contempt of parliament), tidak menghormati putusan MK ialah pelecehan terhadap Mahkamah, alias contempt of constitutional court.
Saya sendiri berpendapat bahwa bukan berarti presiden tidak dapat menerbitkan perppu untuk melaksanakan putusan MK. Bila memang ada kegentingan yang serius dan nyata serta untuk kepentingan penyelamatan bangsa, perppu untuk menghormati putusan MK dapat saja dikeluarkan. Misalnya, Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 memberikan waktu tiga tahun bagi presiden dan DPR untuk membuat undang-undang tersendiri terkait pengadilan tindak pidana korupsi. Ketika batas waktu 9 Desember 2009 nyaris terlampaui, opsi penerbitan perppu sempat dimunculkan. Tanpa selesainya undang-undang, pengadilan tipikor akan kehilangan dasar hukumnya, tidak ada undang-undang lain yang bisa menjadi dasar eksistensi pengadilan korupsi. Perppu pengadilan tipikor karenanya diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum serta menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi.
Tidak demikian halnya dengan Perppu Ciptaker. Tanpa diterbitkan perppu atau bahkan UU Ciptaker sekalipun, masih ada banyak undang-undang yang mengatur materi muatan cipta kerja. Yang terjadi bukanlah kekosongan hukum karena sebelumnya masih ada aturan norma di tiap-tiap undang-undang yang diubah oleh UU Ciptaker. Yang terjadi hanyalah perubahan paradigma di bidang ciptaker yang diklaim lebih ramah investasi. Satu klaim yang selalu bisa diperdebatkan ketika dihadapkan dengan kepentingan publik yang lebih luas dan kelestarian lingkungan. Jadi, masalahnya bukanlah putusan MK yang digugurkan dengan perppu, tetapi perppu yang diterbitkan bukanlah pelaksanaan, tetapi justru tidak melaksanakan putusan MK itu sendiri.
Pemakzulan presiden
Tidak menghormati putusan MK itulah akibat yang paling problematik dari terbitnya Perppu Ciptaker. Bagaimana tidak? Dengan menerbitkan perppu, yang tidak melaksanakan putusan MK, presiden telah memberikan contoh buruk bahwa putusan MK dapat tidak dihormati. Jika dibiarkan, ke depan ini bisa menjadi preseden buruk. Dengan menggenting-gentingkan situasi negara, tanpa maksud penyelamatan bangsa, seorang presiden bisa saja menerbitkan perppu yang menggugurkan putusan MK.
Lebih berbahaya lagi, tidak melaksanakan putusan MK, berarti melanggar konstitusi karena MK adalah constitutional organ yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945. Pelanggaran konstitusi ialah salah satu definisi ‘pengkhianatan terhadap negara’ yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (impeachment). Pasal 169 huruf d UU Pemilu, pada bagian penjelasannya mengatur bahwa tidak pernah ‘mengkhianati negara’ ialah termasuk tidak pernah ‘melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.
Dengan demikian, konstruksi hukumnya: menerbitkan Perppu Ciptaker ialah tidak melaksanakan putusan MK yang merupakan pelanggaran konstitusi, melanggar sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945 dengan lafaz, “…memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.” Pelanggaran konstitusi dan sumpah jabatan ialah pengkhianatan terhadap negara yang masuk kategori impeachment article sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7A UUD 1945.
Kenapa saya memasukkannya ke dalam ketegori ‘pengkhianatan terhadap negara’ dan bukan ‘perbuatan tercela’. Itu karena penjelasan Pasal 169 huruf j UU Permilu mengatur misdemeanour lebih ke arah perbuatan asusila, yaitu ‘melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina’. Meskipun dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi ‘pengkhianatan terhadap negara’, tentu kita paham bahwa impeachment merupakan perpaduan proses politik dan hukum di DPR, MK, dan MPR. Maka itu, realitas politik di ketiga lembaga negara itu, bahkan di MK sekalipun yang semestinya lembaga hukum, tetap memengaruhi arah pemakzulan, alias pemecatan presiden.
Di DPR dengan koalisi pemerintahan yang masih mayoritas mutlak tanpa ada perubahan komposisi koalisi-oposisi, meskipun dengan bergesernya posisi Partai NasDem yang dianggap tidak lagi solid di dalam pemerintahan, tetap saja proses pemakzulan Presiden Jokowi memang tidak mudah dilakukan, bahkan dimulai sekalipun. Itu sebabnya Presiden percaya diri menerbitkan Perppu Ciptaker yang berpotensi melanggar konstitusi sekalipun karena meyakini alih-alih dianggap melanggar UUD 1945 ataupun mengkhianati negara Presiden meyakini Perppu Ciptaker akan disetujui DPR menjadi undang-undang.
Kalaupun, misalnya, anggaplah DPR tidak menyetujui Perppu Ciptaker dan memulai proses pemakzulan, proses di MK pun saya prediksi akan berbeda jika dibandingkan dengan pengujian UU Ciptaker yang memutuskan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).
Dalam putusan UU Ciptaker, lima hakim konstitusi, termasuk Profesor Aswanto, berbanding empat hakim yang lain, berani membatalkan UU Ciptaker. Sekarang dengan telah dipecatnya Hakim Aswanto, jangankan untuk MK menyetujui proses pemakzulan presiden, bahkan membatalkan Perppu Ciptaker ataupun UU yang mengesahkannya saya ragu MK akan berani dan independen. Sebagaimana KPK yang telah dilumpuhkan, MK pun sayangnya telah juga dikerdilkan.
Dengan demikian, saya memprediksi tanpa ada perubahan koalisi politik signifikan di DPR dan tanpa MK kembali merebut independensinya, Perppu Ciptaker akan segera menjadi undang-undang di forum DPR dan dikuatkan konstitusionalitasnya oleh MK. Hal demikian bukan berarti karena penerbitan Perppu Ciptaker itu benar dan konstitusional, tetapi lebih karena dunia politik dan hukum kita memang sedang sakit parah, alias makin jauh dari prinsip negara hukum yang telah diamanatkan UUD 1945.Oleh: Denny Indrayana Guru Besar Hukum Tata Negara Senior Partner Integrity Law Firm Registered Lawyer di Indonesia & Australia.(*)




Tinggalkan Balasan