Menyelisik Pendidikan Kedokteran Kita

SEJARAH telah menuliskan momentum Kebangkitan Nasional sebagai tonggak yang memisahkan antara zaman lama dan zaman baru. Tonggak ini telah melahirkan tidak saja manusia-manusia modern, tetapi juga semangat perjuangan di kalangan anak bangsa. Kepeloporannya lahir dari kaum dokter dan pelajar kedokteran Hindia Belanda kala itu. Komitmen terhadap ilmu kedokteran telah mengilhami mereka untuk membayangkan sebuah negara baru yang merdeka dan bangsa yang sehat. Dan, kini, Indonesia tengah menjelang 77 tahun kemerdekaannya. Namun, menyertai kenyataan itu, bagaimanakah kiranya dunia pendidikan kedokteran kita saat ini? Adakah ia masih memelopori cita-cita kesejahteraan bersama? Masihkah ia memberi inspirasi tentang bagaimana membangun sebuah bangsa yang sehat?
Persoalan pendidikan kedokteran kita Pandemi covid-19 memberi pelajaran betapa pentingnya sistem kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sayangnya, persoalan ini tidak diperlakukan sebagai isu strategis dan vital. Isu kesehatan tidak mendapatkan porsi dan skema pendanaan yang memadai oleh negara. Padahal, pertumbuhan dan transformasi persoalan kesehatan tidak lagi bersifat lokal dan nasional. Ia telah menjadi isu global dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sektor kesehatan sebagai bagian dari percaturan antarnegara. Tolok ukur awal untuk melihat kepedulian negara pada persolan kesehatan ialah ketersediaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan (terutama dokter) menjadi sentral dalam isu kesehatan masyarakat. Menurut World Bank (2010-2017), rasio jumlah dokter di Indonesia hanya 0,4 per 1.000 penduduk atau 4 orang dokter per 10.000 penduduk. Jumlah ini menjadi yang terendah kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Adapun menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), rasio dokter umum di Indonesia 1 banding 1.400 penduduk. Kedua data ini menunjukkan rasio dokter di Indonesia masih di bawah standar WHO, yakni 1 banding 1.000 penduduk. Persoalan menjadi lebih rumit lagi karena tidak meratanya persebaran dokter.
Dari 9.731 puskesmas yang ada, 5%-nya tidak memiliki dokter sama sekali. Sementara 9% puskesmas lain memiliki dokter, tapi tempat tinggal dokternya begitu jauh. Artinya, selalu akan ada kendala dan persoalan jika dibutuhkan penanganan secara cepat dan mendesak. Walhasil, distribusi tenaga dokter ke daerah terpencil, terluar, dan tertinggal menjadi soal lain yang harus segera dijawab. Ini untuk memastikan hadirnya negara dalam pelayanan paling primer dalam hajat hidup rakyatnya: kesehatan. Muara dari persoalan minimnya jumlah dokter dan distribusinya terletak pada proses pendidikan kedokteran (umum dan gigi). Besarnya kebutuhan jumlah dokter ini membuat keran pendidikan kedokteran dibuka selebar-lebarnya. Saat ini, setidaknya ada 72 institusi pendidikan kedokteran dan 26 institusi pendidikan kedokteran gigi milik pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran di Indonesia (PDPT, 2012). Sayangnya, jumlah ini belum mampu menjawab kebutuhan dokter kita. Bahkan muncul persoalan baru terkait kualitas dokter yang diluluskan. Persoalan kualitas ini kemudian dijawab dengan dilakukannya moratorium bagi pembukaan institusi pendidikan kedokteran pada 2016. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah ialah menerapkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia pada 2007, yang diperbarui setiap lima tahun sekali, diikuti dengan Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Masalahnya, ujian ini semakin menjadi cekungan yang menghambat jumlah dokter untuk dapat berpraktik. Dari 7.000-7.500 dokter yang lulus tiap tahun, rata-rata ada 30%-35% tidak lulus ujian kompetensi.
Berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, ada sekitar 38.796 mahasiswa kedokteran yang belum lulus UKMPPD sejak 2014 hingga 2018. Ujian kompetensi ini, menurut Prof Nizam dari Dirjen Dikti Kemendikbudristek dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, menjadi kontrol kualitas atas kelolosan dan kompetensi calon dokter. Namun, ini mengakibatkan adanya ketercekikan (bottleneck) di hilir sistem pendidikan kedokteran Indonesia. Ketercekikan ini bukan karena kapasitas hilir yang tidak mampu memenuhi kuantitas jumlah dokter, tetapi ada sistem yang membuat aliran input hingga output tidak optimal. Artinya, ada ketidakmampuan mengelola jumlah potensial dengan alokasi dan distribusi tenaga kedokteran. Seharusnya, setiap kemajuan dalam pengetahuan sampai batas tertentu merupakan penyederhanaan. Dengan demikian, jikapun ada kontrol kualitas yang dibutuhkan maka bukan dengan memperpanjang atau memperumit proses yang sudah ada, melainkan dengan melakukan modifikasi ide-ide yang lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Misalnya, dengan menjadikan banyak rumah sakit pendidikan demi mengejar ketimpangan jumlah dokter spesialis dan subspesialis. Skema semacam ini terjadi di luar negeri secara masif. Ilmu menjadi berkembang karena peserta didik terlibat secara langsung dengan masalah yang konkret dan aktual. Skema semacam ini juga akan menerabas corak kampus yang cenderung birokratik dan mahal. Sebaliknya, skema UKMPPD cenderung bersifat oligarkis dan aristokratis karena dilakukan di luar dan terlepas dari lembaga pendidikan di mana calon dokter berada. Bukankah seharusnya evaluasi dan kontrol kualitas mahasiswa kedokteran ada di institusi mereka belajar masing-masing? Jika meragukan institusinya, buat apa dibuka lebar-lebar izin membuka pendidikan kedokteran kalau demikian? Kenyataan ini belum ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan kedokteran sebagai eksesnya. Selain lebih komersial, pendidikan kedokteran juga semakin eksklusif. Akibatnya, upaya mendekatkan dunia kedokteran dengan kehidupan sosial menjadi semakin muskil. Dengan biaya kuliah Rp300 juta-Rp750 juta, seorang mahasiswa kedokteran tidak akan punya kesenggangan waktu untuk bersinggungan dengan isu-isu sosial-humaniora.
Bukan sekadar memberi pil Biaya pendidikan kedokteran di Indonesia tergolong sangat mahal jika dilihat dengan pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang sebesar Rp62,2 juta per tahun. Angka ini juga menggambarkan betapa terbatasnya akses penduduk golongan menengah ke bawah dalam pendidikan kedokteran. Kenyataan ini semakin mempersempit proses pemerataan dokter dalam berbagai lapis golongan masyarakat di Indonesia. Kreasi dalam mewujudkan keberpihakan, selain dengan memangkas biaya pendidikan kedokteran, juga dapat dilakukan dengan afirmasi bagi kelompok sosial dan daerah tertentu untuk mendapatkan akses dan manfaatnya. Soal ini seharusnya sudah bisa dipahami dengan mudah karena awal pendidikan kedokteran pada masa Hindia Belanda dulu (STOVIA) juga merupakan sebuah rekayasa untuk mencetak ‘dokter dari kalangan negara jajahan untuk melayani kalangan mereka sendiri’. Bukankah dengan logika yang similar dapat dirumuskan ‘mengapa tidak kita mencetak dokter dari daerah terpencil, terluar, dan tertinggal’ demi terpenuhinya kebutuhan mereka? Dengan logika demikian, harapannya, pendidikan kedokteran tidak saja melahirkan dokter yang berkualitas mumpuni, tetapi juga yang humanis, dekat dengan kebutuhan warga, serta mengutamakan keselamatan pasien dan kesehatan warga masyarakat. Kita tidak bisa membayangkan, dengan beban dan biaya yang tinggi selama proses pendidikan, akan lahir dokter dengan kualitas semacam itu.
Baca Juga: SelebrasiUntuk mendapatkan dokter dan dunia kedokteran yang berkualitas sekaligus humanis, institusi pendidikan kedokteran kita mestinya fokus pada ketersediaan rumah sakit (RS) pendidikan. Saat ini, baru ada 21 RS pendidikan di Indonesia. Sementara kita memerlukan sistem perawatan kesehatan yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi. Tanpa ketersediaan RS pendidikan, kebutuhan dokter untuk berlatih tidak dapat terlayani dengan memadai karena di sanalah eksplorasi, konstruksi baru cara berpikir, hingga pertanyaan atau masalah baru muncul. Di sinilah ilmu kedokteran akan difasilitasi untuk melahirkan terobosan baru dalam dunia kedokteran. Dengan demikian, maka harapan untuk terbangunnya negara dan bangsa yang sehat menjadi lempang untuk digapai. Dengan corak pendidikan yang demikian, peran dokter pun tidak lagi sekadar merekomendasikan pil atau tindakan untuk menyembuhkan pasien, tetapi juga memberi kontribusi dalam membangun sistem ketahanan nasional kita. Oleh: Willy Aditya Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI



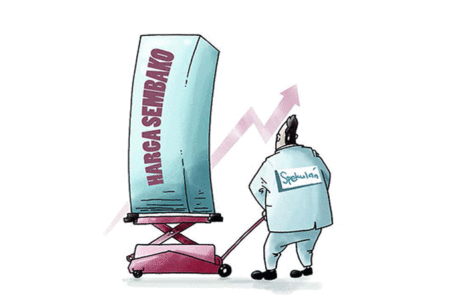








Tinggalkan Balasan