Menjaga Kewarasan Tahun Politik

SEJAK langkah 2023 baru saja ditinggalkan. Di penghujung tahun menjadi saksi bagaimana waktu meleleh ke dalam tinta yang menuliskan banyak kenangan dan sejarah. Modal prudensial yang menuntun bangsa ini menuju gerbang dan menjelajahi tahun 2024. Salah satu agenda besar tahun ini ialah pemilihan presiden pada 14 Februari 2024. Menuju ke etape klimaks tersebut, sulit untuk tidak melihat ‘kaca spion’ sosial-politik sepanjang 2023. Hak-hak rakyat yang disabotase kekuasaan dan kapitalis seperti dalam kasus Rempang, Riau dan kawasan industri pupuk Fakfak, Papua Barat, politik saling sandera kasus korupsi yang melibatkan elite, marwah (pemimpin) Komisi
Pemberantasan Korupsi yang ‘anjlok’, maraknya korupsi di kalangan elite seperti kepala daerah dan menteri, Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdegradasi menjadi alat politik, terciderainya netralitas politik pemilu, kian terkikisnya kebebasan berpendapat, antara lain telah mewarnai portofolio wajah demokrasi kita. Harus diakui, demokrasi kita seakan tersandera oleh patgulipat politik-kekuasaan, pemodal, dan hukum, yang makin mengerikan akhir-akhir ini. Para elite kian memunggungi suara rakyat dalam berbagai beleidnya, dan perilaku demokrasi mereka hanya kepura-puraan. Para pemodal yang tak mau ‘rugi bandar’ terus memainkan jurus-jurus investasi haramnya bagi modal politisi jelang pemilu. Hukum dan keadilan, yang sejatinya melindungi hak-hak kemanusiaan rakyat atas dasar keputusan yang berasal dari ‘tangan Tuhan’, telah bereinkarnasi menjadi institusi yuristokrasi, di mana peran hakim atau pengadil mengalami perluasan eksesif di dalam menghasilkan produk-produk penting politik (Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman, 2021: 162-163), seperti pada kasus ‘Paman Usman’ di MK. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Memperkeruh panggung politik Tanpa disadari, hal tersebut telah memperkeruh panggung politik yang kolaps integritas, etika, kejujuran di hadapan rakyat. Menjungkir-balikkan apa yang dikonstatir Samuel Huntington, bahwasanya panggung politik mestinya menjadi kuil demokrasi tempat diajarkannya prinsip etis, moral, kesetaraan pengorbanan, keadilan dan kemanusiaan (Carsten Anckar, 2022). Kenyataannya, panggung politik tak lebih sebagai adegan ‘sirkus politik’ memuakkan yang mencerminkan pemblokiran masif moralitas publik di atas kerakusan dan perselingkuhan ‘politiktual’ (politik dan intelektual).
‘Narasi satu putaran’ pilpres, yang mengajak rakyat untuk mendukung salah satu pasangan calon, agar suara di pemilu tak hangus, merupakan konkretisasi ‘politiktual’ yang mendepak posisi sakral rakyat dari episentrum mandat demokrasi ke altar pembungkaman elektoral dan demokrasi. Suara rakyat yang suci, didegradasi menjadi suara gemerincing uang di atas meja lotre, dari para pemburu fulus berjubah intelek yang makin mengukuhkan pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi. Bagi JJ Rousseau, yang dijuluki nabi pertama demokrasi, kehendak rakyat merupakan substansi demokrasi yang mencerminkan keinginan ideal dalam proses politik dan pembuatan kebijakan negara (Jacob Wolf, 2023). Karena kandungan kehendak rakyat yang sarat religius itulah, membuat suara rakyat menjadi prinsip penegakan martabat demokrasi. Prinsip yang melampaui nilai-nilai materialisme jangka pendek dan kehendak terbatas kelompok kepentingan. Di aras ini, pemilu dengan seluruh ritual dan suasana kebatinan kontestasi yang menyertainya harus bersendikan pada prinsipal penghargaan terhadap suara rakyat, sebagai bagian dari akuntabilitas terhadap makna dan tujuan substrat demokrasi. Bukan malah menginstrumentalisasi suara rakyat untuk kepentingan sesat mengerdilkan nilai demokrasi sebagai sebatas uang dan kuasa. Kekhawatiran publik terhadap demokrasi yang simbolnya sering ‘dirupiahkan’ sebagai alat-tukar kepentingan oleh elite sosial saat ini terlihat makin jelas, saat menyaksikan bagaimana mereka memperlakukan rakyat dalam berbagai wacana dan argumen politik yang miskin gagasan di balik janji-janji politik yang kian eksplosif sekaligus irasional.
Rakyat kerap diisap keringatnya dalam kerumunan politik sebagai wujud arogansi politik elektabilitas. Tidak lagi menjadi himpunan pemilik suara yang memiliki kehendak dan otoritas politik. Rakyat hendak dijadikan alat mobilisasi suara kepentingan pemilu tanpa pakta integritas sehingga pemilu terancam menjadi arena glorifikasi politik para mantan terpidana, atau mereka yang pernah terseret masalah amoral, korupsi. Dana hibah, bantuan sosial, proyek-proyek pekerjaan kepada kroni, proksi atau klien untuk dibagikan kepada rakyat sebagai pemberian yang mengikat (binding goods). Bukan lagi sebuah wujud tanggung jawab tulus negara dalam mengasihi rakyatnya. Track-record politisi tidak menjadi penting sejauh hasil kompromi dalam pemilu bisa menjamin bagi-bagi jatah kursi kekuasaan. Demokrasi di Barat pernah berada dalam masa yang disebut titik kritis, terutama ketika kekuasaan telah direbut dari tangan rakyat dan berada di tangan segelintir elite politik (Moses I Finley, Democracy Ancient and Modern, 1985).
Titik kritis itu kini sedang menguntit negeri ini. Dikubur Dalam bayang-bayang annus horribilis (tahun mengerikan) yang menguras air mata kekhawatiran, kejengkelan, kesedihan dan nestapa publik atas berbagai peristiwa yang terjadi di 2023, komitmen untuk membangun politik keadaban di 2024 menjadi keniscayaan. Saatnya politik 2024 dibangun dalam nuansa kemelekatan cita-cita, dan harapan rakyat dengan komitmen elite atau pemimpin bangsa. Repetisi keanehan etik dan adab (perilaku ego-sentris, pragmatisme, korupsi, narsisme, hedonisme) yang mengunci rasionalitas elite bangsa dalam menjalankan kekuasaan selama ini saatnya dikubur. Perlu ada resolusi praksis secara berjamaah dari para penyokong mandat publik, untuk bersikap dan berkomitmen melampaui kutub masif pesimisme bahwa elite akan terus terjebak dalam perangkap dis-orientasi seiring mengakumulasinya hasrat ego-sentris dan korupsi (Abramowits, 2023). Sejalan dengannya, elemen sosial, masyarakat kritis dan progresif yang masih sadar, bahwa perubahan yang komprehensif dan menular harus mulai dari level sipil atau ‘grass root’ perlu mengaliansi diri, membangun kekuatan alternatif untuk melawan segala kemurtadan sosial-politik dengan berbagai peran sebagai mahasiswa, relawan, masyarakat pejuang HAM dan kemanusiaan, demokrasi, anti-korupsi, dll.
Baca Juga: Peran Tokoh Hatuhaha dan Krisis Kepemimpinan di MalukuKaum adekuat perubahan tersebut, harus bersinergi untuk menguburkan zona nyaman apatisme sosial-politiknya dengan menghidupkan harapan, bahwa benih hingga aksi perlawanan atas ketidakadilan politik, hukum, sosial, ekonomi dan lain sebagainya di negeri ini, yang ditumbuhkan dari nasionalisme kelas bawah, akan memberikan energi alternatif dalam mendobrak sikap dan kebijakan pemerintah yang kian menyeleweng. Terkhususnya, menjaga kewarasan tahun politik dari cengkeraman tirani elektoralisme atau politik manipulasi dari para elite delinkuen. Oleh: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana. (*)

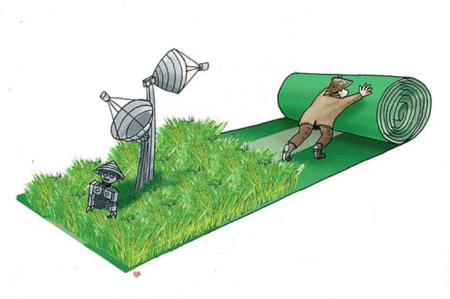


Tinggalkan Balasan