Kedaulatan Rakyat Dikorupsi

MENGAPA demokrasi (kedaulatan rakyat) belum menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah ada yang salah dengan demokrasi kita? Apakah masih ada ruang kesempatan bagi kita untuk menata kembali demokrasi dan membuatnya bekerja seperti tujuan diselenggarakannya?
Kedaulatan rakyat
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan momen yang menulis pesan mendasar tentang dasar pendirian bangsa, yakni dianutnya paham kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Lebih dari itu, kedaulatan rakyat (demokrasi) bukan sembarang demokrasi, tetapi suatu tata yang memuat jiwa kemerdekaan.
Hal ini penting untuk selalu diingat, bahwa demokrasi adalah hikmah kemerdekaan (lihat Mars Pemilu, karya Mochtar Embut). Artinya, bahwa pada dirinya bangsa memiliki tekad kuat untuk membentuk hidup bersama, dalam satu tatanan yang menempatkannya sebagai sumber utama kekuasaan. Negara hanya sah ada karena berasal dari kehendak bangsa. Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 menyebut ‘atas nama bangsa Indonesia’.
Dalam pengertian kekinian, tata yang dimaksud ialah tata di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat secara langsung, atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Pilihan ini merupakan sikap politik bangsa yang ingin menegaskan bahwa bangsa tidak ingin kembali ke dalam tata kolonial yang membuatnya sebagai objek kekuasaan. Kedaulatan rakyat adalah cara bangsa untuk keluar dari sistem lama dan masuk ke sistem baru.
Baca Juga: Ekspor Lobster dan Daya Saing PerikananRakyat dan ruang publik
Tentang kedudukan demokrasi, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, dalam Bali Democracy Forum Ke-15 di Nusa Dua, Badung, Bali, tahun lalu, menyampaikan, ”Demokrasi adalah sekali lagi cara terbaik untuk memerintah dan melayani kepentingan rakyat.” (Kompas.id, 8 Desember 2022)
Pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai kesadaran bahwa demokrasi, pada batas tertentu merupakan perlengkapan rakyat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena kedudukan itulah, dalam demokrasi, tidak mungkin ada pandangan dan tindakan yang mengabaikan rakyat sebagai sumber atau jiwa demokrasi.
Kenyataan kedudukan rakyat dalam tata demokrasi, tentu tidak dengan sendirinya akan melahirkan praktik nyata. Posisi penting rakyat hanya akan punya makna jika dan hanya jika ruang publik terbuka. Keterbukaan yang dimaksud tentu bukan pertama-tama kesempatan bagi kritik, tetapi suatu pengakuan bahwa segala-gala dalam demokrasi adalah tentang ke-publik-an. Artinya, dalam urusan negara, sesungguhnya tidak ada yang ‘privat’. Dan, karena segala sesuatunya bersifat publik, maka keterbukaan menjadi keharusan.
Dalam ke-publik-an itulah keterbukaan menjadi kemutlakan agar yang privat tidak menyelinap dalam ruang publik dan meninggalkan noda.
Pada titik inilah kritik menjadi penting. Kritik bukan sebagai perhiasan yang membuat indeks demokrasi meningkat, tapi suatu cara yang memungkinkan rakyat untuk menjaga agar ruang publik senantiasa bersih dari ke-privat-an. Kritik ibarat tukang sapu, dengan sapu yang bersih, yang setia menyapu ruang publik dari segala ‘kotor’.
Oleh karena itulah, partisipasi rakyat dibuka seluas-luasnya sehingga rakyat dengan penuh cinta menjaga Republik. Dunia akademi diberikan hak dasarnya agar dapat membanjiri ruang publik dengan pandangan kritis dan mencerahkan. Namun, sejarah menyaksikan bahwa kesemuanya itu tidak mudah. Ruang publik yang merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat bukanlah sesuatu yang terberi, melainkan sesuatu yang harus diikhtiarkan.
Perjuangan kemerdekaan, dalam batas-batas tertentu, dapat dikatakan sebagai langkah merebut kembali ruang publik. Langkah tersebut dapat dimaknai sebagai kehendak membentuk ruang publik yang sepenuhnya dalam kendali rakyat (bangsa Indonesia) sehingga apa yang berlangsung di ruang tersebut akan berbuah kebaikan umum.
Korupsi
Apa yang membuat kedaulatan rakyat berjalan secara baik? Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, ketentuan-ketentuan yang menerjemahkan langkah mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kedua, para pelaksana atau individu-individu yang mendapatkan mandat rakyat. Ketiga, rakyat yang memiliki kesadaran dan kecukupan pengetahuan tentang cara kerja negara dan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Ketiganya tentu bukan hal yang saling terpisah, tapi merupakan satu kesatuan. Yang pertama hanya mungkin jika yang kedua baik. Sementara itu, baik yang pertama maupun yang kedua, bergantung pada kesadaran kritis warga. Sebaliknya, yang ketiga bergantung pada kinerja pertama dan kedua. Masing-masing memainkan peran strategis dalam kerangka satu kesatuan susunan.
Masalahnya, apakah kini ketiganya telah membentuk tatanan ideal, atau sebaliknya? Bivitri Susanti dalam ‘Atas Nama Pembangunan’ (Kompas, 11 November 2021) mengatakan, “Hari-hari ini demokrasi seperti cangkang kosong. Ia terlihat bagus dari luar, tetapi di dalamnya tak berisi.” Lukisan Bivitri mirip dengan coretan Buya Syafii, yang menggambar keadaan sebagai, “Jika Republik ini diibaratkan sebuah restoran tertentu, bersih, mentereng, dan gagah di bagian depan, tetapi jorok dan berantakan di bagian dapur. …. Atau, mentereng di luar, remuk di dalam (Kompas, 10 November 2021).
Laporan diskusi panel harian Kompas bersama Asia Research Center Universitas Indonesia pada 17 November 2023 lalu menyebutkan bahwa praktik demokrasi belum dapat diandalkan dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Bahkan dapat dikatakan bahwa ruang demokrasi sesungguhnya tidak dalam kendali rakyat. Bahkan laporan tersebut menyebut, “Pemilihan umum cenderung digunakan untuk menguasai alat kebijakan publik agar bisa mempertahankan akses dan menguasai sumber daya demi kepentingan mereka.” (Kompas.id, ‘Menjaga Harapan Demokrasi yang Realistis’, 20 November 2023).
Institusi dan prosedur demokrasi, secara perlahan tapi pasti, telah dikuasai ‘power’ dan uang. Dalam keadaan yang demikian itu, keputusan tidak lagi mengandalkan kesetiaannya kepada kehendak rakyat, justru sebaliknya. Masalah-masalah hukum yang menimpa pejabat publik menjadi saksi keras bahwa memang ada masalah besar dalam proses rekrutmen politik.
Proses politik tidak lagi bekerja dalam kerangka ke-publik-an, sebaliknya telah menempatkan ruang publik menjadi arena privat. Rakyat yang sejatinya merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sistem demokrasi menjadi tak berdaya akibat kuasa uang (Iqbal Basyari, dalam ‘Demokrasi dan Intervensi Uang’, Kompas.id, 7 Februari 2021).
Kedaulatan rakyat dapat dikatakan telah mengalami tindakan (politik) koruptif, yang ditandai dengan: Satu, makin tampak gerak ke arah abuse of power. Kepercayaan publik telah digunakan untuk kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan publik. Dua, dalam arena publik dipertontonkan siasat privat; atau arena publik telah disalahgunakan untuk kerja-kerja kepentingan privat. Tiga, pengabaian reaksi publik: segala riuh rendah pandangan publik telah diabaikan sedemikian sehingga rasa percaya publik atas institusi demokrasi, termasuk pemilu, merosot drastis.
Hal yang memprihatinkan ialah bahwa segala tindakan politik ditampilkan sebagai pertunjukan ‘teater dangkal demokrasi’, yang mengabaikan nalar dan tidak peduli atas masa depan Republik. Inilah momen korupsi atas kedaulatan rakyat.
Kembali ke rakyat
Apa yang memungkinkan rakyat mendapatkan kembali kedaulatannya? Ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan, terutama oleh kaum terpelajar dan kekuatan tengah. Pertama, mendorong apa yang disebut sebagai ‘refleksi bangsa’, yakni tindakan kolektif bangsa untuk memeriksa perjalanan bangsa dua dekade terakhir. Para cerdik pandai perlu menemukan metode agar aksi kolektif bisa berlangsung, dan pada gilirannya rakyat dapat memberikan penilaian atas keadaan dan merumuskannya secara jelas. Untuk sampai kepada proses tersebut, kelas menengah terpelajar diharapkan bersedia menyumbang perspektif kritis dan kesediaan bersaksi atas keadaan yang tengah berlangsung beserta konsekuensinya bagi masa depan generasi.
Kedua, mendorong keterbukaan politik sebagai agenda bangsa. Reformasi yang semula diharapkan mampu mengakhiri penggunaan arena publik untuk aksi-aksi privat, dalam kenyataan justru sebaliknya. Gerakan reformasi memungkinkan demokrasi. Namun, demokrasi yang berlangsung adalah demokrasi dalam kendali privat. Akibatnya, satu per satu pilar reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, ambruk (Budiman Tanuredjo, Kompas, 25 November 2023). Keterbukaan politik berarti bahwa di arena publik tidak boleh ada tindakan ke-privat-an.
Keterbukaan politik harus juga menerobos ke wilayah yang selama ini mungkin dianggap sebagai wilayah privat, yakni pengelolaan partai dan proses dalam kontestasi politik. Keterbukaan dibutuhkan agar rekrutmen politik menjadi arena publik di setiap sudutnya. Jika hasil pemilu tidak sesuai dengan harapan rakyat, sangat besar kemungkinan telah terjadi pembiaran bekerjanya aksi privat dalam wilayah politik. Hal yang tidak diharapkan ialah terbentuknya ruang-ruang privat dalam arena publik sedemikian sehingga ke-privat-an dapat lolos tanpa diketahui, dan akhirnya menguasai ruang publik.
Ketiga, mendorong partisipasi yang luas dengan jaminan hukum yang kuat. Partisipasi harus dimulai dengan koreksi atas praktik institusi demokrasi. Apa yang diharapkan ialah berlangsungnya proses pemulihan umum yang dipercaya rakyat, yang dengan itu rakyat terpanggil untuk ambil bagian secara aktif dan strategis.
Dengan demikian, rakyat akan memastikan bahwa hanya mereka yang ‘telah selesai dengan dirinya’ yang akan memasuki arena publik, dan dengan itu rakyat akan mengawal seluruh proses sehingga keputusan yang lahir dari tribune publik adalah keputusan yang sejalan dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Hanya dengan keterlibatan seluruh rakyat, kedaulatan akan kembali kepada tangan pemiliknya. Dan, dengan itu, bangsa akan penuh optimistis menyambut masa depannya. Oleh: Sudirman Said Ketua Institut Harkat Negeri.(*)


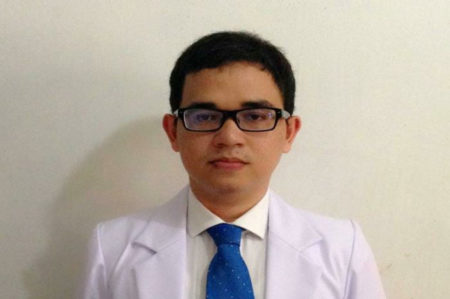

Tinggalkan Balasan