Sekolah untuk Mencegah Yatim Piatu Politik
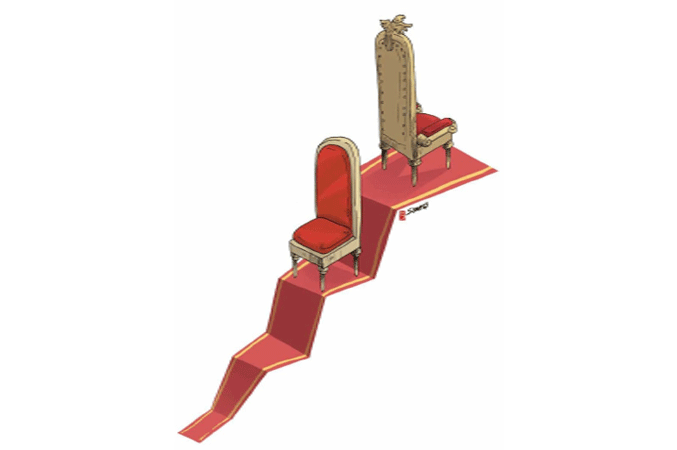
PADA setiap penyelenggaraan pemilihan umum, selalu muncul pertanyaan tentang berapa banyak kader Muhammadiyah yang turut berkontestasi dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada), bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika tidak ada kader, berapa banyak simpatisan atau mereka yang memiliki kedekatan emosional dengan Muhammadiyah yang running dalam pemilu dan pilkada?
Pertanyaan tersebut juga terasa nyaring terdengar di kalangan aktivis Muhammadiyah menjelang perhelatan Pemilu 2024. Sejauh ini, respons pimpinan dan aktivis Muhammadiyah di semua level terhadap pertanyaan tersebut masih dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pembicaraan mengenai peran politik Muhammadiyah juga dilakukan dalam ruang sunyi. Hal itu disebabkan karakter Muhammadiyah yang sejati ialah gerakan kultural.
Muhammadiyah ialah gerakan Islam (Islamic movement) yang konsisten berdakwah amar ma’ruf nahi munkar. Muhammadiyah bukan organisasi politik dan karena itu, tidak seharusnya bermain politik praktis. Politik yang dijalankan Muhammadiyah ialah politik kebangsaan. Komitmen senantiasa bergerak dalam kerangka politik kebangsaan itu sejalan dengan amanah khitah politik Muhammadiyah.
Menerjemahkan khitah politik
Jika kita menyelisik rumusan khitah politik Muhammadiyah, terasa sekali substansinya sangat dinamis. Khitah politik hasil Sidang Tanwir di Ponorogo pada 1969, misalnya, secara ideologis masih menunjukkan pemihakan terhadap Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Namun, Khitah Ponorogo menegaskan pemihakan itu tidak secara organisatoris. Khitah politik hasil Sidang Tanwir Ujung Pandang pada 1971 menegaskan hal sebaliknya. Khitah Ujung Pandang menegaskan netralitas Muhammadiyah terhadap politik praktis. Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
Baca Juga: Kenapa Orangtua Menganiaya Anaknya?Perkembangan penting terjadi pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya pada 1978. Rumusan Khitah Surabaya menegaskan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan. Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak berafiliasi pada partai politik atau organisasi apa pun. Khitah Surabaya ditegaskan kembali dengan Khitah Denpasar 2002. Rumusan khitah hasil Sidang Tanwir di Denpasar menyatakan Muhammadiyah konsisten sebagai gerakan dakwah dan tajdid.
Khitah Denpasar juga menegaskan orientasi gerakan Muhammadiyah ialah sebagai gerakan sosial (civil society) yang memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khitah Denpasar diperkuat kembali dalam Sidang Tanwir yang menyertai Muktamar Ke-45 (Malang, 2005), Muktamar Ke-46 (Yogyakarta, 2010), Muktamar Ke-47 (Makassar, 2015), dan Muktamar Ke-48 (Solo, 2022). Dalam forum permusyawaratan tertinggi itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah mengambil peran dalam politik kebangsaan, tidak berpolitik praktis. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada kader dan warga persyarikatan berkiprah di politik praktis melalui partai-partai politik yang ada.
Sejak kelahirannya hingga berusia ke-111 (18 November 1912-18 November 2023), Muhammadiyah tampak sangat konsisten berkhidmat untuk berjuang melalui jalur kultural. Tidak sekali pun Muhammadiyah tergoda menjadi partai politik. Dalam sejarah mereka interaksi Muhammadiyah dengan dunia politik hanya sebatas menjadi motor penggerak MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia). Melalui tokoh-tokoh seperti KH Mas Mansur, Muhammadiyah turut membidani kelahiran MIAI pada 21 September 1937. Meski bukan partai politik, MIAI saat itu menjadi wadah aspirasi politik umat Islam yang sangat penting.
Muhammadiyah juga pernah tercatat menjadi anggota istimewa Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi merupakan partai politik Islam yang pernah berjaya pada era demokrasi liberal atau demokrasi parlementer (1950-1959). Setelah Partai Masyumi dibubarkan Presiden Sukarno pada 1960, tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat dalam pendirian Parmusi. Bahkan, dua kader utama Muhammadiyan saat itu menjadi pucuk pimpinan Parmusi, yakni Djarnawi Hadikusumo (ketua umum) dan Lukman Harun (sekretaris jenderal).
Pada era reformasi, Muhammadiyah turut membidani kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Sidang Tanwir di Semarang pada 5-7 Juli 1998. Bahkan, Muhammad Amien Rais yang waktu itu sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN. Posisi Amien Rais sebagai nakhoda PAN menjadi daya tarik bagi banyak aktivis Muhammadiyah di level pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting untuk aktif di partai berlambang matahari putih yang bersinar cerah tersebut.
Interaksi Muhammadiyah dan politik sebagaimana terekam dalam sejarah panjang kiprah mereka menunjukkan betapa khitah politik dilaksanakan sesuai dengan konteksnya. Dalam suasana kebijakan multipartai sepanjang era reformasi ini Muhammadiyah semakin meneguhkan jati diri sebagai gerakan kultural, bukan gerakan politik. Hal itu sejalan dengan komitmen Muhammadiyah untuk menerjemahkan khitah politik dalam bentuk politik kebangsaan.
Amal usaha politik
Seakan menyadari bahwa politik praktis sejatinya bukan karakter asli Muhammadiyah, organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu kembali meneguhkan diri untuk berkiprah dalam politik kebangsaan, atau dikenal juga dengan politik adiluhung. Dalam Muktamar Ke-47 di Makassar pada 2-7 Agustus 2015, Muhammadiyah menetapkan konsep Negara Pancasila sebagai dar al-‘ahdi wa al- syahadah.
Konsep negara kebangsaan Muhammadiyah menegaskan, bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara konsensus para pendiri bangsa (dar al-‘ahdi). Dalam konteks itu Pancasila dan NKRI dipahami sudah final. Selanjutnya, yang penting dilakukan seluruh elemen bangsa ialah memberikan pengabdian terbaik bagi negeri tercinta. Pengabdian terbaik itu harus dipersaksikan di antara elemen bangsa (dar al-syahadah).
Meski bukan organisasi politik, aktivis Muhammadiyah tidak boleh abai dengan dinamika politik. Hal itu disebabkan politik dan kekuasaan merupakan instrumen strategis dalam kegiatan dakwah. Terkait dengan pentingnya bidang politik itulah sebagian aktivis mengusulkan Muhammadiyah menjadikan politik sebagai amal usaha baru. Amal usaha politik penting didirikan setelah Muhammadiyah sukses di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Tatkala memasuki abad kedua dorongan agar Muhammadiyah memainkan peran yang lebih menonjol di bidang politik kian menggelora.
Pertanyaannya, dari mana keinginan mewujudkan politik sebagai amal usaha baru itu dimulai? Jawabnya, sebagai langkah awal penting merintis pendirian sekolah politik untuk mendidik kader-kader Muhammadiyah. Kader-kader itu dapat disiapkan untuk mengisi berbagai posisi penting sekaligus sebagai pengawal misi perjuangan Muhammadiyah di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, profesional, dan pekerja sosial (social worker).
Dorongan mewujudkan amal usaha politik sebelumnya pernah diutarakan almarhum Prof Bahtiar Effendy. Di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bahtiar pernah membidangi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Sebagai akademisi andal, Bahtiar dinilai sangat otoritatif berbicara politik. Tatkala Bahtiar wafat, sejumlah aktivis Muhammadiyah menyusun buku Mengenang sang Guru Politik (2020). Buku itu berisi testimoni terhadap kiprah dan karya akademik almarhum di bidang politik.
Dalam berbagai kesempatan, Bahtiar menyatakan bahwa menjadikan politik sebagai amal usaha sangat penting karena sepanjang era reformasi, Muhammadiyah belum banyak menempatkan kader-kader mereka di sejumlah instansi penting negeri ini. Dampaknya, diaspora kader-kader Muhammadiyah di panggung politik dan pemerintahan belum terlaksana dengan baik. Padahal, selalu dikatakan bahwa Muhammadiyah memiliki sumber daya berlimpah. Yang kurang dari kader-kader itu ialah kesediaan, sekaligus keberanian untuk running dalam kontestasi politik.
Yatim piatu politik
Dalam sebuah tulisan di media nasional, Ahmad Syafii Maarif (2019) pernah menyatakan bahwa dalam politik dan kekuasaan Muhammadiyah layaknya yatim piatu. Istilah yatim piatu politik merupakan refleksi mendalam Buya Syafii terhadap nasib Muhammadiyah dalam panggung politik dan kekuasaan. Dalam amatan Buya Syafii, sejauh ini Muhammadiyah belum menikmati buah era reformasi. Padahal, era reformasi tidak dapat dilepaskan dari ketokohan Amien Rais, yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai apresiasi terhadap jasa dan kepeloporan Amien Rais kala itu, publik pun memberi gelar ‘Bapak Reformasi’.
Pertanyaannya, apa yang salah dengan posisi politik Muhammadiyah sepanjang era reformasi sehingga belum sukses mendistribusikan kader-kader terbaik mereka dalam berbagai posisi di lembaga politik dan pemerintahan? Pertanyaan itu selalu dijawab secara normatif dengan menyatakan Muhammadiyah bukan partai politik. Khitah politik Muhammadiyah juga mengamanahkan untuk menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Dengan begitu, tidak boleh ada istilah partai utama dalam pandangan Muhammadiyah.
Sejauh ini, Muhammadiyah juga menunjukkan konsistensi mereka dalam perjuangan melalui jalur kultural. Perjuangan melalui jalur kultural telah memosisikan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society, yang sangat penting di tengah kekosongan peran checks and balances terhadap pemerintah dan partai politik. Dalam posisi itulah, pimpinan Muhammadiyah berpandangan tidak mungkin bermain politik praktis layaknya partai. Peran yang dimainkan Muhammadiyah sebatas politik kebangsaan (high politics).
Sejauh ini, Muhammadiyah telah memainkan politik adiluhung yang menekankan pentingnya politik nilai. Persoalan politik nilai penting di tengah budaya politik yang semakin transaksional. Meski politik kebangsaan untuk mengawal politik nilai penting, sebagian aktivis berharap agar Muhammadiyah sebagai organisasi besar mengambil langkah lebih konkret. Persoalan itu terus menjadi perbincangan serius di kalangan aktivis Muhammadiyah.
Melalui sekolah politik
Muhammadiyah penting mulai menyiapkan kader-kader andal mereka melalui sekolah politik. Keberadaan sekolah politik penting sebagai ikhtiar mewujudkan ‘jihad politik’. Jihad politik merupakan amanah Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makassar pada 2015. Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-48 di Solo pada 2022, persoalan jihad politik kembali digelorakan. Jihad politik penting dilakukan dalam konteks dakwah amar makruf nahi mungkar.
Sebagai bagian dari jihad politik, Muhammadiyah penting mendistribusikan kader mereka di berbagai partai politik. Hal itu berarti Muhammadiyah perlu mendorong kader mereka untuk berdiaspora di sejumlah partai politik. Yang penting, diaspora politik itu dilakukan secara terukur dan berbasis data. Pada konteks itulah tidak boleh ada pernyataan bernada merendahkan, misalnya, “Ia sejatinya kader Muhammadiyah, tapi sayang partainya merah, kuning, oranye, putih, biru, atau hijau.” Dalam konteks Pemilu 2024 juga dikatakan, “Ia kader Muhammadiyah, tapi sayang pilihan calon presidennya berbeda.”
Seyogianya dikatakan bahwa ia merupakan kader Muhammadiyah, apa pun partainya dan siapa pun pilihan calon presidennya. Spirit itu penting, untuk mendorong kader Muhammadiyah berdiaspora. Dengan spirit berdiaspora Muhammadiyah dapat menitipkan aspirasi perjuangan pada kader dan simpatisan yang aktif di sejumlah partai politik. Meminjam istilah Din Syamsuddin dalam Islam dan Politik Era Orde Baru (2001), strategi mendorong kader berdiaspora di sejumlah partai disebut politik alokatif (allocative politics).
Untuk menjalankan politik alokatif, yang harus dilakukan Muhammadiyah ialah mendorong kader-kader terbaik mereka bersiap running dalam proses-proses politik. Mereka harus orang yang memiliki integritas, kompetensi, talenta, dan antusiasme tinggi di bidang politik. Mereka juga harus tahan banting dan tidak mudah kaget berhadapan dengan dinamika politik yang selalu menghadirkan kejutan. Di sinilah, sekolah politik apa pun bentuknya penting untuk melahirkan kader-kader politik dari Muhammadiyah. Oleh: Biyanto Guru Besar UIN Sunan Ampel, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.(*)




Tinggalkan Balasan