Krisis Konstitusi, Reformasi Kembali ke Titik Nol
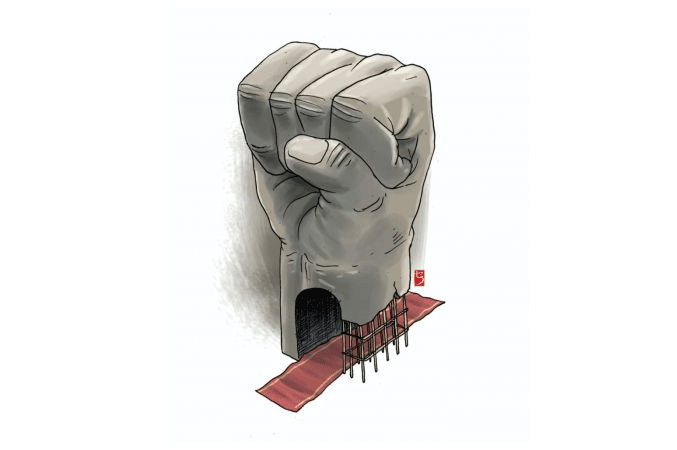
HANYA dalam waktu 25 tahun, amanah reformasi untuk penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kini kembali ke titik nol. Tragisnya, praktik KKN yang semula dibayangkan akan terkikis justru telah kembali menjadi kebiasaan umum. Penyelenggara negara Republik ini seperti tak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya.
Dua puluh lima tahun silam Indonesia mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pengesahan itu dilakukan atas desakan gerakan mahasiswa yang telah berbulan-bulan terus melakukan demonstrasi pada 1998. Mereka menuntut terbitnya ketetapan-ketetapan MPR yang berisi agenda-agenda reformasi, antara lain terkait dengan penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan penghapusan dwifungsi militer. Perjuangan tersebut ketika itu berhasil, tetapi tidak tanpa pengorbanan.
Pengesahan yang berlangsung pada 13 November 1998 tersebut juga bertepatan dengan hari gugurnya sejumlah aktivis mahasiswa yang mendesak adanya tap MPR tersebut. Salah satu mahasiswa yang gugur ialah relawan kemanusiaan yang juga mahasiswa Universitas Katolik Atma Jaya bernama Bernardinus Realino Norma Irmawan.
Nyawa anak muda yang biasa disapa Wawan itu tak tertolong setelah ditembus peluru tajam aparat militer saat membubarkan aksi damai mahasiswa di sekitar Jembatan Semanggi dan area Kampus Unika Atma Jaya yang terletak tak jauh dari Gedung MPR/DPR.
Baca Juga: Sejarah Indonesia Dalam Pandangan GerejaIbunda Wawan, Maria Catharina Sumarsih, saat itu bekerja di salah satu fraksi politik yang ada di DPR. Ia mungkin menyaksikan dari dekat proses pengesahan ketetapan MPR tersebut. Ia juga menyadari betapa penting pengesahan tap MPR tersebut.
Di luar dugaannya, itulah hari saat ia kehilangan putra tercintanya. Barangkali itu hari paling kelam dalam hidupnya.
Namun, ia tak lantas tenggelam dalam duka berkepanjangan. Ia bangkit dan meneruskan suara-suara tuntutan reformasi dari gerakan mahasiswa 1998.
Sumarsih tidak hanya menuntut tanggung jawab negara untuk menegakkan keadilan atas kematian sang buah hati tercintanya, tetapi juga terus menyuarakan pekik mahasiswa tentang semangat anti-KKN.
Tap itu mengamanahkan kepada seluruh penyelenggara negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Setiap penyelenggara negara harus bersikap ‘jujur, adil, terbuka, dan tepercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme’. Tap itu menyebut nama mantan Presiden Soeharto yang sempat diadili atas dugaan KKN.
Maraknya KKN dan penyalahgunaan kekuatan militer sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan juga dijelaskan dalam Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
Tap itu menguraikan dampak buruk praktik KKN, ‘perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar’.
Tiga tahun setelah dimulainya Reformasi 1998, pemberantasan dan pencegahan KKN dianggap belum berhasil. Indonesia kembali menegaskan penolakan KKN melalui Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Tap tersebut menegaskan ‘korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara’.
Dinasti Jokowi
Amanah reformasi itu seharusnya dipatuhi seluruh penyelenggara negara, terutama Presiden Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Sebagai penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan yudikatif, keduanya harus bersih dari praktik KKN, termasuk konflik kepentingan.
Patut disayangkan bahwa peran kepemimpinan keduanya dalam memuluskan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto benar-benar menjadi fenomena politik dinasti yang sarat kolusi dan nepotisme.
Prabowo merupakan eks menantu Presiden Soeharto yang pernah berkuasa selama 32 tahun dan sempat diadili karena praktik KKN. Gibran ialah putra sulung Presiden Joko Widodo yang sedang berkuasa dan kemenakan Ketua MK Anwar Usman.
Putusan MK dilakukan dua hari sebelum hari pendaftaran calon presiden-wakil presiden serta mengundang kritik para ahli hukum konstitusi. Sementara Gibran bisa tiba-tiba menjadi cawapres yang diusulkan Partai Golkar, saudara sekandungnya, Kaesang Pangarep, telah menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam hitungan hari.
Bisnis Gibran dan Kaesang banyak ditopang pengusaha besar (Tirto, 2022), termasuk Sinar Mas Group (Kompas, 2023). Tak jauh berbeda dengan privilese untuk saudara ipar mereka, Bobby Nasution, yang menjabat Wali Kota Medan, Sumatra Utara.
Tanpa adanya relasi keluarga dan pengaruh jabatan dua pemimpin penyelenggara eksekutif dan penyelenggara yudikatif tersebut, mungkinkah Gibran bisa dicalonkan sebagai wakil presiden setelah mendapat jalan pintas menjadi anggota sekaligus orang penting dari salah satu partai besar di Indonesia? Mungkinkah itu terjadi tanpa peran ayahnya yang telah berkuasa sebagai wali kota selama dua periode, sebagai gubernur Ibu Kota, dan sebagai Presiden RI selama sembilan tahun lebih?
Lanjutan kemerosotan demokrasi
Sebagian relawan Jokowi terkejut dengan praktik cawe-cawe Presiden dalam Pemilu 2024. Padahal, kritik terhadap kepresidenan Jokowi yang melemahkan demokrasi sudah berlangsung lama. Fenomena Gibran dan Kaesang hanyalah satu dari sekian banyak bukti dari sikap Presiden Jokowi yang abai terhadap prinsip meritokrasi dan bahkan antidemokrasi.
Keprihatinan ratusan aktivis, akademisi, dan budayawan melalui Maklumat Juanda menegaskan reformasi telah kembali ke titik nol. Fenomena itu merupakan kemerosotan lanjutan demokrasi, dengan enam bukti berikut ini. Pertama, ruang publik untuk kritik dan protes dipersempit. Dikembalikannya pasal-pasal penghinaan penguasa dalam KUHP baru, bertahannya pasal-pasal karet UU ITE, dan maraknya kri-minalisasi menegaskan kebebasan sipil yang suram (ICJR, 2022; Amnesty International, 2022).
Kedua, pemberantasan korupsi melemah akibat revisi UU KPK dan pemecahbelahan masyarakat pendukung KPK berbasis sentimen radikalisme. Polarisasi itu diperkuat kebijakan pluralisme represif (Fealy, 2020) dan hipernasionalistis (Hadiz, 2018), yang mengalihkan perha-tian gerakan sipil dari fenomena oligarki yang terus memenetrasi negara dan partai (Wilson, 2018).
Ketiga, oposisi parlemen menjelma menjadi aliansi kolusif partai-partai politik. Kendala terbesar demokrasi kita ialah partai politik yang korup (Buehler, 2010; Hadiz, 2010), terlalu terpusat pada pemimpin dan dikendalikan segelintir elite dalam relasi patronasi (Carothers, 2006), kurang profesional dan berakar (Tomsa, 2010), dan mengalami deinstitusionalisasi (Johnson Tan, 2012).
Keempat, neodevelopmentalisme Orde Baru kembali terulang dengan kepemimpinan yang melayani pengusaha besar dan mengorbankan derita rakyat kecil (Warburton, 2016). Percepatan investasi proyek strategis nasional, pengesahan UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, dan UU Otsus Papua ialah sebagian con-toh kebijakan yang lebih melayani kepentingan pengusaha besar (KPA, 2022; Pusaka, 2023).
Kelima, kekuasaan dan kekuatan eksekutif ditebalkan seiring dengan melemahnya lembaga-lembaga pengawas dan penyeimbang (check and balances) seperti MK, KPK, dan DPR (Power, 2020). Hal itu semakin diperburuk politik dinasti, kolusi, dan nepotisme.
Keenam, praktik rangkap jabatan menteri sekaligus pebisnis hanya menguatkan terjadinya konflik kepentingan. Penyalahgunaan data intelijen (BRIN, 2023) hingga pasokan senjata BUMN Indonesia untuk junta militer Myanmar berlangsung tanpa pengawasan legislatif (Themis Indonesia, 2023).
Dalam konteks itulah, anak-anak Presiden menikmati privilese jabatan eksekutif, partai politik, dan fasilitas bisnis dari pengusaha besar. Sesuatu yang mustahil diperoleh tanpa status istimewa sebagai anak kepala negara atau presiden yang sedang berkuasa. Oleh: Usman Hamid Eksponen 1998, juru bicara Maklumat Juanda,dan pengurus LHKP PP Muhammadiyah.(*)




Tinggalkan Balasan