Kekerasan Seksual di Kampus

KASUS pelecehan dan tindak kekerasan seksual terus bermunculan dan terjadi di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air. Meskipun terdapat kebijakan dan praktik selama puluhan tahun yang bertujuan menghilangkan kekerasan seksual di kampus-kampus melalui peningkatan respons terhadap kasus kekerasan, kita belum menyaksikan tingkat kekerasan seksual yang lebih rendah, peningkatan keamanan bagi mahasiswa, atau respons yang lebih baik ketika kekerasan seksual terjadi. Jelas bahwa sistem yang ada saat ini tidak berfungsi dengan baik (Brubaker, 2024).
Diperkirakan, sekitar 1 dari 5 perempuan akan mengalami kekerasan seksual selama mereka kuliah. Ini belum termasuk pengalaman ‘ringan’, seperti insiden sentuhan yang tidak diinginkan yang tidak didahului dengan kekerasan, ketidakmampuan, atau paksaan.
Studi yang dilakukan Grocott et al (2023) menemukan sebagian besar kekerasan seksual yang terjadi di kampus (63,0%) melibatkan alkohol (64,4%) dan dilakukan oleh laki-laki (91,7%) yang merupakan teman (27,4%), kenalan (24,7%), atau orang asing (21,9%). Selain itu, sebagian besar responden (78,1%) telah mengungkapkan kekerasan seksual yang mereka alami. Mereka umumnya mengungkapkan hal tersebut kepada teman (68,5%), teman sekamar (27,4%), atau pasangan romantis (21,9%).
Bentuk kekerasan seksual
Studi yang penulis lakukan mengumpulkan data primer yang digali langsung dari para mahasiswa yang pernah menjadi korban tindak pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Lokasi penelitian ditetapkan di tiga kota, yaitu Surabaya, Malang, dan Solo. Ketiga kota itu dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Jumlah responden yang diwawancarai ditetapkan sebanyak 300 mahasiswi, yang notabene pernah menjadi korban tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Baca Juga: Restorasi Narasi KebangsaanStudi yang dilakukan menemukan, di lingkungan kampus, bentuk tindak pelecehan seksual yang pernah dialami korban, sebagian besar ialah pelecehan verbal. Dari 300 responden yang diteliti, sebanyak 36,3% responden mengaku sering mengalami tindak pelecehan verbal. Sebanyak 60,3% mengaku pernah, dan hanya 3,3% mengaku tidak pernah.
Dalam berbagai kasus, sering terjadi mahasiswi terlibat dan dilibatkan dalam candaan yang berbau porno, ucapan-ucapan yang menyerempet pada kurangnya penghargaan akan tubuh perempuan, dan sebagainya. Intinya, walaupun tidak disentuh secara fisik, korban umumnya telah dilecehkan secara verbal.
Selain pelecehan secara verbal, masih banyak bentuk tindak kekerasan seksual yang dialami mahasiswi. Studi ini menemukan, sebanyak 25,3% responden mengaku pernah dikirimi foto atau video porno. Sebanyak 3% bahkan mengaku sering dikirimi foto atau video porno.
Mahasiswa yang memiliki aplikasi VPN atau TOR biasanya dengan mudah mengakses gambar atau video pornografi untuk kemudian bisa di-share ke teman-temannya. Untuk kasus yang sedang populer, tidak sekali-dua kali ada mahasiswa yang kemudian mengunduh dan membagikan kepada teman-temannya, termasuk kepada para mahasiswi. Tanpa sadar bahwa yang mereka lakukan adalah bentuk tindak kekerasan seksual.
Sebanyak 29% responden mengaku pernah diperlihatkan gestur tubuh porno oleh pelaku, dan 3,3% bahkan mengaku sering. Gerakan orang bersenggama atau gerakan tangan seseorang sedang melakukan masturbasi adalah salah satu contoh gestur yang kerap diperlihatkan mahasiswa ke teman perempuannya.
Di lingkungan kampus, mahasiswa sering kali memang terlibat guyonan yang kebablasan. Sebanyak 34% responden mengaku pernah dirangkul pelaku–tanpa persetujuan darinya. Bahkan 5% responden mengaku sering dirangkul begitu saja oleh teman kuliahnya. Banyak responden sebetulnya merasa risi dengan kelakuan pelaku. Akan tetapi, mereka umumnya tidak bisa berbuat apa-apa.
Yang memprihatinkan, studi ini menemukan sebanyak 9,7% responden mengaku pernah diraba bagian intim tubuhnya, seperti payudara, paha, atau bahkan alat kelamin. Meski sentuhan yang dilakukan pelaku masih dilindungi baju yang dikenakan korban, tindakan itu benar-benar membuat korban merasa sangat dilecehkan dan dipermalukan. Ada 0,7% responden mengaku bagian intim mereka sering diraba oleh teman kuliah di kampus.
Sebanyak 12% responden mengaku pernah dicium, dan 1,7% responden bahkan mengaku sering dicium teman kuliah. Studi ini bahkan menemukan sebanyak 9% responden pernah dipaksa berhubungan intim oleh teman kuliah, dan bahkan 1% mengaku sering dipaksa berhubungan intim oleh temannya.
Tidak berani melapor
Di berbagai kampus yang seharusnya steril dari tindak kekeraan seksual, ternyata tindak kekerasan seksual masih sering menjadi momok yang menghantui para mahasiswi dan insan kampus lainnya. Studi yang dilakukan penulis (2024) menemukan, tidak sedikit mahasiswi yang merasa tidak nyaman ketika berkumpul dengan teman laki-laki di kampus. Para mahasiswi sering kali merasa tidak diberi ruang aman ketika di kampus.
Temuan studi yang kami lakukan sama dengan studi yang dilakukan Orchard (2023), para mahasiswi sering kali menghadapi ancaman ketika di kampus, yang menunjukkan bagaimana kerentanan spasial dapat membatasi kebebasan dan pergerakan tubuh mereka (Koskela, 1997; Linder dan Lacey, 2020; Starkweather, 2007; Valentine 1989). Penelitian soal keamanan kampus menggambarkan bahwa perempuan dan pelajar minoritas lainnya mengalami lebih banyak kekerasan dan insiden menakutkan jika dibandingkan dengan pelajar laki-laki (Calogero et al, 2021; Lee dan Wong, 2019; Wooten dan Mitchell, 2015).
Temuan studi ini juga sama dengan penelitian Papp dan McClelland (2021) bahwa perempuan sering kali menjadi sasaran kekerasan dan agresi seksual yang ‘ringan’. Namun, interaksi yang singkat dan ‘ringan’ ini biasanya diabaikan dalam penilaian kuantitatif kekerasan seksual jika dibandingkan dengan bentuk penyerangan yang lebih ‘parah’.
Agresi seksual selama ini masih dianggap sebagai cerminan kegenitan heteroseksual yang umum, di mana laki-laki adalah agen seksual yang berusaha mencapai interaksi seksual melalui cara-cara yang mendesak dan/atau memaksa. Di berbagai kampus di Indonesia, intensitas terjadinya kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi umumnya belum separah kasus yang terjadi di kampus-kampus di negara maju.
Studi sebagaimana dilaporkan menemukan, tidak banyak korban yang memilih dan berani melaporkan peristiwa pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami pada lembaga yang berwenang menangani di kampus. Sebagian korban lebih memilih menceritakan kepada teman dekat saja.
Apa yang terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sama seperti apa yang diteliti Nightingale (2022). Studi Nightingale (2022) menemukan kelompok LGBTQ yang menjadi penyintas kekerasan seksual, ketika melaporkan pelecehan seksual kepada pihak kampus, ternyata justru mengalami pengalaman negatif terhadap proses tersebut.
Dalam banyak kasus, sistem patriarki dan kekuasaan gender memainkan peran penting dalam menstimulasi munculnya berbagai tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Patriarki menciptakan hierarki sosial, yang menempatkan laki-laki–terlebih dosen atau kakak kelas yang senior–di posisi yang lebih tinggi ketimbang perempuan dan memberikan hak-hak istimewa pada laki-laki. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan gender dan memberikan laki-laki lebih banyak kekuasaan atas perempuan. Pada akhirnya, hal ini dapat memperkuat perilaku kekerasan terhadap perempuan, yang dalam hal ini ialah mahasiswi.
Tidak sekali-dua kali terjadi, ketika dosen atau teman kuliah laki-laki memiliki relasi superordinat memanfaatkan posisi dirinya untuk menekan korban, baik dengan cara halus hingga setengah kasar. Mahasiswi yang tersubordinasi sering kali tidak berani melawan dan memilih menyerahkan diri serta kehormatannya karena ulah dosen cabul yang menekan.
Mahasiswi yang menjadi korban tindak kekerasan seksual di kampus biasanya tidak bisa berbuat banyak. Meski merasakan tekanan psikologis yang kuat, mereka umumnya tidak berdaya. Studi yang dilakukan Moore dan Mennicke (2020) menemukan bahwa pelaku pelecehan seksual sering kali meremehkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perlakuan mereka terhadap korban.
Selain itu, para korban menganggap kampus mereka juga kurang adil dalam menanggapi klaim pelanggaran seksual, yang akhirnya membuat korban memilih tidak melaporkan peristiwa yang dialami (Moore dan Mennicke, 2020). Dengan kata lain, insiden pelecehan seksual tidak dilaporkan karena lemahnya sistem yang ada di kampus tersebut (Newlin, 2019).
Studi yang dilakukan Mennicke, Bowling, Gromer, dan Ryan (2021) menemukan ada beberapa alasan kenapa mahasiswi yang menjadi korban tindak kekerasan seksual untuk tidak menggunakan sumber daya formal di kampus, termasuk rasa malu, kekhawatiran akan privasi, takut akan pembalasan, takut tidak dipercaya, dan tidak ingin berurusan dengan prosedur formal. Studi mereka juga menemukan adanya pergeseran rasa takut dalam pengungkapan pengalaman kekerasan seksual kepada sumber daya formal, dari yang semula takut tidak dipercaya, saat ini kekhawatiran yang lebih besar ialah terkait prosedur pelaporan formal yang membebani para korban kekerasan seksual—sebuah bentuk emosi dan tekanan yang berbeda.
Pencegahan dan penanganan
Akar penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi harus diakui sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Menurut Katz (2016), faktor yang memperburuk kekerasan seksual di perguruan tinggi ialah konstruksi sosial tentang maskulinitas. Budaya perguruan tinggi yang menekankan nilai-nilai seperti kejantanan dan kekuasaan dapat mendorong pria untuk berperilaku agresif dan mengabaikan persetujuan dalam hubungan seksual.
Hal ini menyebabkan banyak pria merasa sulit untuk memahami bagaimana perilaku mereka dapat merugikan orang lain. Di samping itu, kelemahan sistem hukum juga menjadi faktor yang memperburuk kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kebanyakan korban kekerasan seksual tidak melapor karena takut tidak dipercaya, atau takut dirugikan. Kehilangan kepercayaan pada sistem hukum menyebabkan korban kekerasan seksual merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain berdiam diri.
Dalam kasus tindak kekerasan seksual, studi ini menemukan tidak sekali-dua kali terjadi sebagian korban ada yang mendapatkan intimidasi atau permintaan dari pihak-pihak tertentu agar tidak makin memperkeruh situasi. Dalam banyak kasus, korban umumnya takut atau tidak diperbolehkan melapor ke aparat penegak hukum karena ada intervensi hingga ancaman dari pihak lain.
Biasanya atas nama kepentingan menjaga reputasi atau nama baik lembaga, maka korban diimbau untuk tidak membawa kasusnya ke ranah hukum, yang dikhawatirkan bisa mencemarkan nama baik perguruan tinggi tempat mereka belajar atau bekerja.
Solusi untuk mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi melibatkan upaya untuk mengubah budaya perguruan tinggi dan memperkuat sistem hukum. Kilmartin (2016) menyarankan bahwa meningkatkan norma-norma pro sosial dapat membantu mengurangi kekerasan seksual. Hal itu mencakup pengembangan pemahaman tentang kesetaraan gender dan menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara mahasiswa untuk melindungi satu sama lain. Bagaimana pendapat Anda? (*)



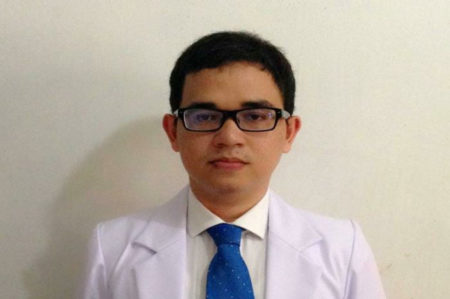








Tinggalkan Balasan