Belajar dari Makkah Halal Forum

MAKKAH Halal Forum (MHF) yang berlangsung di Kota Suci Mekah Al Mukarramah 25-27 Februari yang lalu membuka mata banyak pihak, betapa banyak sekali PR yang belum terselesaikan oleh industri halal global. Mulai ketersediaan produk-produk halal di negara-negara mayoritas muslim yang cukup terbatas, pola perdagangan dunia yang kian berubah, sistem penelusuran halal yang kian kompleks lantaran lintas rantai pasok yang semakin rumit, hingga penggunaan teknologi baru semisal blockchain dan AI dalam ekosistem industri halal.
MHF kali ini merupakan event kedua yang diadakan setelah yang pertama berlangsung tahun lalu. Karena berlangsung berbarengan dengan penyelenggaraan pameran perdagangan dan expo, MHF langsung menyedot banyak peserta. Banyak negara juga memamerkan produk-produk halal yang khas masing-masing.
Banyak pula negara baru yang tampil perdana, seperti dari negara-negara Asia Tengah, tetapi langsung memberikan ‘ancaman’ dalam persaingan industri halal global, seandainya negara-negara yang sudah lama berkiprah seperti Indonesia tidak cepat mengubah pendekatan merebut pasar halal global.
Lokasi penyelenggaraan di Tanah Suci sudah pasti menjadi daya tarik sendiri. Bahkan, MHF sudah bisa menyaingi penyelenggaraan World Halal Summit (WHS), ajang tahunan yang diselenggarakan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, setiap akhir tahun.
KETERGANTUNGAN PADA NEGARA BUKAN MUSLIM MAYORITAS
Baca Juga: Dunia Anak dan Tantangan Lingkungan SekolahJamak diketahui, meski maraknya kemunculan industri halal dalam tiga dekade terakhir, negara-negara mayoritas muslim tidak serta-merta menjadi pemain kunci dalam industri halal global itu sendiri.
Data dari Dinar Index 2020 yang terbit di Dubai menyebutkan negara-negara OKI mengimpor produk pangan halal lebih dari US$200 miliar per tahun dari negara-negara non-OKI. Untuk produk farmasi halal, negara-negara OKI mengimpor US$39 miliar dari negara-negara non-OKI. Negara-negara OKI juga mengimpor lebih dari US$13 miliar kosmetik halal dari negara-negara non-OKI.
Angka-angka itu jelas cukup memberikan gambaran bahwa ada yang kurang tepat dalam pendekatan pembangunan industri halal di setiap negara mayoritas muslim. Jangan-jangan kebangkitan industri halal tidak lebih hanya membuat negara-negara mayoritas muslim sebagai pasar-pasar baru untuk para pemain industri dunia yang sudah mapan.
Indonesia sendiri merupakan pasar yang menggiurkan untuk ketiga sektor halal di atas. Untuk pangan halal, pasar Indonesia menawarkan US$147 miliar dan berada di posisi pertama di Top 5 dunia, di atas Bangladesh, Mesir, Nigeria, dan Pakistan.
Untuk produk farmasi halal, pasar Indonesia berpotensi sebesar US$5,4 miliar dan berada di posisi ke-4 pasaran dunia, di bawah Turki, Arab Saudi, dan AS. Untuk kosmetik halal, pasar Indonesia menawarkan US$4,7 miliar untuk berada di posisi nomor dua dunia, di bawah India, dan berada di atas Bangladesh, Rusia, dan Malaysia. Yang menjadi ironi sebenarnya ialah ketika kebanyakan negara mayoritas muslim itu merupakan penghasil bahan-bahan baku produk halal, tetapi menjadi pasar untuk produk-produk olahan.
Penulis jadi ingat dengan riset yang kami lakukan sebelum ini dan dipublikasikan dalam bentuk buku oleh Kumite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 2021. Dalam kajian ini kami menemukan, lebih dari 10 bahan tambahan makanan (BTM/food additives) yang cukup kritis dalam hal kehalalan dan Indonesia mengimpor dalam jumlah yang luar biasa besar. Mulai gelatin, flavors, oleoresin, seasonings, enzim pangan, pewarna makanan, antioksidan, bahan pengemulsi, agen antifoaming, agen anticaking, humectant, hingga bahan untuk glazing.
Padahal, setelah menilik data BPS, bahan-bahan baku untuk membuat BTM itu sangat banyak tersedia di Indonesia dan ada bukti kita mengekspornya. Artinya, kita mengekspor bahan mentah dan kemudian mengimpor produk olahan.
Gelatin merupakan salah satu BTM yang cukup kontroversial. Ia merupakan super-ingredient yang dipakai di hampir semua produk keseharian, mulai pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Sayangnya, sekitar 90% gelatin yang berada di pasaran dunia diketahui sebagai tidak halal. Sebesar 65% merupakan gelatin yang diturunkan dari tulang dan kulit babi, sedangkan 25% lainnya dari hewan halal tapi penyembelihannya dipertanyakan.
Sayangnya hingga saat ini, Indonesia belum memiliki industri gelatin dalam skala yang lumayan besar. Beberapa produksi gelatin yang ada di tengah masyarakat baru berskala mikro atau industri rumah tangga.
Beberapa waktu lalu, kami bersama tim menyusun sebuah kajian kelayakan (feasibility study) industri gelatin Indonesia. Kulit kambing, kulit sapi, dan sisik ikan sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan. Namun, ketika FS tadi dipresentasikan ke beberapa pihak swasta, tanggapan yang didapat sangat kurang menggalakkan.
Padahal, dalam presentasinya kami sempat memaparkan dua patent yang tim kami punya dengan mengembangkan cangkang kapsul yang menggunakan gelatin dari kulit kambing etawah di Pulau Jawa, dengan kualitas hasil yang sangat mirip dengan cangkang kapsul yang menggunakan gelatin babi.
Bahkan ada sebuah fakta menarik yang lain. Kami pernah diminta pemerintah Malaysia mengevaluasi sebuah perusahaan start-up mereka yang bakal memproduksi gelain halal dari sisik ikan. Setelah diluluskan karena sifat urgensinya, dan dana telah dikucurkan pemerintah, perusahaan start-up itu mulai berproduksi dan bahkan sampai mengekspor gelatin hasil mereka hingga ke Australia.
Anehnya, ketika kami melakukan monitoring, kami diberi tahu bahwa sisik ikan yang menjadi bahan baku perusahaan Malaysia itu berasal dari Semarang. Satu hal yang bisa dipelajari di sini, untuk produk-produk halal strategis kadang kala intervensi pemerintah sangat dibutuhkan.
BANYAK PEMAIN BARU
Satu fenomena menarik yang terlihat selama tiga hari MHF yang lalu ialah maraknya pemain baru di pentas halal global. Beberapa negara yang selama ini seperti ‘tidak peduli’ dengan industri halal kini mulai bangun dan berbenah. Terlihat banyak negara dari Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhtan, dan Kirgizstan mulai menawarkan produk-produk halal mereka, dari wisata ramah muslim hingga produk berbasis daging yang memang sangat terkenal di Asia Tengah.
Penulis sendiri dalam tiga tahun terakhir terlibat dalam sebuah proyek milik Islamic Develoipment Bank (IsDB) yang berpangkalan di Jeddah untuk merevitalisasi industri daging halal di negara Kirgizstan, yang memang sejak zaman Uni Soviet dulu menjadi penyuplai utama daging ke negara-negara di bawah koloni Uni Soviet tersebut.
Tuan rumah Arab Saudi juga sepertinya tidak tinggal diam dalam membangun industri halal mereka. Negara itu merasa sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lain, bahkan jika dibandingkan dengan tetangga mereka, negara-negara Timur Tengah yang lain seperti UEA dan Qatar.
Namun, sejalan dengan Visi 2030 yang digaungkan pemerintah mereka, Arab Saudi langsung gercep dengan dua inisiatif utama. Kedua inisiatif utama itu ialah lahirnya dua lembaga penting terkait halal, Saudi Halal Center dan Saudi Halal Development Corporation (Halal Devco). Kedua lembaga yang memiliki dana pendirian sangat luar biasa besar itu digadang-gadang akan mempercepat tumbuhnya ekosistem halal di Saudi dan memberikan impak ekonomi yang signifikan untuk negara tersebut. Kedua lembaga itu juga menjadi pendukung utama acara MHF 2025.
Arab Saudi kini juga berambisi menjadi pemain utama industri halal global. Bahkan untuk sertifikasi, misalnya, mereka berencana untuk mengakreditasi lembaga-lembaga pemberi sertifikasi halal (certification body) di seluruh dunia. Berbagai peraturan dan mekanisme sedang disusun.
Saudi Halal Devco sejatinya merupakan sebuah entitas public investment fund (PIF) yang didirikan pada 2022 dengan tujuan menjadikan negara Arab Saudi sebagai pusat halal dunia (global hub of halal products). Saudi Halal Devco focus untuk memperkuat industri-industri lokal yang memproduksi pangan, kosmetik, dan obat-obatan halal serta mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Entitas itu juga diharapkan memfasilitasi industri kecil, menengah, dan besar serta membawa produk-produk mereka ke pasaran global.
Peran penguatan ekosistem halal di Arab Saudi juga dipikul Saudi Halal Center. Lembaga yang tadinya berada di bawah Saudi Food and Drug Authority (SFDA) itu kini dijalankan secara professional dengan merekrut para tenaga terampil dari berbagai bidang, dari sains hingga ekonomi.
Saudi Halal Center berfungsi untuk memosisikan Saudi sebagai otoritas legal halal yang terkemuka. SHC juga punya peranan riset dan inovasi yang luar biasa terutama untuk isu-isu terkait autentikasi dan penelusuan (traceability) halal.
Selain para pemain baru, aktor-aktor lama semakin jelas menunjukkan eksistensi mereka. Brasil yang terkenal sebagai penghasil ayam halal terbesar di dunia juga tampil dengan paviliun mewah dan megah. Apalagi selama ini, Timur Tengah juga merupakan pasaran utama ayam-ayam halal dari negara Amerika Selatan itu. Konon selama MHF berlangsung, transaksi yang terjalin di Paviliun Brasil mencapai jutaan dolar AS.
BLOCKCHAIN DAN AI
Tampaknya, isu autentikasi (analisis ketidakhalalan) dan traceability (penelusuran halal) merupakan isu utama dalam industri halal global yang tidak pernah ada surutnya. Bahkan makin ke sini, kedua topik itu juga semakin hangat untuk diperkatakan, termasuk dalam MHF yang baru lalu. Penulis sendiri yang tampil di sesi perdana bahkan diminta secara khusus membahas soal autentikasi dan tracebility itu secara meluas dari perspektif sains dan industri sekaligus. Alhasil, respons dari audiens sangat luar biasa, bahkan dari para pelaku bisnis itu sendiri.
Tidak dimungkiri, semakin canggihnya perkembangan teknologi manufaktur, dan makin kompleksnya rangkaian rantai pasok untuk berbagai produk, autentikasi serta penelusuran halal menjadi sangat penting. Isu-isu yang mengemuka di berbagai negara cukup menarik untuk dite-laah. Misalnya, bagaimana daging yang diproduksi secara halal di Australia, oleh RPH besertifikasi halal, tiba-tiba menjadi tidak halal sesampainya di Malaysia. Kontaminasi terjadi di tengah lautan.
Kasus lain, misalnya, bagaimana cara meyakinkan konsumen muslim akan kehalalan sebuah produk pangan yang diproduksi secara sangat masif selama musim-musim tertentu. Dapur yang digunakan untuk katering selama musim haji, misalnya, yang menyiapkan makanan untuk jutaan jemaah.
Dalam situasi dunia dihadapkan dengan isu ketahanan pangan (food security), isu halal juga mengemuka. Berbagai produk yang lahir untuk mengantisipasi isu kekurangan bahan pangan justru membawa isu baru dari segi kehalalan. Kalau kita lihat senarai produk pangan masa depan (future foods) yang coba ditawarkan berbagai pihak untuk mengatasi isu ketahanan pangan, sebagian besarnya menuntut kita untuk menelaah sisi fatwanya. Mulai serangga, protein ulat, hingga daging yang diproduksi di laboratorium (cultured meat).
Belum lagi, dengan bangkitnya kesadaran berbagai pihak akan animal welfare terhadap produk-produk daging dan unggas, konsu-men tidak hanya akan mempertanyakan kehalalan daging dan unggas semata, tetapi juga akan mempertanyakan bagaimana hewan-hewan ternak tadi diperlakukan selama hidup.
Alhasil, autentikasi dan ketertelusuran halal menjadi kata penting untuk mendukung indus-tri halal itu sendiri. Sayangnya, autentikasi dan teknik penelusuran yang mumpuni hanya bisa diperoleh lewat riset panjang dan serius, yang justru kadang-kadang menjadi titik lemah kebanyakan negara-negara mayoritas muslim. Banyak produk test kit untuk pengecekan halal yang cepat yang ada di pasaran justru berasal dari negara-negara Barat.
Riset-riset yang perlu dilakukan juga mestilah lintas disiplin. Berba-gai bidang ilmu perlu diterapkan dan diaplikasikan dalam konteks halal. Bukan hanya bidang sains seperti kimia, biokimia, dan biologi, tetapi bahkan juga bidang IT.
Ketika banyak yang menyodorkan blockchain dan AI untuk membantu penelusuran halal, kita sepatutnya berharap Indonesia dan negara-negara mayoritas muslim itu yang mengembangkannya. Kita tentu akan terkejut kalau diceritakan bahwa sebuah RPH di Singapura sudah menggunakan teknologi blockchain dan data science, untuk memastikan ayam-ayam halal yang mereka produksi diperlakukan secara baik selama hidup hewan ternak tersebut
MAU KE MANA HALAL INDONESIA?
Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) naik kelas menjadi sebuah lembaga dengan kepalanya setingkat dengan jabatan menteri, tentu kita berharap banyak lembaga sertifikasi halal Indonesia itu bisa berperan lebih luas, untuk mendukung Indonesia menjadi pusat halal dunia. Namun, apakah kehadiran BPJPH saja sudah cukup?
Dengan melihat apa yang berkembang di berbagai dunia, dan melihat peranan BPJPH yang lebih ke arah penjaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat, kami melihat Indonesia butuh lembaga lain yang lebih kuat, berorientasi industri, dan menjadi platform koordinasi berbagai pihak, untuk mendukung penguatan ekosistem halal Indonesia. Mungkin saatnya Indonesia memiliki Indonesian halal development corporation (IHDC), seperti Malaysian Halal Development Corporation (MHDC) di Malaysia, atau Saudi Halal Devco di Arab Saudi.
IHDC seandainya dapat diwujudkan sebagai sebuah lembaga setingkat kementerian atau badan, dapat menjadi think tank pengembangan industri halal Indonesia ke depan, membantu percepatan pemerintah membawa industri halal Indonesia ke peringkat global, mengembangkan ekosistem halal menyeluruh. Bahkan, termasuk dalam hal riset dan inovasi, serta menyediakan talent-talent bidang halal yang dapat diketengahkan ke tingkat global. Model halal Indonesia yang sudah teruji sepatutnya dapat dibawa sebagai model di luar negeri dan itu akan menjadi keuntungan finansial untuk Indonesia. Untuk itu, IHDC seyogianya diisi mereka yang sangat mengerti arah dan percaturan industri halal global.
Sudah saatnya, selain membangun sertifikasi halal yang kuat seperti sekarang ini, Indonesia menjadi negara yang kuat untuk industri halalnya. Seandainya terwujud, IHDC patut diisi para pakar halal Indonesia yang sudah terbukti kredibilitasnya.
Dari pengalaman kami diun-dang ke berbagai kementerian dan lembaga yang ada di Tanah Air, acap kali fungsi koordinasi di antara pelaku halal di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Setiap lembaga dan kementerian bahkan pemda masing-masing melakukan inisiatif sendiri-sendiri, dengan target dan agenda masing-masing. Kesan yang muncul tidak lebih dari permainan solo lembaga atau kementerian tersebut. Ketika itu disebut dalam wacana anggaran, tentu akan banyak penganggaran dapat dihemat seandainya IHDC tadi terwujud..
Fokus halal di Indonesia tentu saja bukan hanya soal sertifikasi halal, melainkan juga bagaimana membangun sektor-sektor industri halal itu sendiri keseluruhan yang pada 2030 diperkirakan sebesar US$10 triliun. (*)
oleh: PenghaIrwandi Jaswir Profesor,
(International Institute for Halal Research and Training, International Islamic University Malaysia dan Universitas Negeri Padang; konsultan, Saudi Halal Center, dan Saudi Halal Development Corporation (Halal Devco)







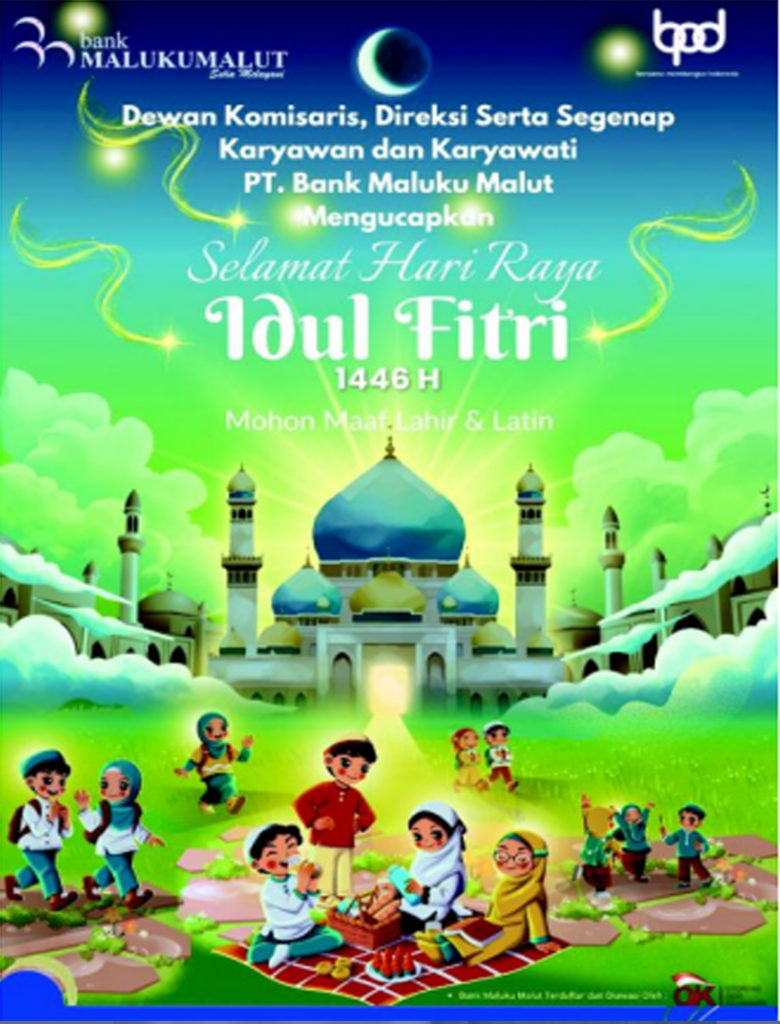

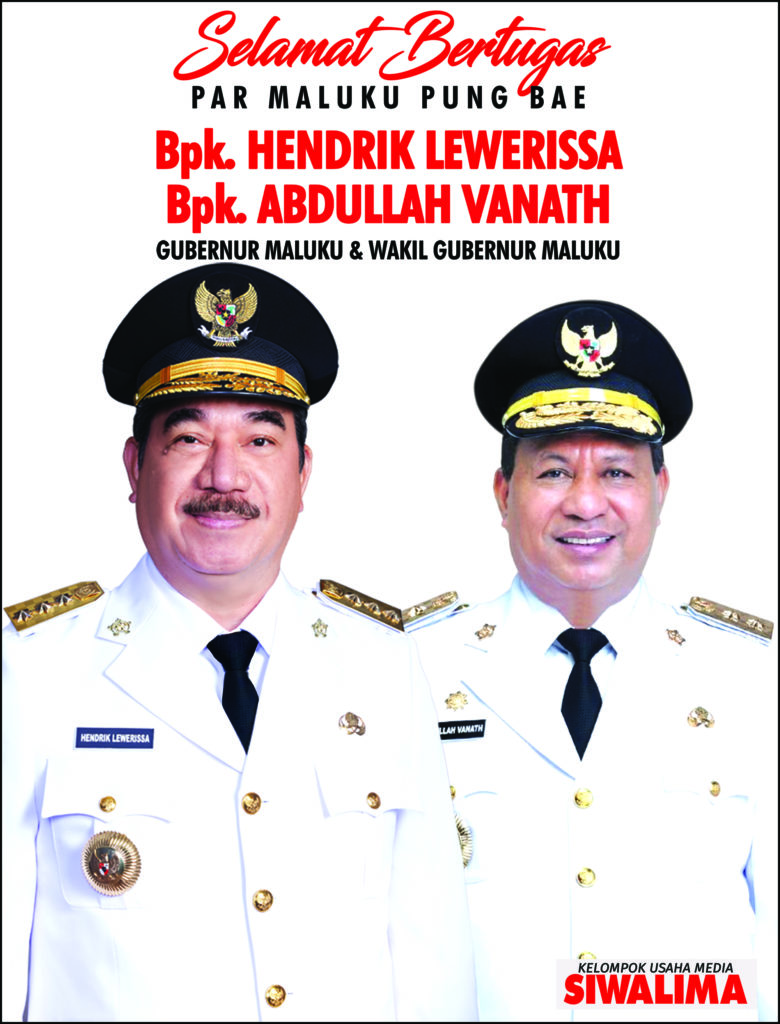


Tinggalkan Balasan