Kearifan Lokal dalam Kosakata Budaya

Bahasa dan budaya merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memengaruhi. Hubungan antara bahasa dan budaya telah diteliti sejak lama oleh para antropolog dan bahasawan. Hubungan antara bahasa dan budaya merupakan dasar munculnya teori relativitas bahasa yang dicetuskan oleh Sapir-Whorf (1920). Benjamin Whorf bertemu dengan gurunya, Edward Sapir, ketika dia menjadi mahasiswa di Universitas Yale di New Haven, Connecticut. Sapir dan para pendahulunya sadar bahwa bahasa dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Sejalan dengan hal tersebut, hipotesis yang dicetuskan Whorf adalah kata-kata dan struktur suatu bahasa memengaruhi cara penuturnya berpikir tentang dunia, cara mereka berperilaku, dan pada akhirnya budaya itu sendiri.
Ide munculnya teori relativitas bahasa saat Whorf bekerja sama dengan Sapir sebagai Insinyur Kimia di Perusahaan Asuransi Hartford yang menyelidiki penyebab kebakaran. Salah satu kasus asuransi kebakaran yang mereka temui adalah kebakaran di sebuah tempat usaha yang terdapat sejumlah drum bensin. Para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sangat berhati-hati ketika dikelilingi tanda-tanda peringatan dilarang merokok di sekitar drum yang berisi bensin. Namun, hal sebaliknya terjadi ketika mereka dekat dengan drum-drum yang bertuliskan kata kosong. Salah satu karyawan perusahaan melemparkan sebatang rokok ke arah drum yang bertuliskan kosong. Hal tersebut menyebabkan kebakaran besar. Whorf kemudian berteori bahwa arti kata kosong menyiratkan kepada pekerja bahwa tidak ada yang perlu diwaspadai. Sayangnya, pada drum kosong tersebut, mungkin masih mengandung asap yang lebih mudah terbakar jika dibandingkan dengan cairan bensin. Karyawan yang membuang puntung rokok pada kasus di atas mungkin memiliki cara pandang tertentu ketika membaca kata kosong. Akibatnya, membuat mereka kurang berhati-hati saat berada di dekat drum kosong. Mungkin juga terdapat karyawan yang lebih berhati-hati saat membaca tulisan kata kosong karena memiliki latar belakang yang berbeda.
Leksikon atau kosakata suatu bahasa merupakan inventarisasi dari hal-hal yang dibicarakan dan dikategorikan oleh suatu budaya agar dapat memahami dunia dan menghadapinya secara efektif. Kosakata budaya di suatu kebudayaan akan menunjukkan corak khas yang berbeda dengan kosakata budaya di kebudayaan lainnya.
Corak budaya yang terkandung dalam kosakata budaya dapat terlihat pada kosakata budaya yang ada di Provinsi Maluku. Contoh kosakata budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat Maluku adalah pela dan gandong. Kata pela dan gandong memiliki makna yang spesial. Kedua kata tersebut berhubungan dengan sistem kekerabatan yang berlaku di Maluku. Bartels (2017) dalam bukunya berjudul Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku (Jilid 1) mendefinisikan pela sebagai ’sistem persekutuan yang disepakati antara dua kampung atau lebih, di antara klan-klan dari kampung yang berbeda dan dalam beberapa kasus’, sedangkan gandong bermakna ’saudara’. Ikatan pela gandong merupakan ikatan persaudaraan yang tetap dijaga hingga kini oleh masyarakat. Ikatan persaudaraan ini tidak mengenal batas wilayah. Selain hubungan sesama marga, adanya kisah sejarah masa lalu yang merekatkan satu marga dengan marga lainnya menjadi latar belakang munculnya hubungan pela gandong.
Kata papeda juga merupakan kata yang umum ditemukan di masyarakat Maluku dan Papua. Meskipun demikian, cara pandang masyarakat Maluku dan Papua mungkin berbeda saat mendengar kata papeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI, kata papeda bermakna ’makanan tradisional Papua berupa bubur sagu, biasanya dicampur dengan ikan dan sayur’. Definisi tersebut merupakan definisi yang umum bagi masyarakat Maluku dan Papua. Namun, bagi sebagian orang di Kabupaten Kepulauan Aru, jenis papeda yang mereka makan berbeda definisinya dengan yang tertera di KBBI. Hal tersebut disebabkan papeda yang biasanya mereka konsumsi bertekstur agak keras dan padat.
Baca Juga: HMI Desak Pemkab dan DPRD Tolak Program TaperaKata seng juga memiliki makna yang berbeda bagi penutur bahasa Melayu Ambon jika dibandingkan dengan makna dalam bahasa Indonesia. Makna kata seng dalam KBBI Edisi VI adalah ’besi tipis yang berlapis timah (supaya tidak mudah berkarat) untuk atap dan sebagainya’. Selanjutnya, dalam Kamus Melayu Ambon (terbitan Kantor Bahasa Provinsi Maluku), kata seng bermakna ’tidak’. Perbedaan makna yang terdapat pada kata seng akan sangat berpengaruh pada sudut pandang penutur bahasa Melayu Ambon dan penutur bahasa Indonesia ketika melihat tulisan kata seng.
Setiap orang akan memaknai sebuah kosakata dengan cara pandangnya masing-masing. Cara pandang tersebut bergantung pada pengalaman, lingkungan, dan budaya yang dimiliki setiap orang. Kosakata budaya di suatu kebudayaan akan menunjukkan corak khas yang berbeda dengan kosakata budaya di kebudayaan lainnya. Koentjaraningrat dalam buku Pengantar Antropologi mengungkapkan bahwa corak khas budaya muncul dari unsur yang kecil, baik berupa unsur fisik dengan bentuk khusus maupun pola khusus dalam suatu sistem sosial atau karena masyarakatnya menganut tema budaya khusus. Corak khas tersebut kemudian membedakan satu budaya dengan budaya lainnya. Oleh karena itu, kekhasan yang muncul pada sebuah kosakata budaya tidak dapat disandingkan superioritasnya dengan kosakata budaya di budaya yang lain. Para pemilik kosakata budaya harus senantiasa merasa bangga dan menggunakan kosakata budayanya sehingga dikenal luas. Oleh: Nita Handayani Hasan, S.S.Widyabasa Ahli Muda, Kantor Bahasa Provinsi Maluku. (*)







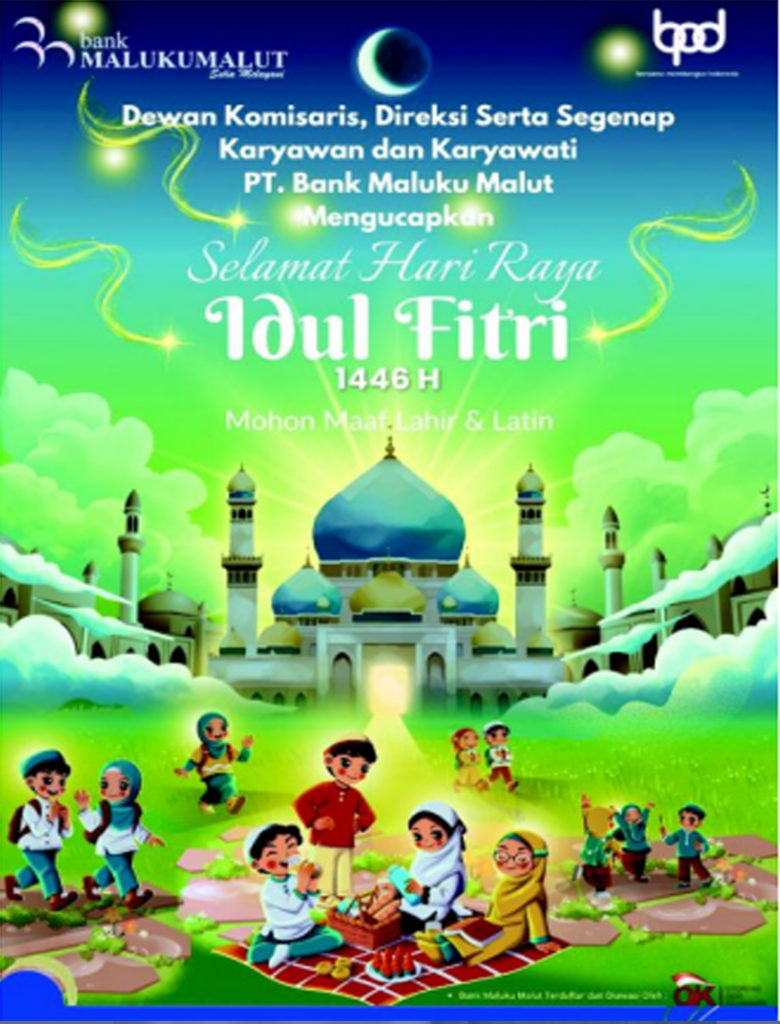

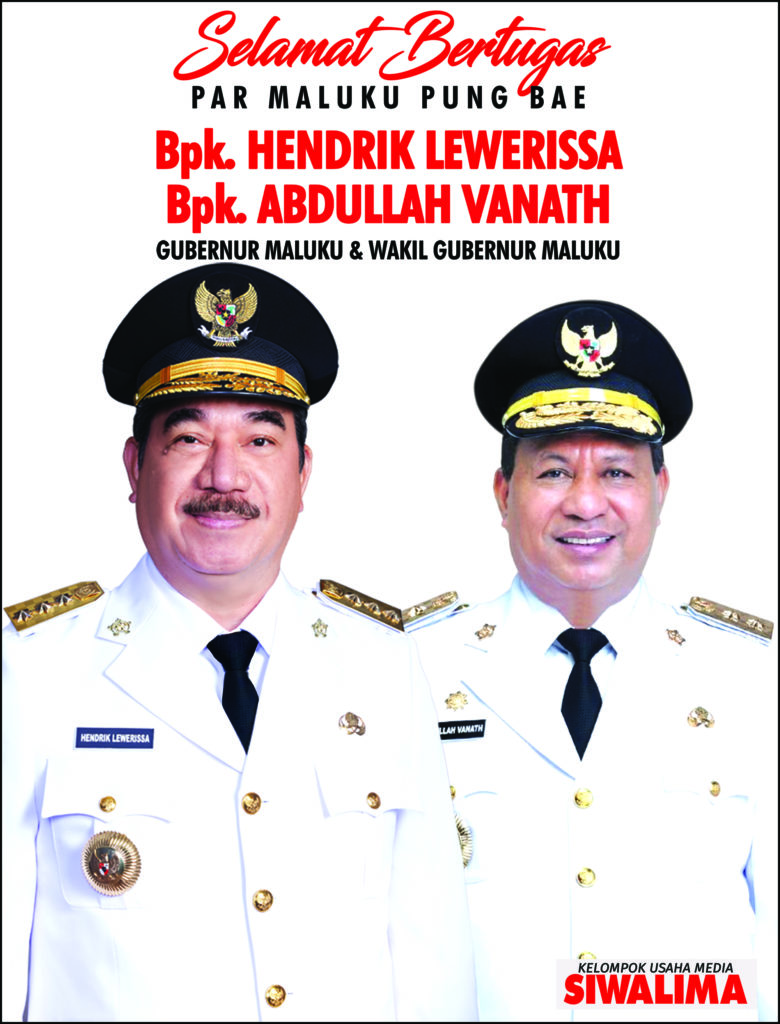


Tinggalkan Balasan