Elegi Ekonomi Kelas Menengah

DATA terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia mengalami turun kelas dalam lima tahun terakhir. Kondisi itu tentu cukup mengkhawatirkan secara ekonomi mengingat kelas menengah ialah salah satu tulang punggung perekonomian nasional, terutama terkait dengan kontribusimnya pada sisi konsumsi dan sisi fiskal. Bagaimanapun, harus pula diakui bahwa penurunan kelas menengah itu ikut memberikan andil pada deflasi yang terjadi selama beberapa bulan belakangan akibat melemahnya permintaan.
Apabila merujuk kepada klasifikasi kelompok sosial berdasarkan garis kemiskinan yang disusun oleh BPS, terdapat lima kategori kelas, yakni kelas miskin (di bawah gari kemiskinan), kelas rentan miskin (1-1,5 kali garis kemiskinan), kelas calon kelas menengah (1,5-3,5 kali garis kemiskinan), kelas menengah (3,5-17 kali garis kemiskinan), dan kelas atas (lebih dari 17 kali garis kemiskinan).
Calon kelas menengah ialah kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya bertambah 8,65 juta hingga menyentuh 137,5 juta orang. Kelompok terbesar kedua ialah kelompok rentan miskin. Selama lima tahun terakhir, jumlah warga rentan miskin bertambah 12,72 juta orang. Per 2024, angkanya mencapai 67,69 juta atau 24,23% dari total populasi.
Nah, pada saat jumlah warga calon kelas menengah dan rentan miskin terus bertambah, penduduk kelas menengah justru kian menyusut. Sepanjang 2019-2024, warga kelas menengah berkurang 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam. Padahal, proporsi kelas menengah diharapkan mencapai sekitar 70% dari total populasi pada 2045.
LPEM FEB UI dalam laporan Indonesia Economic Outlook 2024 for Q3 2024 menyebut bahwa kelas menengah nyatanya memang memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara dengan andil 50,7% dari penerimaan pajak. Sementara itu, calon kelas menengah menyumbang 34,5%.
Baca Juga: Urban Farming dan Ketahanan PanganApabila daya beli kelas menengah menurun, secara fiskal kontribusi pajak akan semakin berkurang dan berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah. Secara ekonomi, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan juga akan menurun.
Namun, jika ditilik dalam kacamata kelas menengah sendiri, penurunan tersebut tampaknya cukup bisa dipahami mengingat semakin beratnya beban hidup yang ditanggung oleh segmen tersebut. Dengan bahasa sederhana, bisa dikatakan bahwa situasi kelas menengah kita memang serbasalah dan serbasulit. Dikatakan serbasalah karena kelas menengah bukanlah segmen masyarakat yang mendapatkan dukungan pemerintah secara fiskal, baik subsidi maupun berbagai macam insentif. Kira-kira kondisi dilematisnya begini, ‘Malu kalau meminta subsidi, tapi semakin menderita jika tak mendapat subsidi’.
Akibatnya, dalam situasi yang serbasulit seperti hari ini, semua pendapatan kelas menengah akan menjadi disposal income, akan dipakai untuk konsumsi, baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk kebutuhan sekunder, tertier, dan gaya hidup. Bahkan, tabungan pun akhirnya harus dipakai untuk menutupi itu semua.
Kondisi itu belakangan dikenal dengan istilah ‘makan tabungan’. Artinya, perbandingan tingkat pendapatan kelas menengah kita dengan tingkat biaya hidup dan kebutuhan semakin hari semakin kurang singkron. Daya beli (purchasing power) menurun karena pertumbuhan pendapatan lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan biaya hidup dan tuntutan kebutuhan.
Namun, di sisi lain, karena masih dianggap berpenghasilan tetap, minimal seukuran UMR atau sedikit di bawahnya, kelas menengah otomatis tidak menjadi segmen yang dianggap kurang layak disubsidi. Bahkan, subsidi BBM pun sering kali dianggap dinikmati oleh kelas menengah, lalu dianggap salah sasaran. Apalagi subsidi langsung seperti BLT dan sejenisnnya.
Lalu dikatakan serbasulit karena kelas menengah dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia melalui budaya konsumsi (konsumerisme) di satu sisi dan menjadi objek pajak (pph) di sisi lain. Karena itu, kelas menengah menjadi objek konsumerisme sekaligus objek pajak yang terus dikejar oleh korporasi dan pemerintah secara bersamaan.
Pendapatan kelas menengah terus diincar untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak pendapatan, pajak barang konsumsi, dan pajak berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh kelas menengah, sekaligus diincar untuk berbelanja agar tingkat konsumsi rumah tangga tetap memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, kelas menengah ibarat sapi peras, baik oleh negara maupun oleh korporasi.
Nah, memburuknya performa ekonomi kelas menengah belakang diiringi dengan deflasi yang berturut-turut dalam beberapa bulan, semestinya menjadi sinyal bagi pemerintah. Jika kelas menengah terus-menerus diperlakukan demikian, prospek pertumbuhan ekonomi akan semakin memburuk karena beban sebagai tulang punggung ekonomi nasional sudah terlalu berat.
Sektor-sektor yang pasarnya bergantung kepada kelas menengah berpotensi terkontraksi dari sektor manufaktur, perdagangan, otomotif, properti, sampai pada sektor perbankan dan pembiayaan. Ujungnya tidak hanya berpotensi mengganggu kinerja sektor-sektor tersebut, tapi juga akan memperburuk prospek investasi di negeri ini. Investor di berbagai sektor yang menarget kelas menengah sebagai konsumennya akan berpikir panjang untuk berinvestasi atau berekspansi di Indonesia.
Di sisi lain, dengan mengecilnya atau hilangnya porsi pendapatan kelas menengah untuk ‘saving’ atau tabungan, karena semua pendapatanya menjadi disposal income, likuiditas perbankan bisa semakin seret untuk membiayai investasi dan pembiayaan sejenisnya di masa depan. Ditambah lagi dengan suku bunga yang masih tinggi. Maka itu, pertumbuhan ekonomi pun akan ikut terganggu dari sisi investasi yang tidak tumbuh sesuai dengan harapan dan target. Jadi, memburuknya performa ekonomi kelas menengah ini harus menjadi perhatian pemerintah, lagi-lagi karena segmen kelas menengah ialah tulang punggung perekonomian nasional.
Beberapa warning mulai dimunculkan para pakar terkait dengan konsekuensi tekanan demi tekanan yang dialami oleh kelas menengah ini. Salah satunya ancaman Chillean paradox. Namun, sebenarnya istilah Chillean paradox ini bukan spesifik untuk kelas menengah. Pun istilah itu tak banyak dipakai di luar sana. Di Indonesia diperkenalkan oleh Chatip Bisri setelah ia membaca buku The Chile Project: The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism karya Sebastian Edwards yang belum lama ini terbit.
Sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan oleh para Chichago Boy di Chile (setara dengan mafia Barkeley di Indonesia) telah membawa Chile menjadi salah satu negara termaju di Amerika latin. Namun, kemudian justru mengalami goncangan dadakan akibat perlawanan masyarakat, terutama kelas menengah pada 2011. Triger-nya cukup sederhana, hanya kenaikan tariftransportasi publik metro.
Penolakan tersebut sebenarnya hanya akibat dari sistem ekonominya yang dijangkiti gejala yang hampir mirip dengan kutukan sumber daya atau resource curse yang mana sebuah negara memiliki SDA berlimpah, tapi pertumbuhannya tidak terlalu siginifikan di satu sisi dan merebaknya ketimpangan yang cukup tinggi di sisi lain. Artinya, kue ekonomi tidak terlalu dinikmati oleh kelas menengah.
Namun, bagi saya, kondisi Chile dan Indonesia tak terlalu sama. Jika ingin dicarikan perbandingan, Brasil jauh lebih mirip dengan Indonesia dengan model decadent developmental state-nya, ketimbang dengan Chillean paradox. Bagi saya, bahaya penuruan kelas menengah itu lebih cenderung kepada kondisi makro ekonomi nasional. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kelas menengah ialah tulang punggung ekonomi, baik dari sisi konsumsi maupun revenue atau pajak di satu sisi maupun dari sisi ketersediaan tenaga kerja tranpil dan produktif.
Nah, jika kehidupan kelas menengah semakin sulit, pertumbuhan ekonomi akan tertekan dari sisi komsumsi maupun investasi. Dua sisi itu, baik konsumsi maupun investasi, ialah kontributor sangat penting terhadap pertumbuhan, setelah itu baru belanja pemerintah dan ekspor impor.
Jadi, bisa dibayangkan jika kelas menengah itu semakin tertekan kehidupan ekonominya, Indonesia bisa mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi akan melambat, banyak sektor yang akan terkontraksi, dan pendapatan negara akan semakin sulit ditingkatkan yang ujungnya akan memaksa pemerintah untuk terus memperbesar porsi utang. Pendeknya, daya tahan ekonomi nasional akan menjadi taruhannya. (Ronny P Sasmita, Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI 25/9/2024)



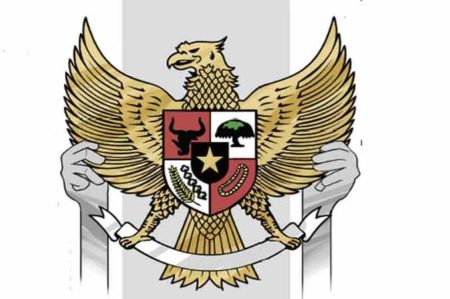








Tinggalkan Balasan