Akar Persoalan KDRT, Bisakah Diatasi

MESKI kita sudah memiliki Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga sejak 2004 (UU No 23 Tahun 2004), angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih tinggi. Pertanyaannya, mengapa tingkat kekerasan di rumah tangga masih sangat tinggi? Akar persoalan apa yang menjadi faktor penentu tingginya KDRT dan mengapa sulit dieliminasi?
Banyak kasus KDRT yang menjadi headline nasional, baik di media cetak maupun elektronik. Bukan hanya orang biasa yang menjadi korban, melainkan juga dialami oleh figur publik sehingga kasusnya menyita perhatian publik. Pada 2023 kita dikejutkan oleh akibat paling ekstrem tindakan KDRT seperti yang dialami oleh seorang ibu muda berusia 24 tahun yang meninggal di tangan suaminya setelah sering mendapat perlakuan kekerasan sampai pada pelaporan ke kepolisian.
Dampak buruk KDRT juga tidak hanya dialami oleh pasangan (istri), tapi juga oleh anak yang juga sering menjadi korban. Kasus paling menyita publik ialah kematian empat orang anak di tangan ayahnya sendiri ketika ibu mereka sedang dirawat di RS akibat mengalami KDRT.
Fenomena yang menyeruak di masyarakat bisa digambarkan seperti fenomena gunung es karena ada banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap. Menurut survei nasional terkait dengan KDRT (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan 12,800 responden perempuan, satu dari empat perempuan (26,1%) usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidup mereka dan 1 dari 11 perempuan (8,7%) pernah mengalami kekerasan serupa dalam setahun terakhir.
Ada empat jenis kekerasan yang ditanyakan dalam survei tersebut, yaitu kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan pembatasan perilaku. Menariknya, dari seluruh jenis kekerasan, yang terbanyak dialami perempuan sepanjang hidup mereka ialah pembatasan perilaku oleh pasangan yang mencapai 30,9%. Pembatasan perilaku berkorelasi dengan adanya potensi perilaku kekerasan lain karena akan selalu menaruh curiga, ingin tahu keberadaan korban, serta membatasi gerak dan membatasi pertemanan serta hubungan dengan keluarga. Kekerasan emosional atau psikis dialami oleh 11,3% perempuan selama hidup mereka dan 4,7% perempuan dalam setahun terakhir. Kekerasan ekonomi dialami oleh 17,9% perempuan sepanjang hidup mereka dan 6,8% perempuan dalam setahun terakhir.
Baca Juga: Merdeka dari Tantangan KesehatanDari mereka yang mengalami kekerasan fisik, frekuensi kejadian kekerasan sebagian besar dilakukan secara berulang (recurring event). Dari jenis kekerasan fisik yang dilakukan, mayoritas (66,9%) ialah kekerasan di tingkat berat atau parah seperti dipukul dengan tangan atau benda yang menyakiti, ditendang, dihajar, diseret, dicekik, dibakar dengan sengaja, serta diancam dengan senjata tajam, senjata api, dan senjata lainnya.
Berbeda dari pandangan umum, yang mana perempuan yang berpenghasilan kemungkinan besar lebih terhindar dari kekerasan karena memiliki posisi tawar yang lebih kuat, data survei menunjukan sebaliknya. Berbeda dari data survei pada 2016, perempuan bekerja saat ini lebih banyak yang mengalami kekerasan daripada perempuan yang tidak bekerja (12,8% jika dibandingkan dengan 9,9%).
Hal itu mengindikasikan perempuan bekerja tidak secara otomatis terhindar dari KDRT, terutama ketika suami atau pasangan mereka memiliki penghasilan atau stasus sosial ekonomi yang lebih rendah. Namun, data laporan pada 2022 yang disampaikan kepada Komnas Perempuan sama dengan data dari survei sebelumnya yang mana mayoritas korban KDRT berstatus sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan tidak bekerja.
Dari sisi kelompok umur, mereka yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidup lebih banyak dari kalangan yang berusia lebih muda (antara 15-24 tahun), sebesar 15,6%, jika dibandingkan dengan generasi yang lebih tua (berusia 25-34 tahun), sebesar 10,7%, dan mereka yang berusia 35-44 tahun, sebesar 11,7%.
Data kekerasan Komnas Perempuan menunjukkan tren yang sama terkait dengan mereka yang berstatus sebagai pelajar yang mengalami kekerasan oleh pasangan menempati urutan terbanyak kedua setelah IRT. Itu menjadi keprihatian bersama karena generasi Z banyak yang menjadi korban kekerasan ketimbang generasi yang lebih tua. Salah satu kerentanan itu bisa jadi karena banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (pasangan) pada masa pacaran.
Ada beberapa alasan dan persoalan mengapa KDRT masih sangat tinggi di tengah masyarakat kita. Jika melihat hasil survei nasional yang dilakukan KPPA dan BPS di atas, faktor utama mengapa terjadi kekerasan ialah faktor ekonomi (30,7%). Namun, ekonomi bukan satu-satunya alasan karena sebanyak 15,6% responden menyebutkan tidak ada alasan yang jelas karena suami atau pasangan cemburu (14,5%), karena mabuk (13,1%), karena masalah pekerjaan (12,3%), saat suami menunjukkan dia lebih berkuasa (9,8%), karena masalah dengan keluarga suami/istri (8,9%), istri tidak patuh (7,1%), saat suami/pasangan menganggur (4,2%), masalah makanan (3,8%), istri menolak berhubungan seks (2,6%), dan istri hamil (0,5%).
Jika mencermati beberapa alasan yang disebutkan di atas, KDRT berakar dari persoalan yang kompleks, tidak hanya ekonomi, tapi juga faktor sosial budaya, pandangan terhadap maskulinitas laki-laki, persoalan ketidakadilan gender, dan akar teologis yang bersumber dari interpretasi terhadap teks keagamaan yang selama ini dipahami dan banyak dipraktikkan di masyarakat.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu akar persoalan utama yang menjadi penyebab KDRT. Sebuah penelitian terkait dengan faktor ekonomi dalam persoalan KDRT menunjukkan bahwa ketika laki-laki (suami) memiliki persoalan ekonomi (ketika tidak memiliki pekerjaan, kesulitan keuangan, dan hidup kekurangan), itu bisa memicu terjadinya perilaku kekerasan oleh laki-laki (suami) pada pasangan (istri) karena adanya tekanan dari masyarakat atau pihak lain sehingga berakibat pada perilaku kekerasan laki-laki (Nilan, Demartoto, Broom, & Germov, 2014).
Lebih jauh, Nilan dkk menjelaskan bahwa kerentanan laki-laki menjadi pelaku kekerasan untuk menunjukkan kelaki-lakian dan kuasa laki-laki terhadap perempuan (istri) sehingga perlakuan kekerasan memberikan kompensasi bagi laki-laki untuk menutupi kekurangan mereka di aspek lain seperti ekonomi.
Selain ekonomi, faktor sosial budaya berpengaruh pada praktik kekerasan terhadap perempuan, di antaranya padangan yang memberikan keunggulan pada laki-laki dan praktik yang tidak berkeadilan gender seperti dalam pembagian kerja rumah tangga (domestic labor division). Istri yang dianggap tidak patuh pada suami dan tidak menjalankan pekerjaan rumah tangga mereka bisa menjadi sasaran perilaku kekerasan seperti tergambar dari alasan adanya KDRT di atas.
Akar persoalan KDRT lain yang jarang menjadi perhatian ialah pandangan terhadap maskulinitas laki-laki yang berpengaruh pada perilaku yang menjunjung tinggi kelaki-lakian (maskulinitas) serta kuatnya akar teologis yang mengakar dalam masyarakat.
Maskulinitas laki-laki
Prianti (2019) dalam The Indentity Politics of Masculinity as a Colonial Legacy menyebutkan maskulinitas laki-laki sebagai bagian dari legasi masa kolonial dan menjadi simbol penolakan dari identitas ‘keperempuanan’ (feminity) yang lebih mengedepankan nilai-nilai keluarga dan komunal jika dibandingkan dengan nilai individual.
Pengaruh besar era kolonial terhadap pembentukan identitas maskulinitas laki-laki dan peran gender tergambar dalam budaya populer yang berkembang saat itu (misalnya dalam majalah Gaya Hidup Laki-Laki).
Tidak bisa dimungkiri jika wacana maskulinitas sebagai identitas laki-laki terus mengakar di masyarakat hingga saat ini. Pembagian kerja dalam rumah tangga menjadi salah satu contoh ketika laki-laki melakukan pengasuhan dan pekerjaan domestik sering dianggap ‘kurang laki-laki’ karena adanya anggapan pekerjaan domestik merupakan pekerjaan perempuan dan kurang patut bagi seorang laki-laki mengurus pekerjaan rumah tangga. Meski keliru, pandangan itu sering dipraktikkan dan dianggap sebagai keniscayaan.
Hayati, Emellin, dan Eriksson (2014), yang melakukan penelitian hubungan antara pandangan maskulinitas, keagamaan, dan perilaku kekerasan laki-laki, menjelaskan bahwa pandangan tradisional terkait dengan maskulinitas berbanding lurus dengan perilaku dominan laki-laki dan perilaku kekerasan.
Akar teologis
Meski mungkin ada yang tidak setuju, akar teologis/keagamaan yang berkembang di masyarakat sering menjadi acuan sebagian orang dan menjadi alasan adanya perlakuan kekerasan. Afirmasi dari responden bahwa alasan KDRT ialah ‘karena istri tidak patuh pada suami’, ‘karena suami ingin menunjukkan kuasa’, dan ‘menolak berhubungan seksual’ berakar dari pandangan teologis. Itu bersumber dari penafsiran terhadap QS Annisa: 34 terkait dengan keunggulan lak-laki terhadap perempuan dan larangan untuk tidak taat (nusysuz) pada suami.
Ayat tersebut dilanjutkan dengan menyebutkan tata cara penyelesaian yang perlu diambil jika istri tidak taat (nusyuz), salah satunya diartikan dengan kebolehan bagi laki-laki (suami) memukul (dharaba sering diartikan sebagai memukul).
Mayoritas ulama tidak mempertanyakan penafsiran itu dan membolehkan upaya pendisiplinan istri secara fisik seperti dengan memukul. Para ulama dan mufasir lebih membahas prosedur dan batasan apa yang dibolehkan dalam pemukulan agar tidak berat atau menyebabkan luka atau patah tulang (Nafisah Ghafournia, 2017).
Selain perintah kepatuhan pada suami, ayat lain yang sering menjadi rujukan misalnya perintah untuk tetap tinggal di rumah (QS Al-Ahzab: 33) dan hadis yang sering dikutip terkait dengan larangan untuk menolak ajakan berhubungan seksual bagi istri. Ayat dan hadis seperti itu sering menjadi sumber legitimasi kekerasan yang dialami perempuan seperti yang terungkap dari alasan adanya KDRT di atas.
Upaya eliminasi
Kompleksitas akar persoalan KDRT seperti digambarkan di atas bisa jadi membuat kita pesimistis apakah sebetulnya kekerasan terhadap perempuan, terutama di ranah rumah tangga, bisa dieliminasi. Ada banyak perempuan yang enggan melaporkan kejadian kekerasan yang dialami mereka dan memilih untuk tetap tinggal bersama pasangan (suami) pelaku kekerasan karena berbagai alasan: ada anak, malu jika menjadi janda, tergantung secara ekonomi, atau merasa tidak aman karena mendapat intimidasi dan ancaman jika memilih berpisah.
Sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk menurunkan angka KDRT dan layanan bantuan untuk korban. Kementerian PPPA, misalnya, sudah memiliki hotline layanan untuk pengaduan korban kekerasan melalui Sapa 129 dan telah ada layanan di setiap kabupaten atau kota yang sudah memiliki Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Begitu juga Komnas Perempuan menerima layanan aduan jika mengalami atau mengetahui KDRT (Telepon: 021-3903963).
Namun, program yang fokus pada laki-laki sebagai pelaku belum banyak dilakukan. Karena itu, upaya eliminasi ke depan perlu juga menyasar dan memberikan rehabilitasi bagi pelaku, terutama laki-laki, anak atau remaja laki-laki yang terpapar KDRT atau memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan. Intervensi sejak dini pada anak atau remaja laki-laki penting dilakukan, terutama jika mereka merupakan korban KDRT dalam keluarga mereka.
Selain itu, masih perlu adanya penyadaran masyarakat untuk peduli dan peka terhadap KDRT di tengah masyarakat secara umum sehingga mereka yang mengetahui kasus-kasus KDRT tidak tinggal diam. Pemberdayaan perempuan korban dan rehabilitasi psikis penting untuk dilakukan, teruama untuk mengobati trauma psikologis yang diderita korban.
Perlindungan bagi anak korban KDRT juga perlu menjadi perhatian agar anak tidak menjadi korban berikutnya dan tidak menjadi pelaku kekerasan pada masa dewasanya (intergenerational violence).
Selain peran masyarakat, penguatan peran pemerintah, terutama penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, perlu terus dilakukan agar kepolisian dan peradilan kita lebih ramah dan berkeadilan gender dalam merespons persoalan KDRT yang dilaporkan oleh masyarakat.Oleh: NN Pemerhati Sosial Masyarakat.(*)


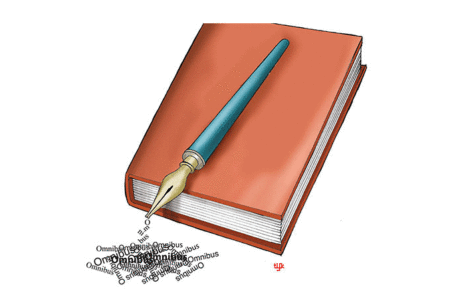









Tinggalkan Balasan