Revisi UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha di Daerah
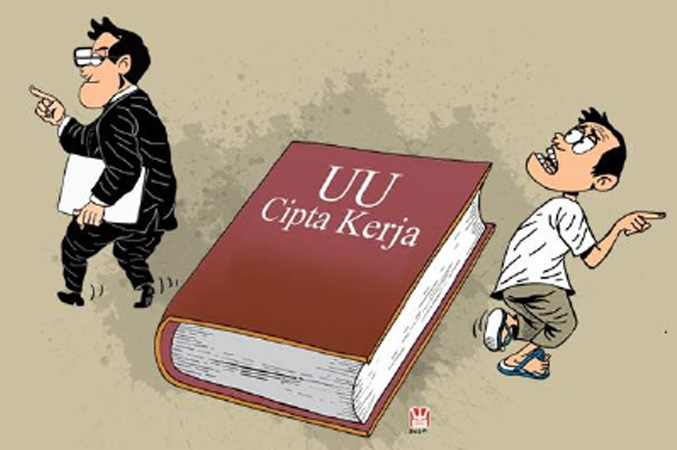
Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi nirmakna bagi penciptaan kemudahan berusaha jika tidak diikuti dengan perbaikan sistematis UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya.
Aral sesungguhnya masih terbungkus rapi dalam regulasi-regulasi tersebut dan berkelindan dengan ego sektoral yang tampaknya dilihat sebagai ”DNA” kementerian/lembaga ketimbang penyakit yang mesti diberantas.
Revisi ini semakin urgen mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memberikan alarm terkait mandeknya investasi bernilai triliunan rupiah lantaran pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) darat (Rp 115,45 triliun) dan persetujuan lingkungan (Rp 10,73 triliun) tidak dapat diproses melalui sistem pelayanan elektronik online single submission risk based approach (OSS RBA).
Sketsa masalah
UU Cipta Kerja merupakan proyek deregulasi yang dinilai mampu mengatasi obesitas dan tumpang tindih peraturan perizinan berusaha.
Baca Juga: Review Pengeluaran APBN Semester I Tahun 2022, Wilayah Kerja KPPN AmbonKajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2019) juga merekomendasikan pendekatan omnibus law dalam mengatasi sengkarut regulasi perizinan. Kehadiran beleid ini pun bak oase di tengah upaya pemerintah meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) dan daya saing daerah berkelanjutan yang masih menunjukkan kinerja rendah (KPPOD, 2020).
Selain menyimplikasi jumlah acuan regulasi, UU sapu jagat ini juga mengubah paradigma layanan perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko.
Sialnya, pada tataran isi regulasi, aras kelembagaan, dan platform layanan berbasis digital terdapat noktah-noktah yang menodai deregulasi itu sendiri dan mengunci secara struktural upaya penciptaan kemudahan berusaha di daerah (KPPOD 2021).
Pada sisi kebijakan, pengaturan yang belum solid dalam UU Cipta Kerja sendiri menjadi sumber soal. UU ini tak tegas menyatakan OSS RBA sebagai satu-satunya sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Ketidaktegasan ini berdampak pada munculnya sistem-sistem sektoral pada kementerian/lembaga (K/L) yang sulit berintegrasi dengan OSS RBB.
Lebih dari itu, UU ini sangat menekankan pusat (Presiden) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang memuluskan ”sentralisasi” sejumlah prosedur pelayanan perizinan berusaha dari daerah.
Regulasi-regulasi turunan UU Cipta Kerja juga tak luput dari persoalan. Sebut saja yang terkait persyaratan dasar perizinan berusaha, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, PP No 16/2021 tentang Bangunan Gedung, PP No 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, PP No 22/2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP No 06/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Regulasi-regulasi ini ternyata bukan turunan terakhir di level nasional sebelum ke peraturan daerah. Peraturan-peraturan ini masih menurunkan sejumlah ketentuan teknis ke peraturan-peraturan menteri. Di sini, ruang terbuka lebar untuk kembali penyakit lama, di mana peraturan-peraturan menteri sektoral menjadi biang ruwetnya perizinan berusaha.
Pada sisi substansi, peraturan turunan juga belum tuntas. Sebagai contoh, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) belum diatur tuntas dalam PP No 05/2021.
Peraturan ini juga belum mengatur batasan dalam penerapan diskresi oleh pemerintah daerah dalam penerapan sistem OSS RBA. Ketidaksolidan ini memberikan kegamangan pemda dalam pelayanan dan memberikan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Mesti disadari, ketidakpastian ini memberikan kesempatan emas bagi permufakatan jahat (penyuapan) di sektor perizinan selama ini.
Bergeser ke ranah kebijakan daerah peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) juga belum siap. Yang paling krusial adalah Perkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Saat ini, baru terbentuk 50-an RDTR dari 2.000 RDTR yang ditargetkan Kementerian ATR/BPN.
Ini sangat mengkhawatirkan karena penataan ruang merupakan panglima yang menentukan implementasi OSS RBA sekaligus determinan yang menentukan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan daerah.
Kajian KPPOD (2019) menunjukkan bahwa perubahan legalitas RDTR dari perda ke perkada hanya menyelesaikan secuil soal. Masalah besar lain muncul pada proses mendapatkan persetujuan substansi dari Pusat, di mana Kementerian ATR/BPN mesti berkoordinasi dengan kementerian lain.
Tahapan ini tentu tidak menjadi kerikil tajam jika K/L mampu melepaskan ego sektoralnya. Persis inilah yang dikeluhkan Presiden Jokowi seperti diberitakan Kompas (10/6/2022).
Dimensi soal berikutnya adalah problem kelembagaan di level pusat, terutama kesulitan dalam menata irama kerja K/L menjadi satu orkestrasi menuju kemudahan dan kepastian berusaha. Lembaga OSS sebagai satu-satunya pintu keluar masuk pelayanan perizinan berusaha tampaknya susah direalisasikan. Setiap K/L masih merasa memiliki kewenangan sektoral.
Alhasil, pelimpahan kewenangan ke lembaga OSS dan pengintegrasian sistem pelayanan ke OSS RBA masih menjadi tantangan tersendiri.
Masalah kelembagaan ini merambat ke proses integrasi antarsistem K/L dengan OSS RBA dan sistem pendukung daerah dengan OSS RBA. Kajian KPPOD menunjukkan integrasi antara OSS RBA dan sistem perizinan dasar lain, seperti SIMBG (persetujuan bangunan gedung), GISTARU (persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang), dan AMDALNet (persetujuan lingkungan), tak berjalan sebagaimana mestinya.
Akibatnya, selain pelaku usaha berhadapan dengan banyak aplikasi dalam mendapatkan perizinan dasar dan perizinan sektoral, layanan perizinan pun mandek, yang berujung pada terhambatnya realisasi investasi senilai triliunan rupiah.
Rasionalitas instrumental tata kelola
Sengkarut ini bersumber pada keterjebakan pranata politik dan institusi birokrasi pada ruang rasionalitas instrumental dalam tata kelola kebijakan perizinan berusaha.
Menggunakan perspektif filsuf dan pemikir sosial J Habermas, perangkap rasionalitas ini membuat tata kelola perencanaan-perancangan dan implementasi kebijakan diutilisasi semata sebagai alat untuk mengkalkulasi dan jalan untuk mencapai kepentingan subyektif tertentu. Parahnya lagi, para perancang kebijakan kehilangan otonomi dan daya kritisnya.
Mereka terperangkap dalam relasi patron-client monologis antara pemilik power (politik) dan perancang kebijakan (birokrat). Fenomena ini tampak dalam perancangan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya.
Meski harus diakui, deregulasi dengan pendekatan omnibus law ampuh mengatasi obesitas regulasi dan menggaransi kemudahan dan kepastian berusaha di masa depan, kepentingan politik untuk ”cepat membuktikan” reformasi regulasi ke publik begitu besar, menjadikan proses perancangan kebijakan terkesan ugal-ugalan.
Yang terpenting sampai tujuan: UU dan peraturan turunan selesai. Titik. Implikasinya jelas. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam penyusunan regulasi masih jauh panggang dari api. Drama-drama penyusunan ini hanya mementaskan fenomena partisipasi terbatas-semu, nir-transparan, kehilangan akuntabilitas, dan bercorak ekstraktif. Hasilnya pun tampak gamblang. Kebijakan yang tak solid seperti tergambar dalam sketsa masalah di atas.
Tindak lanjut
Kompleksnya persoalan di atas membuat upaya menciptakan kemudahan dan kepastian berusaha di Indonesia masih menghadapi jalan terjal. Tak cukup berpuas diri dengan revisi UU PPP, berikut beberapa langkah yang harus diperhatikan.
Pertama, terkait revisi UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya. Dalam konteks perizinan berusaha, beleid ini harus tegas menyatakan OSS RBA adalah satu-satunya layanan sistem perizinan berusaha.
Publik hanya berhadapan dengan satu platform layanan, yaitu OSS RBA. Penegasan ini akan menutup ruang bagi munculnya pintu-pintu baru dalam layanan perizinan. Jika ada sistem lain, harus diintegrasikan ke OSS RBA.
Kedua, penetapan masa transisi kebijakan. Pada masa transisi ini, pemda diberi kesempatan untuk memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan daya dukung daerah (disesuaikan dengan kebijakan yang masih berlaku, infrastruktur yang ada).
Momentum ini juga dipakai pusat untuk menyiapkan peta jalan bagi implementasi pascarevisi kebijakan. Selama ini, implementasi kebijakan sering tidak efektif karena pemberlakuan serentak tanpa peta jalan yang jelas, termasuk memperhatikan kesiapan daerah.
Ketiga, menciptakan kelembagaan politik dan birokrasi yang inklusif. Ini adalah prakondisi atau ”syarat perlu” determinan yang membutuhkan gerakan bersama semua elemen (stakeholders) pembangunan (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, buruh, dunia usaha, media massa).
Selain membebaskan dua institusi tersebut dari jeratan relasi patron-client, kelembagaan inklusif ini akan memberikan dan membuka akses bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) untuk terlibat dalam tata kelola kebijakan publik di negeri ini. Oleh: Herman N Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan