UU Ciptaker, Kembalinya Muruah Hukum Sipil

KETIKA tulisan ini dibuat, ada beberapa versi draf fi nal dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disetujui DPR pada 5 Oktober 2020. Demonstrasi atas UU ini juga berlangsung secara serentak di berbagai daerah. Tulisan ini tidak dibuat untuk membahas isi dan proses pembuatan UU Cipta Kerja, tetapi menyampaikan posisi omnibus law dalam struktur sistem hukum di Indonesia. Ini semacam catatan kaki bagi lahirnya omnibus law untuk bidang-bidang lainnya. Sistem hukum Saat ini, dalam dunia hukum modern dikenal dua sistem hukum meski hukum syariah sudah mulai dimasukkan juga, yaitu civil law dan common law. Kedua sistem ini meski berasal dari Eropa, memiliki kekhususannya.
Civil law lahir dari kode sipil (civil code) yang diberlakukan bangsa Romawi bagi negara-negara jajahannya. Negara-negara Eropa daratan (kontinental) banyak menggunakan sistem hukum ini dalam membentuk bangunan hukum negaranya. Hal itu yang membuat sistem hukum civil law ini juga disebut sebagai sistem hukum kontinental. Dalam sistem hukum ini, bangsa Romawi menuliskan pasal-pasal yang dipaksakan kepada rakyat jajahannya untuk dipatuhi dan dijalankan. Dalam deretan pasal-pasal tersebutlah segala urusan disebutkan secara detail dan ditambahkan bertahap sesuai kebutuhan yang ada. Semakin kompleksnya perkembangan masyarakat, membuat dalam sistem hukum ini, diperlukan pengelompokan aturan untuk urusan-urusan tertentu. Kodifikasi hukum menjadi mekanisme bagaimana peraturan itu dikumpulkan dan disatukan untuk berbagai macam urusan terkait, dengan diberi nama sesuai tujuan melakukan kodifikasi tersebut. Jika ada perkembangan yang membutuhkan pengaturan baru, akan dilihat apakah itu akan mengubah kodifikasi yang sudah ada. Bahkan, jika dirasa ada asas-asas baru yang akan ditambahkan bisa saja dalam, biasanya, bagian awal kitab kodifi kasi tersebut ditambahkan asas barunya dan pasal-pasal lain kemudian disesuaikan dengan asas baru itu.
Dalam proses penegakan hukumnya juga akan sangat kelihatan mana yang disebut sebagai aturan umum (lex generalis) dan aturan khusus (lex specialis). Para penegak hukum akan merujuk kepada aturan yang khusus jika perkaranya tidak bisa dikategorikan sebagai peristiwa yang diatur secara umum. Peradilan pun kemudian dibuat seperti ada seorang ahli hukum yang dianggap lebih menguasai hukum dan memiliki posisi terhormat untuk memeriksa jalannya perkara. Hakim bertindak seperti seorang magistrate yang mengendalikan jalannya peradilan dengan kewenangan penuh untuk bertanya kepada para pihak yang beperkara. Kendali utama antara pihak yang menuntut atau menggugat dan pihak yang dituntut atau digugat, sepenuhnya kewenangan hakim. Konsekuensinya, hakim lebih aktif bertanya dalam persidangan. Para pihak, sekalipun diberi kesempatan menyampaikan gugatan/tuntutannya atau menjawab gugatan atau membela diri dari tuntutan, seolah-olah diajukan kepada hakim.
Hakim yang akan memutuskan perkara ini, baik berdasarkan fakta nyata maupun interpretasi hukumnya. Konsekuensinya, dalam peradilan pun para pihak yang beperkara akan menyandarkan argumentasinya kepada peraturan-peraturan positif normative ketimbang kepada putusan-putusan pengadilan sebelumnya karena hakim yang memeriksa perkara memiliki kewenangan mutlak untuk itu. Sementara itu, dalam sistem common law yang digunakan di Inggris dan kebanyakan negara commonwealth lainnya, seperti Australia, AS, Malaysia, dan Kanada, cara pembuatan UU bersifat lepas-lepas. Tidak ada kodifikasi secara terpusat. Kebutuhan akan adanya pengaturan baru akibat adanya perkembangan masyarakat dilakukan dengan menerbitkan UU baru. Akibatnya, satu UU dengan lainnya bisa saja menggunakan asas yang tidak sama. Interpretasi terhadap pasal-pasal itu menjadi kebebasan para pihak yang nantinya berperkara. Dalam peradilannya, para pihak yang beperkara mendasarkan argumentasinya dari interpretasi pasal-pasal peraturan.
Salah satu interpretasi yang dianggap sahih ialah apabila interpretasi itu dapat ditunjukkan sudah digunakan dalam keputusankeputusan hakim sebelumnya. Sangat kelihatan argumentasi mereka tidak disandarkan kepada pasal dalam UU, tetapi lebih kepada putusan-putusan hakim yang sudah terjadi untuk kasus-kasus masa lampau. Suatu gugatan/tuntutan atau jawaban terhadap gugatan dan atau pembelaan sering kali disandarkan dengan merujuk kepada kasus daripada pasal yang mengatur.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Vaksin Aman Untuk MasyarakatPosisi hakim pun pada saat persidangan lebih bersifat pasif, membiarkan para pihak yang berperkara saling beradu argumen, kadang di depan juri atau di depan hakim. Hakim hanya memastikan tiap-tiap pihak mendapatkan kesempatan yang wajar dan adil dalam menyampaikan perkara dan argumennya.
Jika ada yang dirasa tidak sesuai, hakim bisa setuju dengan salah satu pihak yang berkeberatan dengan argumentasi lawannya atau menerima jika menolak terhadap keberatan yang diajukan. Kodifi kasi hukum tidak terlalu diperlukan dalam sistem hukum ini. Sistem hukum Indonesia Kerajaan Belanda termasuk yang menggunakan sistem hukum ini. Dalam pengaturannya, Belanda mewariskan pembukuan-pembukuan urus an-urusan utama, seperti Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie (WvS–Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), burgerlijk wetboek voor Indonesie (BW–Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK–Kitab Undang- Undang Hukum Dagang). Sayangnya, dalam perkembangannya, cara kita menerbitkan peraturan lebih mirip cara sistem hukum common law. Antara satu UU dan lainnya diterbitkan secara terpisah dan bahkan dalam pembahasannya seolah tidak pernah disampaikan keterkaitannya secara langsung. Bahkan, kitab-kitab kodifikasi warisan Belanda pun diperlakukan setara seperti UU biasa. Akibatnya, kadang ketika terjadi perkara penegak hukum tidak melihat mana yang aturan umum dan mana yang khusus. Kejadian seorang pemimpin redaksi media massa cetak dituntut dengan pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan bukan dengan UU Pers, menunjukkan tidak adanya pemahaman pembedaan kitab yang menjadi kodifi kasi atau UU biasa yang mengatur secara khusus. Parahnya lagi di Indonesia, tidak ada satu lembaga yang berwenang melakukan sinkronisasi terhadap UU yang lepas-lepas tadi. Pihak yang punya kewenangan yang cukup untuk memutuskan, misalnya, dicabutnya pasal-pasal tertentu dari suatu UU karena ada UU baru, terutama jika seolah-olah kedua UU itu tidak saling terkait.
MK lebih memiliki kewenangan apabila ada UU yang tidak sesuai dengan UUD, tetapi tidak antar-UU. Catatan akhir Sebenarnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi mengusulkan adanya omnibus law bisa ditilik sebagai upaya mengembalikan lagi muruah hukum sipil sebagai tulang punggung sistem hukum kita. Menyatukan berbagai macam UU yang terkait ke dalam satu tubuh UU besar sehingga lebih komprehensif, layak diupayakan. Hanya, dalam prosesnya, omnibus law ini belum menggunakan struktur yang layaknya dikenal dalam sebuah kodifikasi.
Namun, masih menggabungkan UU lepas itu dengan mencabut, mengubah, atau menambah pasal-pasal untuk disesuaikan dengan tujuan utama kodifi kasi ini. Namun, sebagai sebuah langkah awal setelah kita meninggalkan mekanisme kodifi kasi ini (bahkan merevisi KUH Pidana saja belum selesai sampai saat ini), layak diapresiasi.

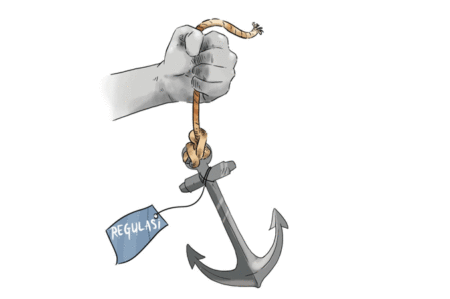


Tinggalkan Balasan