Sengkarut Rekrutmen Hakim, Eksekutif Mendikte Yudikatif

BAYANGKAN seandainya TNI tidak merekrut prajurit dan taruna selama lima tahun berturut-turut, apa yang akan terjadi? Tentu saja kacau. Untung hal itu tidak pernah, dan tak mungkin, terjadi di tubuh TNI. Begitu juga di Polri atau di berbagai lembaga pemerintahan. Rekrutmen berjalan secara rutin tiap tahun. Namun, tidak demikian halnya di Mahkamah Agung (MA), pilar yudikatif Indonesia. Di sini pernah terjadi moratorium rekrutmen calon hakim. Bukan hanya lima tahun, melainkan juga tujuh tahun berturut-turut dari 2010 hingga 2017. Baru pada 2017 dilakukan rekrutmen satu kali. Anehnya, setelah 2017, selanjutnya tidak juga dilakukan rekrutmen secara rutin. Baru pada 2021 dilakukan rekrutmen. Itu pun hanya secara ‘darurat’. Pemerintah (Kemenpan-Rebiro, BKN, Kemenkeu, dan Setneg) memberikan kesempatan kepada MA untuk mendidik analis perkara pengadilan menjadi calon hakim. Akan tetapi, itu hanya sekali. Ini moratorium berkepanjangan yang nyata terjadi pada MA. Seakan lembaga yudikatif ialah anak tiri di antara ketiga ‘anak’ trias politika.
Langgar UU Moratorium berkepanjangan jelas menimbulkan masalah. Dalam keadaan sekarang saja, kuota hakim untuk pengadilan yang ada tak terpenuhi, apalagi pada tahun-tahun mendatang jika tidak dilakukan rekrutmen rutin. Ingat, setiap tahun ada ratusan hakim yang pensiun atau meninggal. Masalahnya bukan hanya pada beban kerja hakim, melainkan juga pada manajemen. Tidak hanya sekarang, tapi juga belasan tahun mendatang. Sebagai contoh, masalah pimpinan pengadilan tingkat pertama pada 15 tahun yang akan datang. Ketika itu, hakim generasi 2009, generasi terakhir sebelum moratorium, sudah tidak cocok lagi menjadi ketua pengadilan kelas II karena pangkatnya sudah IV C. Sementara itu, 1.500-an generasi 2017, yaitu generasi setelah moratorium, belum memenuhi syarat karena baru berpangkat III C. Menurut aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pimpinan pengadilan kelas II berpangkat IV A. Jika tetap terikat pada aturan tersebut, 15 tahun yang akan datang akan terjadi kekosongan pimpinan pengadilan kelas II. Generasi di atasnya sudah IV C, tentu tak cocok lagi secara kepangkatan.
Sementara itu, generasi di bawahnya belum memenuhi syarat. Yang fatal, MA terpaksa melanggar UU karena banyak pengadilan yang hanya memiliki tiga hakim. Setiap hari ada saja permohonan hakim tunggal dari pengadilan-pengadilan dan Ketua MA terpaksa menyetujuinya. Kalau tidak dipenuhi, persidangan tak bisa berlangsung. Kekosongan legislasi Akar permasalahannya sebenarnya sederhana sekali, yaitu moratorium berkepanjangan. Itu terjadi akibat tiadanya aturan pelaksanaan perundang-undangan yang memungkinkan MA menyelenggarakan sendiri rekrutmen hakim sesuai dengan kebutuhannya. Undang-Undang No 48/2009 sudah menyatakan hakim merupakan pejabat negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 43/PUU-XII/2015 sudah menegaskan rekrutmen calon hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan MA. Namun, tidak ada aturan perundang-undangan tentang bagaimana rekrutmen calon hakim sebagai calon pejabat negara itu dijalankan. Tiadanya aturan pelaksanaan rekrutmen calon hakim sebagai calon pejabat negara memaksa MA mengikuti mekanisme yang ditentukan pemerintah untuk rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Maka itu, dapat dikatakan dalam hal ini lembaga yudikatif MA didikte lembaga eksekutif. Buktinya, jika pemerintah tidak mengakomodasi angka kebutuhan yang diajukan MA, MA pun tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi kekosongan aturan pelaksanaan rekrutmen calon hakim sebagai calon pejabat negara, dua kali MA terpaksa mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2/2017 dan No 1/2021. Kedua perma itu diterbitkan karena rekrutmen calon hakim yang bersamaan dengan rekrutmen ASN bukan kewenangan Kemenpan-Rebiro. Kewenangan Kemenpan-Rebiro hanya untuk rekrutmen ASN. Sifatnya darurat, tambal sulam untuk ketiadaan aturan pelaksanaan rekrutmen calon hakim dan masing-masing hanya berlaku untuk sekali rekrutmen. Catatan khusus layak dibuat untuk rekrutmen 2021 karena sebenarnya rekrutmen tahun itu tanpa perencanaan. MA hanya kebagian formasi 3.000-an ASN, separuh di antaranya untuk jabatan APP (analis perkara peradilan). Karena kebutuhan mendesak akan hakim, MA harus bernegosiasi dengan pemerintah agar APP tersebut dapat dialihkan menjadi calon hakim. Sekali lagi, ini menunjukkan begitu lemahnya bargaining position MA di mata pemerintah dalam rekrutmen tulang punggung peradilan Indonesia.
Solusi permanen Kebijakan tambal sulam tak boleh diteruskan. MA dan pemerintah harus menemukan jalan keluar bagaimana rekrutmen hakim ke depan bisa dilakukan secara rutin. Hal itu harus dilakukan sekarang pada 2022. Inti sebenarnya hanya aturan pelaksanaan UU Peradilan, yaitu untuk mengatasi kebuntuan pengadaan hakim akibat kekosongan regulasi. Terkait hal tersebut harus segera diterbitkan aturan pelaksanaan UU Peradilan menyangkut rekrutmen calon hakim sebagai pejabat negara. Aturan pelaksanaan itu bentuknya bisa peraturan pemerintah (PP), bisa juga peraturan presiden (Perpres). Yang penting, isinya menegaskan bahwa MA berwenang merekrut calon hakim secara rutin sesuai dengan kebutuhan tanpa bergantung pada formasi rekrutmen ASN yang diselenggarakan pemerintah.
Baca Juga: Proses Transisi Menuju ke Arah EndemiSelain itu, dalam PP atau perpres yang akan diterbitkan itu, harus ditegaskan bahwa kewenangan rekrutmen tersebut berada di tangan MA. Rekrutmen calon hakim tak boleh tergantung pada kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa melakukan moratorium secara sepihak sebab kebutuhan akan hakim sudah jelas karena tiap tahun dibutuhkan hakim baru. Setidaknya untuk menggantikan sejumlah hakim yang pensiun dan meninggal. MA harus berupaya keras agar pemerintah segera menerbitkan PP atau perpres itu. Yang pasti, dikte pemerintah harus dihentikan segera. Oleh: Viktor Pane Pemerhati peradilan Indonesia



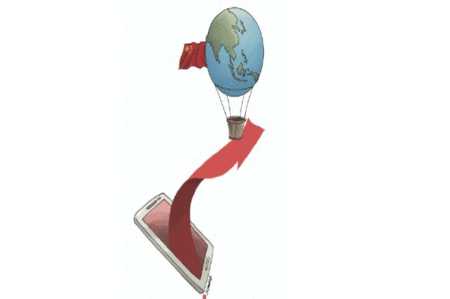
Tinggalkan Balasan