Polarisasi dan Merosotnya Demokrasi

BERBAGAI studi mutakhir tentang demokrasi menunjukkan keterkaitan erat antara polarisasi dan tren global redupnya demokrasi. Bersama politik identitas dan populisme, polarisasi dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi.
Polarisasi adalah keterbelahan masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik. Umumnya terjadi karena perubahan sosiokultural dalam masyarakat dan munculnya elite-elite politik baru yang memanfaatkan perubahan itu.
Perbedaan dalam masyarakat adalah sesuatu yang wajar dan mestinya tak perlu dicemaskan. Demokrasi menampung perbedaan itu serta menyalurkannya dalam bentuk partai politik dan organisasi masyarakat. Sikap partisan atau keberpihakan kepada partai tidak dianggap sebagai hal yang negatif. Sebaliknya, ia adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi.
Polarisasi berbeda dari keberpihakan politik atau partisan. Menurut Nolan McCarty (2019), partisan adalah sikap dalam mendukung suatu partai, terlepas apakah sikap itu muncul karena perbedaan pandangan yang tajam (polarisasi) atau karena sebab lain. Adapun polarisasi adalah perbedaan dalam menyikapi isu-isu fundamental.
Partisan umumnya dianggap sebagai sikap yang wajar dan penting dalam demokrasi, sedangkan polarisasi dinilai sebagai sesuatu yang kurang sehat. Bahkan, belakangan, istilah ini sering disebut senapas dengan hal-hal yang negatif, seperti konflik, ketegangan, dan intoleransi.
Baca Juga: Revisi UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha di DaerahDalam konteks itulah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melontarkan pernyataan yang kontroversial baru-baru ini bahwa lebih baik tidak ada pemilu jika pemilu hanya melahirkan perpecahan. Menurutnya, polarisasi di Indonesia sudah sangat mencemaskan, yang jika tidak diatasi, bisa berdampak buruk bagi demokrasi kita.
Pernyataan Surya Paloh bukan tanpa dasar. Dalam sebuah tulisannya, Eve Warburton (2019), sarjana asal Australia, menegaskan hal yang kurang lebih sama bahwa polarisasi di Indonesia ‘sudah menggerus lembaga-lembaga demokrasi dan merusak bangunan sosialnya’ (polarization is already eroding Indonesia’s democratic institutions and damaging its social fabric).
Sebab polarisasi
Mengapa polarisasi menguat di Indonesia? Dan mengapa terjadi sekarang? Sebetulnya, Indonesia tidaklah sendirian. Polarisasi adalah fenomena global yang belakangan menimpa banyak negara di dunia. Tak hanya negara-negara berkembang, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris juga mengalaminya.
India, negara demokrasi terbesar di dunia, mengalami keterbelahan politik sejak tiga dekade terakhir. Turki juga menjalani hal sama sejak Recep Tayyip Erdogan menguasai negeri itu pada awal tahun 2000-an. Beberapa negara di Amerika Latin, seperti Venezuela, Bolivia, Kolombia, dan Brasil, berjuang keras mengatasi ketegangan dan konflik akibat keterbelahan sikap politik masyarakatnya.
Masing-masing memiliki latar belakang dan sebab khusus, mengapa polarisasi terjadi. Sebagian bersumber dari perbedaan ideologi dan isu-isu kebijakan publik, seperti terjadi di Amerika Serikat. Sebagian lainnya dipicu karena perbedaan kelas dan agama, seperti terjadi di Amerika Latin dan beberapa negara muslim.
Di Indonesia, polarisasi sebenarnya bukanlah hal baru. Ia pernah ada pada zaman Soekarno, yang berujung pada konflik massa tahun 1965. Menurut Dan Slater dan Aries Arugay (2018), jika dibandingkan dengan di negara-negara Asia lainnya, tingkat polarisasi di Indonesia sebetulnya tergolong rendah meski bahan bakar konflik di tengah masyarakat cukup banyak.
Sejak Reformasi 1999 hingga 2014, politik Indonesia relatif ‘stabil’. Tidak ada pembelahan politik yang ekstrem seperti terjadi sejak 2014. Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berusaha merangkul semua pihak dan menekankan pentingnya stabilitas politik menjadi sebab utama mengapa polarisasi tak terlihat pada era itu.
Beberapa pengamat menganggap langkah yang diambil SBY sebagai sesuatu yang bagus. Akan tetapi, sebagian lain menganggapnya sebagai bom waktu yang bisa meledak suatu saat. Kebijakan SBY dalam merangkul semua pihak, termasuk elemen-elemen ultrakonservatif dalam pemerintahannya, melahirkan perubahan sosial-politik yang fundamental, yang dampaknya baru terasa sekarang.
Berbeda dari Amerika dan beberapa negara lain, polarisasi di Indonesia umumnya berbasis agama. Pada satu sisi, ada kelompok ‘nasionalis’ yang ingin menyelenggarakan negara dengan cara-cara yang plural dan setara untuk semua orang. Pada sisi lain, ada kelompok ‘islamis’ yang merasa bahwa kepentingan Islam harus diprioritaskan dan diberi perhatian lebih besar.
Studi-studi tentang bangkitnya konservatisme di Indonesia merujuk pada kebijakan-kebijakan islamis yang terjadi pada masa SBY, yang berdampak luas bagi perubahan identitas masyarakat Indonesia. Sejak 15 tahun terakhir terjadi gelombang islamisasi yang sangat kuat di negeri ini. Apa yang dilakukan Soeharto pada masa akhir kekuasaannya mengalami puncaknya pada masa SBY.
Polarisasi dipicu, salah satunya, oleh menguatnya identitas Islam pada sebagian masyarakat Indonesia. Benih-benihnya sudah ada sejak lama, tapi ekspresi publiknya baru mengalami momentum pada Pemilu 2014. Elite politik adalah sebab kedua mengapa polarisasi di Indonesia muncul lagi. Identitas Islam yang membuncah digunakan oleh sekelompok elite untuk memobilisasi suara.
Semangat keagamaan dan perilaku elite menjadi kombinasi yang efektif dalam menciptakan keterbelahan di Indonesia. Pola ini terulang lagi pada Pilkada DKI 2017 dan kembali menguat pada Pemilu 2019. Jika tak ada tindakan untuk mengubahnya, pola yang sama agaknya bakal terjadi lagi pada Pemilu 2024.
Dampak polarisasi
Bahwa polarisasi adalah sesuatu yang negatif sudah banyak diketahui orang. Akan tetapi, bahwa daya rusaknya cukup besar dalam menggerogoti institusi-institusi demokrasi tampaknya kurang disadari. Studi Thomas Carothers dan Andrew O’Donohue (2019) tentang merosotnya demokrasi di berbagai negara mendaftar sejumlah dampak buruk polarisasi.
Setidaknya ada enam masalah yang muncul akibat keterbelahan politik di tengah masyarakat. Pertama, polarisasi merusak institusi-institusi demokrasi, terutama lembaga hukum. Keterbelahan politik melahirkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik kepada pengadilan karena pengadilan dianggap sebagai instrumen penguasa.
Kita sering mendengar dan membaca berita tentang luapan ketidakpercayaan sebagian masyarakat kepada proses pengadilan, baik terhadap pemimpin FPI Muhammad Rizieq Shihab maupun tokoh-tokoh oposisi lainnya. Mereka menganggap bahwa proses pengadilan terhadap Rizieq Shihab dan tokoh-tokoh oposisi sebagai bagian dari rekayasa penguasa.
Kedua, polarisasi memperlemah dan menghalang-halangi proses pembuatan undang-undang. Polarisasi bukan hanya tentang perbedaan, tapi juga tentang kebencian dan kecurigaan terhadap apa saja yang datang dari lawan politik. Pembuatan undang-undang sejatinya melewati proses diskusi dan perdebatan yang rasional. Namun, polarisasi kerap mengakhiri percakapan yang waras.
Di Indonesia, hal ini terlihat jelas pada beberapa penanganan RUU (rancangan undang-undang). Partai oposisi menolak sebuah RUU bukan karena isinya buruk, tapi karena yang mengajukannya adalah lawan politik yang tak bisa dimaafkan. Perdebatan seputar RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) adalah salah satu contoh nyata bagaiman polarisasi menghambat proses pengesahan undang-undang penting ini.
Ketiga, polarisasi berdampak pada pelecehan institusi kepresidenan. Karena presiden dipilih hanya oleh sebagian orang, dia dianggap bukan sebagai presiden semua warga. Penolakan dan perundungan terhadap Jokowi pada pilpres berlanjut terus, bahkan jauh setelah pilpres berakhir.
Pelecehan terhadap presiden dan institusi kepresidenan juga terjadi di Amerika Serikat. Perbedaan yang tajam di tengah warga membuat Donald Trump mengalami penolakan yang sangat keras dari para penentangnya. Tingkat pelecehan dan perundungan terhadap Trump tak pernah ada presedennya dalam sejarah Amerika Serikat.
Keempat, polarisasi juga menghilangkan kredibiltas partai politik. Karena partai politik berusaha ‘populis’ dan ikut terlibat dalam pertengkaran-pertengkaran dua kelompok yang berseteru, mereka tak lagi memiliki agenda yang jelas. Alih-alih memikirkan hal-hal fundamental, partai politik terlibat dalam perdebatan tak produktif, seperti isu tes keperawanan, rendang babi, label halal, pengeras suara, ketentuan salat berjemaah, poligami, dan sejenisnya.
Kelima, polarisasi tak hanya merusak beberapa aspek demokrasi di dalam negeri, tapi juga berdampak pada penyikapan masyarakat terhadap isu-isu yang terkait dengan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri pemerintah yang seharusnya mendapat dukungan mengalami penolakan dan kritik keras, bukan karena kebijakan itu buruk, tapi simply karena mereka tak suka dengan sang presiden.
Keenam, dampak paling buruk dari polarisasi adalah meningkatnya intoleransi dan kekerasan di tengah masyarakat. Karena mereka tak lagi percaya kepada pengadilan dan lembaga-lembaga pemerintah, solusinya adalah kekerasan di jalanan. Kasus pengeroyokan yang terjadi pada Ade Armando beberapa bulan lalu adalah contoh nyata dari dampak buruk polarisasi.
Ikhtiar politik
Lalu, apakah indikasi-indikasi di atas cukup untuk mengatakan bahwa polarisasi di Indonesia sudah parah? Jika kita menyimak pandangan para pengamat dan elite Indonesia, mereka terbelah. Sebagian menganggapnya masih dalam batas normal. Sebagian lain, seperti tampak jelas dalam pernyataan Surya Paloh, polarisasi berbahaya dan sudah merusak sendi-sendi demokrasi kita.
Tentu saja, dampak paling destruktif polarisasi, yakni konflik bersenjata, belum terjadi di Indonesia. Perang saudara seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman adalah dampak terburuk polarisasi. Dampak terburuk berikutnya, intervensi militer, juga belum terjadi di Indonesia. Polarisasi yang tajam di Mesir pada 2013 berujung pada kudeta militer dan membawa negeri itu kembali ke era otoritarian.
Yang sudah jelas terjadi di Indonesia ialah rusaknya institusi-institusi demokrasi. Polarisasi telah menciptakan berbagai problem yang sudah saya jelaskan di atas. Turunnya kualitas demokrasi kita, salah satunya, disebabkan oleh keterbelahan politik di tengah masyarakat ini.
Pada akhirnya, kita cuma punya dua pilihan: membiarkan terus situasi ini berlanjut atau mencari jalan keluar dengan melakukan ikhtiar politik, termasuk dengan cara-cara yang tidak populer.Oleh: Luthfi Assyaukanie Dosen di Universitas Paramadina dan Staf Ahli Wakil Ketua MPR RI (*)



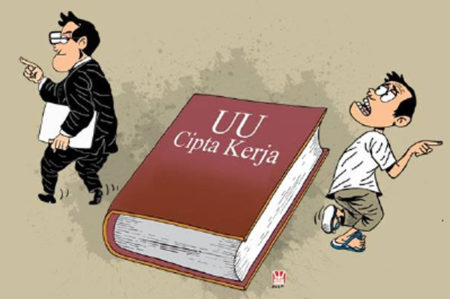
Tinggalkan Balasan