Kurikulum ini itu dan Penilaian

PENILAIAN adalah salah satu bentuk evaluasi proses pembelajaran. Ada yang dilaksanakan secara harian, tengah semester, dan akhir semester. Penilaian dilakukan untuk melihat seberapa siswa memahami materi yang sudah diajarkan. Hasil akhir belajar itu biasanya dalam bentuk rapor. Mencakup kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan.
Dinamika penilaian Tak salah jika kita kembali merefleksi bagaimana dinamika sekolah dalam memberikan nilai rapor yang tak hanya sebatas angka-angka. Angka-angka itu merepresentasi proses panjang yang mengerahkan segala daya upaya dan melibatkan para pihak. Dalam memberikan nilai rapor, guru memperhitungkan banyak hal sebagai pertimbangan, dan biasanya pertimbangan nonteknis pembelajaran. Pertama, memberikan nilai kasih sayang kepada siswa karena sikapnya dianggap sopan di kelas. Padahal dalam kurikulum telah jelas dipisahkan antara penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Kedua, takut diprotes orangtua. Kondisi ini lumayan banyak terjadi di kalangan orangtua yang tidak siap menerima nilai rendah anaknya. Pernah ada orangtua komplain nilai mata pelajaran agama Islam rendah karena—menurutnya–anaknya pintar mengaji. Ada juga yang ingin memasukkan anaknya ke fakultas kedokteran, tidak akan diterima jika nilai matematika dan bahasa Inggrisnya rendah, juga banyak lagi cerita lain. Ketiga, ini sepertinya sudah terjadi secara sistemik di lingkungan pendidikan kita, sudah berada di fase sangat mengkhawatirkan.
Guru merencanakan nilai anak sejak awal supaya nanti bisa masuk ke universitas melalui jalur undangan. Guru memberikan nilai rendah dianggap telah menghancurkan masa depan anak. Dalam praktik lain, ada pola menabung nilai di setiap semester. Misalnya di semester 1 siswa mendapat (diberikan) nilai 90, maka yang dipasang di rapor ialah 85. Sisanya disimpan untuk semester depan supaya grafik nilai siswa menaik, dan ini akan dianggap bagus oleh universitas. Ini bukanlah semata-mata atas inisiatif guru mata pelajaran, tapi sudah tersistem dari sekolah. Keempat, guru pemalas. Saya berdiskusi dengan banyak guru di banyak sekolah. Mereka bercerita tentang kondisi sekolah masing-masing. Ada hak-hak siswa dalam proses pembelajaran tidak dipenuhi guru, seperti hak siswa untuk remedial, yaitu siswa secara pengetahuan belum memenuhi tujuan pembelajaran. Akan tetapi, karena gurunya malas, biasanya akan diberikan nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) atau bahkan nilai bagus. Harusnya guru melakukan proses remedial, proses pendampingan untuk perbaikan.
Generasi stroberi Nilai rapor yang tidak merepresentasi kemampuan siswa yang sebenarnya, pada dasarnya inilah cara sekolah melahirkan generasi stroberi. Istilah ini muncul untuk menggambarkan generasi Taiwan yang lahir di 1980-an, masa pascaperang. Mereka tidak mau anaknya susah seperti mereka ketika masa perang, dan memanjakannya dengan segala fasilitas yang mewah (nytimes.com). Kini kondisi seperti itu menimpa lingkungan pendidikan kita. Setidaknya empat alasan guru memberikan nilai dalam rapor di atas adalah bentuk upaya kita dalam memanjakan mereka, memberikan kemewahan, membenarkan untuk mereka berleha-leha. Jadinya, mereka tidak punya ‘kesempatan’ untuk menempa diri dalam hal kemandirian, daya tahan, daya juang, serta karakter bertahan di segala tantangan. Mereka menjadi manja, lembek, seperti sifat stroberi yang lunak, mudah koyak ketika terbentur. Saat dihadapkan pada tantangan, anak akan rapuh dan mudah menyerah. Ini akan membuat kita semakin jauh dari makna manusia berkualitas menurut UU No 20 Tahun 2003, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks sekolah, etos kerja dan mentalitas menjadi sangat penting ketika seorang anak berada dalam lingkungan masyarakat, atau ketika berada di bangku perkuliahan. Pendidikan tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Seperti apa ia ditempa, seperti itulah kepribadiannya di masyarakat. Kita mewarisi generasi emas palsu, yang nantinya akan bertindak sebagai pengambil kebijakan (palsu) dan pemecah masalah (palsu) di masyarakat, seperti nilai (palsu) yang ia terima ketika di bangku sekolah.
Mari berbenah Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus segera berbenah. Menurut saya, harus ada kolaborasi yang seimbang antara guru (sekolah), orangtua, dan pemerintah. Saya menempatkan guru (sekolah) di posisi garda terdepan dan pertama dalam upaya mengubah ini semua. Menurut saya, ada idealisme yang hilang dari guru kita hari ini jika kita kembali menilik fungsi guru di sekolah, yakni memberikan pertolongan-pertolongan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik itu kompetensi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pertolongan-pertolongan inilah yang kini kian sulit diperoleh, seakan semakin mahal. Ada selentingan dari guru mengenai anak-anak sekarang yang sudah hilang rasa hormat kepada gurunya. Namun, ada pertanyaan satire, bagaimana siswa bisa menghormati gurunya, sedangkan ia tidak pernah dididik untuk disiplin, jujur, bekerja keras? Guru malah mendidiknya dengan ‘tidak mendidik.’ Pesan karakter apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa jika tanpa hadir ke sekolah ia bisa naik kelas; tidak paham materi bisa mendapatkan nilai bagus. Bagaimana ia bisa menghormati gurunya jika gurunya tidak mendidik apa-apa, jika tidak mau disebut mendidik kemalasan? Di barisan kedua adalah orangtua. Orangtua harus memahami proses dan mendampingi setiap proses itu dengan kesabaran. Banyak orangtua berambisi meraih prestise dengan mendorong anaknya harus juara lomba, harus jago matematika. Jika itu terjadi, anak dianggap berprestasi.
Baca Juga: Subsidi: Di Kala Harus MemilihSekolah dianggap berhasil. Tanpa disadari, hal seperti itu sebenarnya telah menempatkan mereka dalam sebuah jebakan. Barisan paling fundamental ketiga ialah pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Sejak Kurikulum Merdeka diluncurkan, sudah banyak produk pendidikan dihasilkan. Semua produk itu muaranya pada kompetensi lulusan. Kurikulum terus berganti, program peningkatan guru dengan segala macam nomenklatur, sekolah dengan berbagai label, dan kesejahteraan guru terus ditingkatkan dengan macam-macam insentif, tidak akan berdampak apa pun jika proses penilaian di kelas telah jauh dari hakikat penilaian itu sendiri. Kurikulum berganti menjadi ini dan itu, tapi cara mengajar dan menilainya tidak berubah. Mari duduk sejenak, merefleksi apa yang saat ini sedang kita siapkan sebagai warisan untuk anak cucu kita. Oleh: Zubir Direktur Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe.(*)

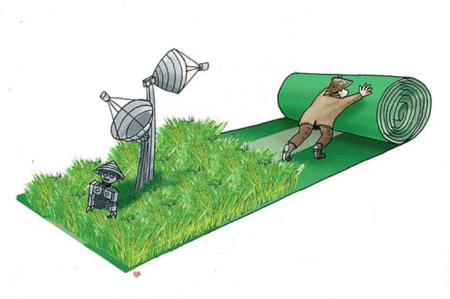


Tinggalkan Balasan