Kontrak Sosial Peningkatan Mutu Pendidikan

KULTUR kecewa, gelisah, dan takut menjadi siklus manusia dalam laju inovasi teknologi. Sajian ketidakpastian global bukan pemenuhan harapan untuk sekadar mengasah kapabilitas dinamis melalui mulai sensing, seizing, sampai transforming. Bahkan, manusia tak mampu mengidentifikasi kebiasaan negatif karena tidak terbiasa memiliki persepsi sehat atas kegagalan.
Dari sini, kemampuan mengambil risiko melemah sehingga upaya berubah selalu dilihat sebagai gangguan stabilitas kehidupan. Pada kenyataannya, teknologi berkembang begitu cepat daripada kapasitas manusia untuk memahami implikasi sosial, ekonomi, politik, kultural, dan moral melalui ragam inovasi. Salah satu solusi yang mungkin ialah membangun sebuah membangun ketahanan adaptif (adaptive resilience). Dalam ketidakpastian, ketahanan adaptif diandalkan sebagai fondasi perubahan.
Model ketahanan adaptif itu sesungguhnya sedang ingin diimplementasikan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Bungtilu Laiskodat (VBL) melalui kebijakan perubahan waktu sekolah dimulai pukul 05.00 Wita. Mengapa waktu sekolah diubah? Bagaimana dampaknya terhadap peserta didik? Apakah resiliensi hanya menjadi alasan utama untuk menutupi kebijakan yang dianggap terburu-buru tanpa kajian?
Mc Diarmid dan Zhao melalui Learning for Uncertainty: Teaching Students How to Thrive in a Rapidly Evolving World (2022) memaparkan pemikiran komprehensif tentang pembelajaran untuk berhadapan dengan ketidakpastian melalui sebuah kajian eksploratif. Kedua pengajar senior tersebut hendak memastikan sistem pendidikan mampu memberikan pengalaman, kesempatan, dan model belajar yang diperlukan untuk menghasilkan naradidik yang mampu mengembangkan pemikiran kritis, menjadi inovator kreatif, dan generasi yang diperlukan untuk memberi dampak signifikan bagi pikiran, tubuh, dan jiwa semua orang.
Uniknya, dari keseluruhan pembahasan terkait dengan kekhawatiran tentang ketidakpastian dengan peluang dan tantangan, optimalisasi teknologi dalam pembelajaran, dan keterampilan yang dibutuhkan masa kini dan nanti, keduanya menyajikan dua bahasan penting. Pertama, soal tata kelola pembelajaran, penciptaan pengetahuan, dan perubahan norma. Kedua, tentang optimalisasi upaya dan waktu sebab teknologi dapat mengambil alih peran guru karena terlalu mempersoalkan rutinitas ketimbang melakukan inovasi atau meningkatkan kompetensi.
Baca Juga: Belajar Bahasa Indonesia Melalui Korpus, Memang Bisa?Perubahan waktu: perubahan norma
Pembelajaran untuk menghadapi ketidakpastian mesti bermula dari pertanyaan, bagaimana seharusnya mempersiapkan anak-anak untuk berhadapan dengan dunia yang sulit diprediksi, bahkan belum kelihatan wujudnya? Manusia dan teknologi berpacu dengan waktu. Salah satu antisipasi penting dalam pacuan itu ialah singularitas teknologi, saat kecerdasan teknologi melampaui kecerdasan manusia dengan titik waktu hipotesis teknologi semakin tidak terkendali sehingga mengakibatkan perubahan yang tidak dapat diramalkan pada peradaban manusia.
UNESCO dalam Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education (2021) memaparkan satu bab sajian tentang menjaga dan mentransformasi sekolah. Menata kembali sekolah sebagai ruang transformasi menuju masa depan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan melalui perwujudan pedagogi kolaborasi dan solidaritas. Sekolah sebagai lembaga sosial memainkan peran penting dalam setiap budaya dan tradisi.
Sekolah tidak hanya untuk pendidikan dasar dan menengah, tetapi telah menjadi pusat masyarakat dalam memenuhi hak mereka sendiri, yang mendukung kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Sekolah mesti menjadi ruang untuk mencapai perubahan. Kekurangannya sekolah memiliki keterbatasan dalam pencapaiannya karena definisi ruang dan struktur waktu pembelajaran yang sempit.
Dengan bersumber pada pemikiran tersebut, terdapat empat elemen penting yang dapat dielaborasi untuk menata kembali dinamika belajar di sekolah dalam ketidakpastian. Pewujudan pedagogi kolaborasi dan solidaritas, peran sekolah dalam budaya dan tradisi, sekolah dan pemenuhan hak masyarakat, serta ruang dan struktur waktu pembelajaran. Semua praktisi dan ahli pendidikan sepakat bahwa model pembelajaran yang tepat membantu para pelajar untuk membangun masa depan kolektif yang menyenangkan, mampu beradaptasi dengan krisis yang tidak diketahui dan tidak pasti akan terjadi nanti.
Oleh karena itu, diperlukan shock untuk semua agar menyadari situasi terkini bahwa anak-anak kita kian dimanjakan dengan setiap sajian instan pembelajaran. Mendaratkan sebuah model pedagogi, peran sekolah dalam budaya, sekolah dan pemenuhan hak, membutuhkan dialog bersama untuk merumuskan kurikulum pembelajaran.
Salah satu elemen yang dapat dioptimalkan sedini mungkin ialah ruang dan struktur waktu pembelajaran. Mengubah waktu belajar lebih awal dapat dipandang sebagai perubahan norma, menyesuaikan dengan kebutuhan dan orientasi belajar, berpijak pada rutinitas dan kultur masyarakat setempat.
Berdasarkan kajian ilmiah ahli kesehatan dan para pemerhati pendidikan melalui ragam publikasi, salah satu aspek yang perlu diperhatikan ialah siklus biologis anak berkaitan dengan waktu tidur sebelum memulai kegiatan di sekolah. Idealnya, anak-anak di usia 13-18 tahun membutuhkan waktu tidur selama 8-10 jam.
Analoginya, jika sekolah dimulai pukul 05.00 anak-anak dapat beristirahat pada pukul 20.00 atau 21.00. Penerimaan dan penolakan atas perubahan norma ialah sebuah kewajaran. Sebuah kebijakan dapat menjadi keliru sehingga diperlukan pengkajian ulang karena sekolah merupakan wadah pengembangan kapasitas (capacity building).
School that learn: peningkatan kemampuan belajar
Pemerintah, elemen dan pemerhati pendidikan, orangtua, dan guru sering kali berbicara tentang capacity building. Pengembangan kemampuan atau kapabilitas dipandang sebagai titik pencapaian sehingga analisis data, rencana strategis, dan penyelarasan kurikulum dijadikan intervensi untuk mendorong sekolah dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pelajar.
Namun, pola intervensi teknis mekanis sering tidak mampu mendefinisikan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk kreativitas. Sekolah bahkan berpijak secara kaku pada panduan kurikulum tanpa imajinasi tentang masa depan dengan hasil akhir jalan buntu pembelajaran. Lalu, kapasitas apa yang diperlukan pelajar dalam situasi yang tidak pasti?
Dalam School that Learn, Peter Senge membuka kebuntuan jalan tersebut tentang model kemampuan yang diperlukan dan semua dimulai dari guru, administrator, dan anggota komunitas sekolah lainnya. Mereka harus belajar bagaimana membangun kapasitas mereka sendiri. Hal itu berarti pendidik dan naradidik harus mengembangkan kapasitas untuk belajar atau belajar bersama. Senge menyodorkan satu paradigma penting bahwa peningkatan yang nyata (real improvement) hanya akan terjadi jika semua bertanggung jawab atas implementasi rancangan perubahan.
Mengutip Senge, ‘It is becoming clear that schools can be re-created, made vital, and sustainably renewed not by fiat or command, and not by regulation, but by taking the learning orientation’. Sekolah dapat diciptakan kembali, diperbarui agar menjadi vital secara berkelanjutan bukan berbasis keputusan, apalagi perintah dan aturan, melainkan melalui keberanian mengambil orientasi pembelajaran.
Senge memberikan sebuah pendekatan sistem dan orientasi pembelajaran dengan sebuah frasa mendalam school that learn berpijak dari perspektif historis pendidikan. Era industri memberi asumsi-asumsi baru tentang geliat pembelajaran; bahwa anak-anak memiliki kekurangan dan sekolah harus memperbaikinya, bahwa pembelajaran ialah usaha intelektual, bahwa setiap orang harus belajar dengan cara yang sama, bahwa pembelajaran di dalam kelas sangat berbeda dengan pembelajaran di luar sekolah, dan bahwa beberapa anak cerdas sementara yang lain tidak, dan sekolah ‘dijalankan para ahli yang memegang kendali’. Kemudian pengetahuan pada dasarnya terpecah-pecah, sekolah perlu mengajarkan suatu kebenaran objektif, dan pembelajaran pada dasarnya bersifat individualistis serta kompetisi dibutuhkan untuk mempercepat pembelajaran. Atau, jika boleh ditambahkan, sekolah ideal dimulai dan diakhiri pada waktu tertentu, kurikulum harus menyasar kompetensi.
Asumsi-asumsi tentang pembelajaran itu, menurut Senge, mencerminkan keyakinan budaya yang tertanam kuat harus dipertimbangkan dan dievaluasi kembali, apabila perlu, dalam banyak kasus harus dilawan secara langsung, jika sekolah ingin mengembangkan orientasi pembelajaran yang diperlukan untuk perbaikan dan perubahan.
Peningkatan kapasitas mesti beriringan dengan peningkatan kemampuan belajar. Kemampuan belajar tidak terbatas pada penggunaan instrumen belajar, kesesuaian dengan aturan teknis praktis mempelajari disiplin ilmu tertentu, tetapi lebih dari itu, yakni kemampuan melakukan refleksi. Senge memaparkan lima disiplin, yakni system thinking, personal mastery, mental model, shared vision, dan team learning sebagai perancah esensial dan substansif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas individu maupun komunitas, tanpa melepaskan diri dari keterkaitan antara kebijakan dan impelementasinya, budaya dan kinerja sekolah, serta perubahan mendasar lainnya dalam dinamika belajar.
Quantum leap: sebuah kontrak sosial
VBL dalam setiap kesempatan menyampaikan gagasan bahwa membangun NTT membutuhkan lompatan besar dengan daya kejut untuk menyadarkan masyarakat agar tak selalu lekat dengan anekdot yang melekat, ‘nanti Tuhan tolong’.
Lompatan besar mengandaikan landasan pijakan kuat dengan tingkat elastisitas yang memenuhi syarat. Pada kenyataannya, pijakan teramat rapuh untuk melakukan lompatan yang digagas. Bagaimana tidak? Dengan persentase anggaran tinggi pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, gerakan literasi masih jauh dari perhatian, hanya menjadi inovasi komunitas pemerhati pendidikan, belum lagi permasalahan pendidikan lainnya. Sebagian elemen birokrasi memiliki model mental menyenangkan pemimpin daripada menerjemahkan visi pembangunan yang ingin diimplementasikan demi pembangunan daerah.
Mengutip Peta Jalan Pembelajaran dalam laporan The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD/organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi) berjudul The Future of Education and Skills 2030, dunia global membutuhkan visi bersama (shared vision) dalam bidang pendidikan menyongsong 2030.
Visi bersama itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk membangun dunia yang lebih baik. Visi bersama dimaksud untuk mencegah generasi muda kehilangan arah dalam tumbuh kembangnya sebagai pribadi selama menempa diri di bangku pendidikan. Peningkatan kualitas SDM dimaksud mesti berpijak pada dua fondasi utama. Pertama, merujuk pada pengetahuan, keterampilan, budi pekerti, dan nilai yang dibutuhkan para pelajar untuk bertumbuh dan berkembang, membentuk dunia yang damai.
‘Kedua, sistem dan pedoman yang diperlukan untuk mengembangkan elemen mendasar dimaksud secara efektif. Perubahan waktu belajar dalam konteks tertentu merupakan daya kejut sekaligus lompatan besar menuju perubahan. Perumusan kembali tata kelola dan orientasi pembelajaran global bersumber dari kesadaran akan ketidakpastian (sense of uncertainty).
Ketidakpastian dimaksud ditemui dalam perubahan dinamika belajar, pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim, dan ragam bencana alam yang menyertai. Dengan begitu, VBL menyadari bahwa perubahan dalam setiap situasi tidak pasti mesti bermula dari kedisiplinan diri dan organisasi karena elemen yang berharga lintas zaman ialah ruang dan waktu.
VBL melalui gagasan quantum leap-nya dalam membangun NTT sejatinya sedang membarui kontrak sosial bersama masyarakat. Kontrak sosial dimaksud memuat tujuan peningkatan kemampuan belajar, implementasi norma berbasis kultur lokal dengan prioritas peningkatan mutu pendidikan. Itu senada dengan antisipasi Mc Diarmid dan Zhao, masa depan dengan dua sisi tantangan dan peluang sedang menanti. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan intelektual, disposisi emosi, perilaku sosial, dan keterampilan untuk bertahan dan beradaptasi dalam ketidakpastian karena disrupsi teknologi serta kemungkinan teknologi mengubah pendidikan.
Seiring dengan masa pemulihan dan krisis saat ini, sebuah ruang diskursif disediakan bagi pendidik, orangtua, dan pembuat kebijakan untuk memikirkan kembali kurikulum, pedagogi, kesempatan belajar, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Sebuah kewajaran saat kebijakan dianggap terburu-buru tanpa kajian diikuti ragam kritik. Namun, tata kelola pembelajaran, penciptaan pengetahuan, dan perubahan norma menuju resiliensi tidak hanya berdampak baik bagi peserta didik, tetapi juga bagi pendidik dan orangtua. Kala dunia pendidikan global berpacu dengan waktu untuk mengubah sistem pendidikan yang peka zaman, kita masih berkutat pada jam ideal pembelajaran.
Nonaka dan Takeuchi (1995), kala memperkenalkan penciptaan pengetahuan (knowledge creation) sebagai proses dinamis menuju perubahan, membutuhkan proses untuk menerapkan tata kelola optimalisasi pengetahuan untuk perubahan besar melalui optimalisasi pengetahuan tacit dan eksplisit diikuti sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi.
Model transformasi dinamis: sebuah tawaran solusi
Dengan memperhatikan ragam saran dan kritik, dinamika perubahan waktu belajar dapat dilihat sebagai ruang awal tata kelola pendidik dan peserta didik, dimulai dari optimalisasi waktu wujud kontrak sosial peningkatan mutu pendidikan tanpa mengabaikan pedagogi sebagai elemen dasar pendidikan. Berani berubah berarti berani mengambil risiko. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan ialah model transfomasi organisasi dinamis (Moerdijat, 2021), sebuah model transformasi yang ditemukan melalui penelitian pada Yayasan Sukma dalam mengelola Sekolah Sukma Bangsa pascabencana dan pascakonflik.
Dalam konteks NTT, implementasi model transformasi itu dapat dilakukan pada sekolah-sekolah prioritas sebagai organisasi pembelajar (learning organization). Sebagai organisasi pembelajar, sekolah target dapat mengoptimalkan lima disiplin penting, yakni sistem berpikir, model mental, team learning, visi bersama, dan personal mastery. Dari sana, kemampuan dinamis (dynamic capabilities) terbentuk menuju penciptaan pengetahuan sehingga komunitas sekolah mencapai ketahanan (adaptive resilience).
Pada tahapan ini, transformasi yang diinginkan menjadi mungkin karena kapasitas inovatif terbentuk melalui sumber daya (resource), pembelajaran (learning), dan tata kelola (management). Ketika berhadapan dengan situasi kompleks dan multidimensi dengan setumpuk ketidakpastian, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan penuh kasih (compassionate leadership) baik di tingkat menengah hingga atas, untuk dapat memobilisasi sumber daya serta meneguhkan nilai-nilai fundamental menuju perubahan yang lebih baik, khususnya, dalam bidang pendidikan. Oleh Lestari Moerdijat Ketua Yayasan Sukma (Sekolah Sukma Bangsa) Anggota Komisi X DPR RI Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Sumber: https://mediaindonesia.com.


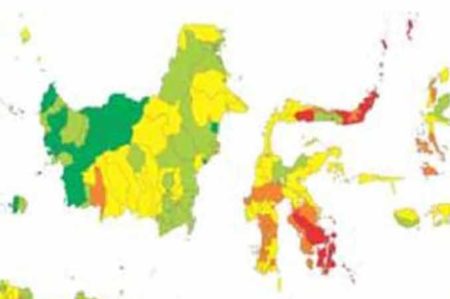

Tinggalkan Balasan