Dibalik Pembunuhan Shireen Abu Akleh
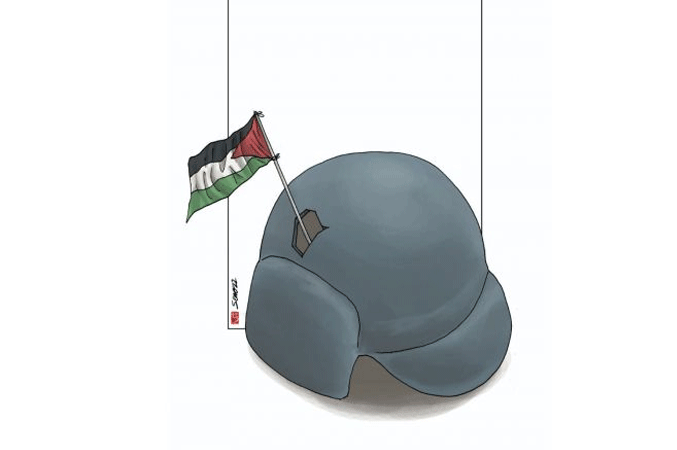
MEMBUNUH wartawan yang terkait dengan Palestina bukan hal baru bagi Israel. Sejak 2000, Israel telah membunuh 55 wartawan yang meliput konflik Israel-Palestina. Namun, pembunuhan terhadap wartawan Al-Jazeera Shireen Abu Akleh pada 11 Mei lalu sungguh di luar dugaan. Ketika meliput konflik bersenjata Israel-Palestina di kamp pengungsi di Jenin, Tepi Barat, Abu Akleh mengenakan helm dan rompi bertuliskan ‘Pers’. Namun, ia ditembak di kepala.
Bahkan, jenazahnya pun tak diperlakukan dengan hormat ketika aparat Israel menyerbu para pengusung peti jenazahnya. Tindakan brutal itu segera saja mendapat kecaman internasional. Bahkan oleh AS dan sekutu Barat, yang menuntut investigasi segera, menyeluruh, transparen, dan imparsial. Tawaran Israel untuk menyelidikinya sendiri insiden itu ditolak karena Israel punya catatan buruk soal penyelidikan terkait dengan orang Palestina.
Bagaimanapun, pembunuhan Israel terhadap wartawan dan warga sipil Palestina tak akan berhenti sepanjang akar masalah Palestina tak diselesaikan. Sejak proses perdamaian Israel-Palestina terhenti pada 2014 disebabkan Israel terus membangun permukiman Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur, Palestina terus bergolak. Pemberontakan di Jenin merupakan kelanjutan dari konflik di Kompleks Masjid Al-Aqsa antara Palestina dan aparat Israel dalam delapan bulan terakhir. Akibat terhentinya proses perdamaian, Otoritas Palestina (OP) di bawah Presiden Mahmoud Abbas yang merupakan arsitek Kesepakatan Oslo melemah. Kesepakatan Oslo berbasis pada prinsip pertukaran tanah dengan perdamaian.
Kalau Israel memenuhi komitmen mereka, mestinya pada 1998 Palestina sudah merdeka dengan wilayah mencakup Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang berdaulat penuh. Sayangnya, setelah Rabin dibunuh pada 1995 dan Israel dipimpin partai garis keras Likud yang menentang Kesepakatan Oslo, proses perdamaian tertatih-tatih hingga terhenti total. Abbas pun terkesan hanya sebagai kaki tangan Israel terutama karena Kesepakatan Oslo mewajibkan OP mengendalikan perlawanan rakyat Palestina di Tepi Barat yang diserahkan Israel untuk dikontrolnya.
Klausul perjanjian itu mau tak mau menghadapkan OP dengan rakyat mereka sendiri manakala muncul demonstrasi Palestina melawan kebijakan provokatif Israel membangun permukiman Yahudi. Posisi Abbas didukung AS dan sekutu Barat, yang berperan penting dalam menyalurkan bantuan kepada seluruh rakyat Palestina, termasuk sekitar 5 juta pengungsi yang tersebar di Jalur Gaza, Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan negara-negara tetangga. Bila Abbas mundur dari kesepakatan, yang sejauh ini tak membawa manfaat bagi Palestina, AS dan Barat akan menarik dukungan politik dan keuangan. Bahkan, Israel pun akan membekukan OP dan mungkin mengusir Abbas dari Ramallah, ibu kota OP. Alhasil, Abbas serbasalah.
Baca Juga: Mewaspadai Tekanan Stagflasi GlobalPadahal, Abbas hanya akan mendapat legitimasi kalau proses perdamaian digulirkan kembali, yang dapat menimbulkan optimisme rakyat Palestina akan masa depan yang bermartabat. Dalam menghadapi insiden pembunuhan Abu Akleh dan konflik di Kompleks Al-Aqsa, UE dan AS memang mengecam Israel, tetapi tak terdorong untuk mendesak Israel maju ke meja perundingan.
Bahkan, kecaman itu lebih terlihat sebagai upaya menenangkan publik dalam negeri dan memenangkan hati bangsa Arab terkait dengan perang Ukraina. Aktivis HAM di AS dan UE sangat marah atas pembunuhan Abu Akleh. Di luar itu, AS dan NATO juga sedang memobilisasi dukungan internasional melawan Rusia dengan isu, di antaranya kejahatan perang Rusia di Ukraina.
Lalu, di tengah terhentinya proses perdamaian, pada 2020 empat negara Arab–Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan–menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accord (Perjanjian Ibrahim). Palestina menyebut perjanjian itu sebagai tusukan dari belakang. Frustrasi Palesina meluas karena sejak 2007 Israel memblokade total Jalur Gaza yang dihuni sekitar 2,5 juta warga yang sangat miskin. Di Jerusalem Timur, ketika banyak warga Palestina diusir dari rumah mereka, Israel terus memperluas permukiman Yahudi untuk mempercepat yahudinisasi di kota yang oleh umat Islam dipandang sebagai kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, di kota yang hendak dijadikan ibu kota negara Palestina merdeka. Tahun lalu, di tengah serangan aparat Israel terhadap muslim Palestina di Masjid Al-Aqsa menyusul protes Palestina atas rencana penggusuran rumah-rumah warga Palestina di Sheikh al-Jarrah di pinggiran Jerusalem Timur, protes berujung pada perang Hamas-Israel.
Tidak kurang dari 260 warga sipil Palestina tewas dan ribuan kehilangan tempat tinggal. Serangan itu juga disengaja menyasar infrastruktur vital Gaza untuk melemahkan perjuangan Hamas. Israel berharap hukuman yang dijatuhkan itu akan mendorong warga Gaza memberontak terhadap milisi Islam militan itu. Namun, meskipun warga Gaza harus membayar ongkos yang sangat mahal, dukungan pada Hamas tidak berkurang. Toh, lepas dari hasil yang didapat, perjuangan Hamas dipersepsikan sebagai perlawanan meraih martabat Palestina. Malah di Tepi Barat, markas OP dari faksi Fatah, dan Jerusalem Timur, simpati pada Hamas meluas.
Konflik di Jenin dan pembunuhan Abu Akleh tak bisa dilepaskan dari situasi sosial-politik di Palestina sebagaimana dipaparkan di atas. Di tengah frustrasi Palestina itu, April lalu empat pemimpin negara Arab yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel, Mesir, UEA, Maroko, dan Bahrain, mengadakan pertemuan dengan pemimpin Israel di Kota Aqaba, Israel. Beberapa hari sebelumnya, pemimpin UEA, Mesir, dan Israel berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir.
Pertemuan-pertemuan itu bertujuan mengantisipasi pemulihan perjanjian nuklir Iran (JCPOA) dengan lima anggota DK PBB plus Jerman (P5+1) yang ditentang negara-negara Arab Teluk, Mesir, dan Israel. Mereka menganggap pulihnya JCPOA, dengan Iran dibebaskan mengekspor minyak dan gas ke pasar global sebagai kompensasi mereka mengekang program nuklir mereka, akan membuat Teheran leluasa menjalankan politik ekspansi mereka di kawasan dengan mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Arab.
Bagaimanapun, dalam pertemuan-pertemuan itu, Yordania, salah satu negara Arab yang telah berdamai dengan Israel sejak 1994, menolak hadir sebagai protes terhadap kebijakan Israel di Jerusalem Timur, khususnya terkait dengan Masjid Al-Aqsa. Sesuai dengan perjanjian perdamaian itu, pengelolaan masjid suci tersebut berada di bawah otoritas Yordania.
Konflik di Al-Aqsa yang bermula dari serangan sporadis Palestina di berbagai kota di Israel pada akhir Maret menewaskan 14 warga sipil Yahudi. Tentara Israel membalas dengan melakukan pembunuhan terhadap puluhan warga Palestina yang dicurigai terkait dengan para pelaku serangan itu. Ketegangan Israel-Palestina pun meningkat dengan cepat. Apalagi aparat Israel mengawal para orang Yahudi militan memasuki Kompleks Masjid Al-Aqsa untuk merayakan Passover dengan menyembelih hewan di tempat itu. Orang Palestina marah karena aksi-aksi mereka dicurigai bertujuan merobohkan Masjid Al-Aqsa dalam janga panjang untuk dibangun kembali Bukit Kuil yang dihancurkan tentara Romawi pada abad kedua.
Mereka percaya Masjid Al-Aqsa dibangun persis di atas reruntuhan Bukit Kuil dan, terlebih, masjid itu jadi pengingat akan eksistensi Palestina di kota yag direbut Israel dalam Perang 1967. Israel pun terus berjuang untuk menghilangkan semua jejak dan atribut Palestina di Jerusalem Timur. Serangan terhadap peti jenazah Abu Akleh yang dibalut bendera Palestina merupakan bagian dari upaya itu. Bendera, yang di bawahnya semua komponen Palestina bersatu, dipandang berbahaya karena juga menginspirasi kemerdekaan Palestina. Bagi Israel, Jerusalem Timur, tempat bercokol Tembok Ratapan, ialah simbol identitas negara Yahudi.
Bagaimanapun, kunjungan-kunjungan orang Yahudi militan yang diam-diam disokong pemerintah untuk menuntaskan program yahudinisasi Jerusalem bertentangan dengan perjanjian yang dibuat dengan Yordania. Perjanjian itu membolehkan kunjungan orang Yahudi ke tempat itu selama bukan untuk tujuan berdoa atau melakukan upacara keagamaan. Faktanya, kunjungan untuk tujuan yang tak dibolehkan itu terus terjadi. Itu disebabkan PM Israel Naftali Bennet dikenal sebagai pendukung pembangunan permukiman Yahudi di daerah pendudukan dan pemerintahan koalisinya dibentuk dengan dukungan partai-partai agama.
Serangan ke Jenin, yang berujung pada pembunuhan Abu Akleh, ialah opsi yang dipilih Bennett untuk menunjukkan ia sama kerasnya dengan Netanyahu dalam berurusan dengan Palestina. Tujuannya mempertahankan pemerintahannya di saat Partai Arab List, anggota kabinet, telah mengundurkan diri dari pemerintahan. Bisa jadi partai lain anggota koalisi juga akan mengundurkan diri karena pemerintahan Bennett telah kehilangan kredibilitas dan legitimasi internasional. Namun, kematian Abu Akleh tak akan bermakna kalau pengorbanannya tak berujung pada kemerdekaan Palestina. Oleh: Smith AlhadarPenasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) (*)




Tinggalkan Balasan